1. Di Tepi Pantai
Di sebuah pantai terpencil, dua perempuan saling menatap tajam.
Matahari yang tinggi di langit menyinari mereka dengan sengatan yang seolah ingin membunuh.
Panas.
Tidak—itu terik membakar.
Cahaya matahari yang kejam dan tak kenal ampun menghujani pasir panas, sementara kedua perempuan itu berdiri bertelanjang kaki. Sebenarnya, mereka bahkan nyaris tanpa busana, meski tak benar-benar telanjang bulat.
Mereka hanya setengah telanjang. Masing-masing membalutkan semacam kain kasar di dada dan pinggang mereka. Tapi sebenarnya, itu bukan kain kasar. Yang mereka kenakan adalah bahan bukan-tenun, dibuat dari kulit kayu yang direbus lalu ditumbuk. Karena tidak ditenun dari bulu binatang, atau dari batang dan daun tumbuhan, maka itu tidak bisa disebut kain dalam arti biasa.
Rambut keduanya cukup panjang. Salah satu mengikat rambutnya menjadi kepangan, sementara yang lain menguncirnya ke kiri dan kanan. Tali yang mereka gunakan juga dibuat dari serat kulit kayu yang dipilin.
Ada cahaya tajam dalam tatapan mereka saat keduanya merendahkan tubuh, menekuk lutut, dan mencondongkan badan ke depan. Mereka menggoyangkan lengan, menggerakkan satu tangan ke depan lalu segera menariknya kembali, berpindah-pindah beban dari satu kaki ke kaki lain. Seolah-olah mereka tengah saling mengamati reaksi satu sama lain.
Tubuh mereka basah kuyup oleh keringat. Butiran keringat yang tampak seperti manik-manik kaca muncul di kulit cokelat mereka, lalu mengalir turun dari dagu dan lengan—tak berhenti barang sedetik pun.
Tak ada peringatan. Tiba-tiba, perempuan dengan rambut dikepang menyerang perempuan dengan rambut yang dikuncir ke samping.
Perempuan berkepang itu menyerbu dari posisi rendah, mencoba meraih lawannya dan menjatuhkannya secepat mungkin. Pasir seharusnya bisa sedikit menghambat langkahnya, tapi serangannya melesat secepat kilat. Itu bukan sekadar serudukan cepat—itu serudukan iblis. Tidak, ini serudukan iblis yang sesungguhnya.
Perempuan yang dikuncir terkejut, menelan ludah. Matanya membelalak, dan seolah yang bisa ia lakukan hanyalah menerima serudukan itu.
Atau begitulah kelihatannya. Tapi perempuan yang dikuncir tak hanya berpikir, Wah, dia cepat juga. Dia malah menyeringai. Dan bukan cuma itu—dia benar-benar berkata, “Heh!”
Pikiran Wah, ini bisa jadi buruk melintas sejenak di benak si perempuan berkepang yang sedang menerjang. Tapi perempuan yang dikuncir sudah memperhitungkan semuanya—dari gerakan, waktu, hingga arah serangan.
Dengan tepat, ia meraih kepala lawannya, menekannya ke bawah, lalu melompati tubuhnya.
Perempuan yang dikuncir melompat ringan, dan si perempuan berkepang hanya bisa menggertakkan gigi saat tubuhnya terdorong ke depan oleh momentumnya sendiri. Hanya itu saja sudah cukup membuatnya merasa kalah, tapi perempuan yang dikuncir belum puas.
Yang ini juga aku ambil, seolah itulah yang ia katakan, saat ia mengayunkan kaki kirinya ke belakang.
Saat itu, si rambut kuncir melayang di udara, sementara perempuan berkepang nyaris terjerembab ke depan. Punggung mereka saling membelakangi.
Kaki kiri perempuan yang dikuncir melayang makin dekat ke punggung perempuan berkepang. Kelima jari kakinya terbuka lebar, seolah-olah itu adalah jari tangan. Kalau ini adalah permainan batu-gunting-kertas, maka ia sedang melempar kertas. Tidak, bahkan lebih dari itu—ini adalah kertas sempurna yang menjadi nyata. Tak ada kertas yang lebih ideal daripada ini.
Jempol kakinya menyentuh punggung perempuan berkepang.
Untuk lebih tepatnya, jempol itu menyentuh titik di antara bahu kiri dan kanan, tepat di tempat simpul kain penutup dadanya diikat. Setelah jempol itu menyentuh simpul, jari kaki kedua pun ikut menyusul.
Bukan cuma jempol, jari yang itu juga? Duh, ini gawat.
Perempuan berkepang mengeluarkan teriakan aneh, “Mobah!” dan berusaha memutar tubuhnya. Sayangnya, sudah terlambat. Dengan kejam tanpa belas kasihan, perempuan yang dikuncir menjepit simpul kain itu menggunakan jempol dan jari kaki telunjuknya.
“No-chah!”
Sambil meneriakkan semacam pekikan perang, perempuan yang dikuncir berputar seperti pusaran angin.
Dan dengan itu, kain penutup dada pun terlepas.
Wajah perempuan berkepang nyaris mencium pasir yang menyengat panas, namun tepat sebelum itu terjadi—“Ngh, nah!”—ia menahan tubuhnya dengan kedua tangan, mencegah akhir yang menyedihkan itu.
Kalau dia mencoba berkata, Tapi, sebenarnya sih, aku nggak kesal-kesal amat, maka itu jelas bohong.
Bukan hanya dijadikan rintangan lompatan, dadanya kini terbuka lebar, dan posisinya sekarang tampak seperti orang yang sedang mencoba push-up—tanpa alasan yang jelas.
Ohhh, kenapa sih?! Kenapa semua ini terjadi?!
Meluapkan amarahnya menjadi tenaga ledakan, perempuan berkepang berteriak, “Kwomuh!” lalu meluncur ke udara hanya dengan kekuatan kedua lengannya.
Perempuan yang dikuncir terkikik pelan, menyeringai sambil mengangkat sedikit kaki kirinya.
Kain penutup dada yang kini tergantung di jari-jari kaki itu bergoyang ke sana kemari.
“Susuuuumu keliatan, Yumeryun~ Heheheheh…”
“Grrrr…”
Yume—alias Yumeryun—mengertakkan gigi sampai wajahnya yang sudah cokelat karena matahari berubah jadi merah gelap.
Bukan karena malu dadanya terlihat. Hal semacam itu tidak penting baginya. Yang benar-benar membuatnya terpukul adalah kenyataan bahwa serudukan yang ia kerahkan dengan segenap tenaga barusan sama sekali tak membuahkan hasil.
Namun begitu, Yume mengangguk pelan. “…Belum selesai,” gumamnya.
Ia mengembuskan napas. Berdiri tegak, mengambil posisi bertahan dengan satu kaki di depan dan satu lagi di belakang, lalu mengendurkan ketegangan tubuhnya.
“Pertarungannya belum selesai, Momo-san. Skornya masih 2-1, tahu?”
“Iya.”
Momohina—alias Momo-san—menjatuhkan kain penutup dada yang tadi digenggam dengan jari kakinya, lalu menurunkan kaki kirinya ke pasir.
“Itu baru semangat yang benar, Yumeryun.”
Cara dia berdiri tampak aneh. Sekilas, seperti penuh celah untuk diserang dari berbagai arah, tapi kalau benar-benar mencoba menyerang, dia akan menghindar dengan mudah.
Menurut penilaian Yume, Momohina itu licin. Licin, lentur, dan lembut. Tapi di saat dibutuhkan, crack, pow—ia bisa berubah keras. Ia bisa meledak dengan kekuatan dahsyat—boom, bam, kaboom—dan kadang, itu terjadi tanpa peringatan.
Momohina bisa bergerak sesuka hati—secepat atau selambat yang ia mau—dan karena itulah, mendekatinya bukan perkara mudah.
Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi itu?
Saat Yume mengajukan pertanyaan itu pada dirinya sendiri, jawaban yang muncul kurang lebih berbunyi, “Hmm, mungkin… semacam begitu, ya.”
Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini termasuk hal-hal yang masuk kategori: “Jangan dipikirkan. Rasakan!”
Begitu ia mencoba merangkai esensinya dalam kata-kata, semuanya justru menguap. Ia harus merasakannya. Merasa. Dan contohnya, ada tepat di hadapannya.
Yume membayangkan Momohina. Menjadi Momohina. Yume adalah Momohina. Momo-san.
Yume = Momo-san.
Ia mulai melangkah. Yume berjalan menyusuri pantai. Momohina berdiri di sisi seberang.
Siapa pun yang lebih dulu berhasil meraih kain penutup dada dan pinggang lawannya, dialah pemenangnya. Itu adalah aturan pertarungan ini. Tapi itu bukan masalah besar.
Telapak kakinya merasakan lembut dan panasnya pasir. Suara ombak terdengar. Angin berhembus dari selatan, namun tak cukup kencang untuk membuat rambut panjangnya berkibar.
Momohina tersenyum, matanya tetap menatap Yume. Yume sendiri tidak tersenyum. Tatapannya tertuju pada Momohina—tanpa senyum, tanpa tawa. Mereka melihat hal yang berbeda, tapi mungkin, pada dasarnya, mereka sama.
Yume terhubung dengan Momohina. Bukan secara fisik, tapi ada semacam ikatan. Saat ini, kalau ada yang mencubit pipi kanan Momohina, Yume-lah yang akan merasakan sakitnya.
Jarak antara keduanya menyempit.
Sudah hampir waktunya.
Yume—dan juga Momohina—mengulurkan tangan kanan mereka, sedikit terbuka. Punggung tangan mereka saling bersentuhan. Hampir seperti jabat tangan. Itu adalah isyarat.
Momohina langsung mengayunkan tangan kirinya ke depan. Tangan kanan Yume mendorong lengan kiri Momohina ke arah luar, dan tangan kanan Momohina mengarah ke rahang Yume. Yume menepisnya dengan tangan kiri.
Momohina mencoba menebas sisi leher Yume dengan tangan kirinya. Yume mengalihkan tebasan itu secara diagonal ke atas menggunakan siku kiri. Momohina membalas dengan sapuan kaki kanan ke arah lutut kiri Yume. Yume segera menarik kaki kirinya ke belakang, menunggu hingga kaki kanan Momohina melewatinya.
Mereka bertarung dalam jarak amat dekat. Nyaris bersentuhan. Lengan dan kaki mereka saling berkelit dan bertabrakan. Mereka bersinggungan. Saling menyentuh ringan.
Tak perlu mengepalkan tangan kecuali saat benar-benar menghantam. Kadang, jari bisa digunakan layaknya cakar. Bisa juga untuk mencengkeram. Dan menyikut, tentu saja, sah-sah saja. Tendangan dari lutut, tendangan ujung kaki, tumit, injakan—dan masih banyak lagi.
Ada banyak cara. Tak terbatas.
Karena itulah, jika ia terus berpikir, Kalau dia begini, aku harus begitu, dan mencoba merencanakan semuanya, tubuhnya tak akan mampu merespons.
Tubuhnya harus bergerak sendiri.
Dan memang untuk itulah semua latihan ini dilakukan.
Yume mendorong kuat bahu kiri Momohina dengan tangan kanannya. Ia berusaha meraih kain penutup dada Momohina dengan tangan kiri, tapi Momohina segera menahannya dengan tangan kanan.
Yume mencoba memutar ke belakang Momohina dari arah kanan. Untuk menghindarinya, Momohina memutar tubuhnya ke arah sebaliknya.
Yume menghentikan gerakan ke kanan dan berpindah ke kiri. Atau lebih tepatnya, seolah-olah berpindah ke kiri—lalu berhenti sejenak.
Itu menciptakan celah.
Yume menarik napas dalam-dalam. Faktanya, selama bergerak tadi, ia hampir tak sempat bernapas. Terutama untuk menarik napas—itu mustahil dilakukan. Dan Momohina pun sama.
Yume hanya mengambil jeda sebentar untuk bernapas. Tapi Momohina tidak.
Yume mempercepat gerakan. Ia sudah bernapas—berarti ia bisa bergerak. Lebih cepat. Dengan tenaga lebih besar.
Yume melepaskan tendangan memutar ke kanan. Momohina menahannya dengan mudah menggunakan lengan dan kaki kirinya.
Yume tidak menarik kembali kaki kanannya. Ia langsung melancarkan tendangan memutar ke atas, lalu ke tengah, dan ke tengah lagi. Atas, tengah, atas, bawah, bawah—Yume mengganti-ganti ritme tendangannya.
Keseimbangannya yang stabil, poros tubuhnya yang tidak goyah—itu adalah hal-hal yang pernah Momohina puji.
Tubuh Yume sedikit lebih besar, dan pada jarak ini, di mana tangan mereka tidak bisa saling menjangkau, ia bisa menekan Momohina.
Namun, ia tak bisa menembus pertahanan Momohina.
Sekalipun ia mencampur berbagai jenis tendangan—tendangan memutar, tendangan lurus ke depan, ke belakang, ke samping, dengan kombinasi dan variasi—semuanya gagal.
Tendangan terbang akan terlalu membuka celah. Tendangan lutut justru akan membawa tubuhnya masuk ke jarak serang efektif milik Momohina—dan itu jelas berbahaya.
Semakin banyak Yume menyerang, semakin sedikit kartu yang tersisa untuk dimainkan. Seolah-olah setiap serangan justru mengeliminasi pilihannya satu per satu. Dan tiap kali menyerang, Yume makin terdesak ke pojok.
Dia kuat.
Yume tak bisa menahan rasa kagumnya—lagi. Momohina sejak awal memang kuat, tapi sejak mereka mulai berlatih bersama di pulau ini, kekuatan itu tumbuh lebih jauh lagi. Momohina kini berada jauh di depan Yume.
Meski Yume mengejarnya sekuat tenaga, punggung Momohina terasa semakin menjauh.
“Koh!”
Yume mengangkat kaki kanannya dengan tenaga begitu besar hingga tubuhnya nyaris melengkung ke belakang. Jika Momohina tidak menundukkan tubuhnya tepat waktu, ujung jari kaki Yume pasti sudah menghantam rahangnya.
Tapi Yume tahu Momohina akan menghindar. Karena itu, ia tidak hanya melengkung ke belakang—ia langsung berguling. Ada teknik berburu bernama Weasel Somersault. Yume menggunakannya.
Bukan hanya sekali. Ia berguling dua kali berturut-turut, menjauh dari Momohina.
Akhirnya, ia bisa bernapas. Meskipun tetap tidak lega. Tenggorokannya perih. Paru-parunya seperti terbakar. Jantungnya berdebar sekeras-kerasnya. Dan keringatnya mengucur seperti air bah.
“Kamu udah jago juga sekarang, Yumeryun.”
Momohina juga berkeringat. Tapi tidak sampai seperti akan tenggelam dalam peluh sendiri seperti Yume. Meski udara panas menyelimuti mereka, wajah Momohina tetap terlihat tenang.
“Waktu pertama kali kita datang ke pulau ini, kamu tuh… beeeener-berer nggak ada apa-apanya dibanding aku. Urgh. Bukan ‘berer’, ya. Bener, kan?”
Momohina meletakkan tangan di pinggang dan tertawa kecil. Semua ini bukan masalah besar baginya. Ia bukan tipe orang yang suka khawatir. Ia selalu lapang dada dan santai.
Selama bersama Momohina, Yume nyaris bisa melupakan bahwa mereka sedang berada di pulau terpencil. Yume bisa tetap waras di pulau ini karena ada Momohina. Tanpa Momohina, ia tak akan bisa sekuat sekarang. Momohina yang mengajarinya, melatihnya. Kalau Yume tak ingin lemah, maka ia harus menjadi kuat. Dan ia bisa jadi kuat. Momohina membuatnya percaya akan hal itu.
Yume merentangkan punggungnya, membuka kuda-kuda selebar bahu, dan membiarkan kedua lengannya menggantung lemas.
“Tinju Hewan… Beruang!”
“Baiklah, kalau begitu aku pilih…”
Momohina melangkahkan kaki kiri ke depan, menaruh kaki kanannya ke belakang, berjarak kira-kira selebar dua kepalan. Ia menekuk lututnya, menurunkan pusat gravitasi. Lalu ia condong ke depan, membungkukkan punggung, dan menaruh tangannya di atas pasir pantai.
“Tinju Hewan… Anjing!”
Rambut Momohina berdiri. Grrrr! Suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya.
Yume meraung. Grawwwwr! Ia benar-benar jadi beruang sekarang.
Sang anjing menerjang sang beruang. Sang beruang mengayunkan lengannya dengan liar untuk mengusir si anjing. Si anjing melompat ke sana kemari, menghindari serangan beruang dan mencoba menggigit lehernya.
Beruang dan anjing itu bergumul. Kadang si anjing yang berada di atas, kadang si beruang.
Mereka terpisah. Anjing itu lari; beruang mengejarnya. Anjing itu berbalik, dan beruang itu justru melarikan diri. Tapi akhirnya, beruang itu melancarkan serangan balasan, dan si anjing mencoba menjaga jarak.
“Tinju Hewan… Ular!”
Lengan si beruang bergerak lincah, seperti ular. Bukan hanya lengannya—seluruh tubuh si beruang, tidak, tubuh Yume, berubah menjadi seekor ular. Ia menerjang si anjing dengan serangan seperti tangan-tangan ular.
“Tinju Hewan… Tupai!”
Tiba-tiba, si anjing—tidak, Momohina—berubah menjadi seekor tupai. Tupai itu kecil dan gesit. Ia bergerak seperti baling-baling angin yang berputar, menghindari semua serangan ular.
“Baiklah! Tinju Hewan… Kalajengking!”
“Aku pakai Tinju Hewan… Katak!”
“Tinju Hewan… Lebah!”
“Tinju Hewan… Kupu-kupu!”
“Kupu-kupu?!”
“Salah! Ubur-ubur!”
“Ubur-ubur?!”
“Bukan, Gurita!”
“Kuda nil!”
“Badak!”
“Burung beo!”
“Burung beo?! Gajah!”
“B-Buaya!”
“Telur!”
“Telur?!”
“Nyaa! Tinju Hewan, Kucing!”
“Kalau begitu, Lalat!”
“Fungh!”
“Munah!”
“Dohh!”
“Undakatsuohhh…!”
Pikirannya menguap satu per satu. Tak ada ruang untuk memikirkan hal lain. Tubuhnya sudah kelelahan, tentu saja. Bisa dibilang, dia sangat kehabisan tenaga. Namun, dia tak pernah benar-benar berhenti. Entah bagaimana, saat ia menangkis serangan-serangan Momohina, atau menghindarinya dengan putus asa, kekuatannya tiba-tiba kembali. Dan saat itulah, ia segera melancarkan serangan balasan. Kalau tidak menyerang ketika ada kesempatan, ia akan terus-terusan menerima pukulan.
Dalam pertarungan, ada sebuah aliran. Kau harus bisa membacanya. Menyatu dengan arusnya. Yume benar-benar ingin menguasai seni menunggangi arus itu. Tapi untuk saat ini, itu masih terlalu sulit baginya. Yume belum mampu menciptakan arus sendiri saat menghadapi lawan seperti Momohina.
Dia bisa mengikuti arus yang sudah ada, dan mencoba sedikit mengarahkannya agar lebih menguntungkan dirinya. Bukan hal yang mudah. Momohina selalu mengamati Yume dengan tenang. Melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Untuk memahami keseluruhan lawannya, tapi juga detail-detail terkecilnya. Bukan secara terputus-putus, tapi terus menerus, dengan hati-hati. Sebuah pemahaman yang menyeluruh dan membungkus segalanya.
Selama masa latihannya bersama Momohina, Yume setidaknya telah menemukan petunjuk awal untuk teknik itu. Berkat itu, sekarang ia pun bisa mengikuti arus yang sama.
Entah sejak kapan, matahari mulai terbenam.
Setelah entah berapa kali serangan dan pertahanan silih berganti, Yume menangkap simpul kain dada Momohina dengan ibu jari kaki kirinya. Dengan lihai, dia gunakan ibu jari dan jari telunjuk kakinya untuk melonggarkan simpul kain itu.
Di saat yang bersamaan, tangan kiri Momohina mencengkeram kain pinggang milik Yume dan menariknya dengan kasar.
Siapa pun yang berhasil merebut kain dada atau kain pinggang lawannya lebih dulu, ialah yang menang.
“Hee! Sepertinya aku menang!”
“Unnyoh! Yume kalah~!”
Cahaya matahari senja mewarnai tepi air dengan rona jingga. Tak ada yang bisa menghentikan bayangan yang perlahan meluas, mencaplok lebih banyak wilayah tiap detiknya. Dunia yang mereka jejaki itu kini tanpa malu mengenakan warna-warna malam.
Mereka berdua terbaring telentang di atas pasir. Yume telanjang bulat. Hanya bagian bawah tubuh Momohina yang masih tertutup kain pinggangnya. Tapi, memangnya kenapa? Hanya mereka berdua di pulau ini. Sebelum mereka terdampar, tempat ini benar-benar tak berpenghuni.
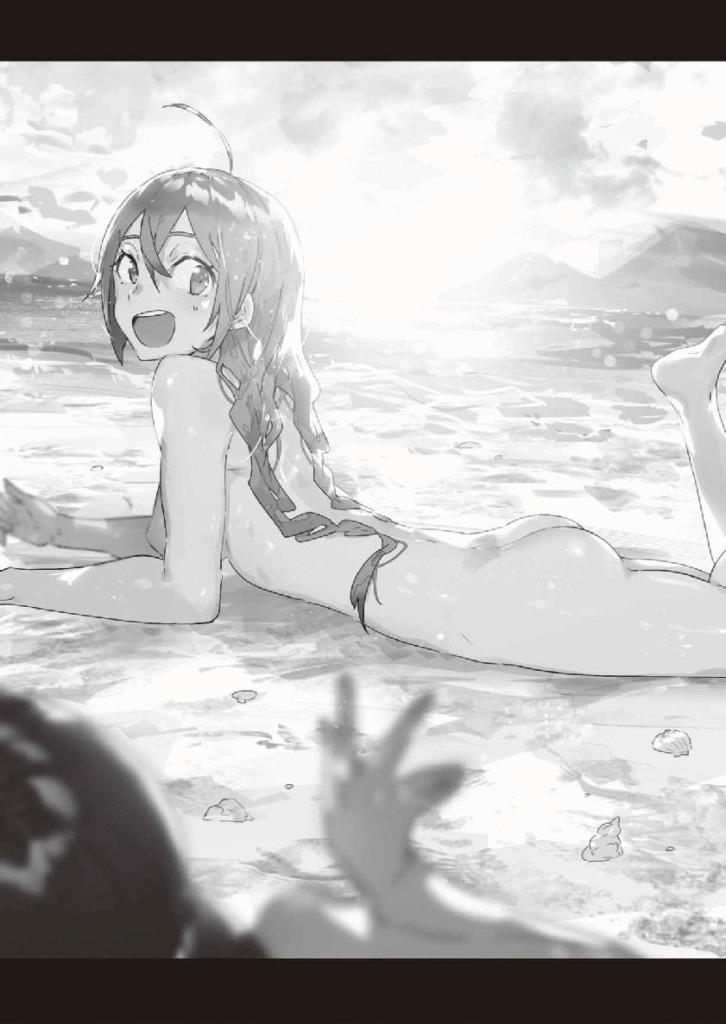
“Kita latihan banyak banget hari ini, ya? Kerja bagus, Yumeryun.”
“Masih panjang jalannya. Berapa kali pun kita sparing, Yume tetap ngerasa nggak bakal bisa menang.”
“Oh, ya? Aku nggak yakin, deh. Bisa jadi lebih seimbang dari yang kamu kira.”
“Hmm. Seimbang, ya?”
“Yumeryun, pantatmu empuk banget, loh.”
“‘Pantat empuk’ tuh maksudnya buddlywut, ya?”
“Yaaa, bener banget. Buddly-uddly-wut-wut-wut.”
“Pantatmu juga empuk, Momo-san.”
“Nahhh, pantatku nggak ada apa-apanya dibanding punyamu, Yumeryun.”
“Eh, kamu lagi muji Yume, ya?”
“Yup, bener. Karena pantat empuk itu yang terbaik, tahu?”
“Oh, gitu?”
Begitu Yume bilang itu, suara keroncongan terdengar keras. Ia mengusap perutnya. Kali ini bunyinya lebih kencang.
“…Oh. Yume lapar!”
“Baiklah!”
Momohina langsung bangkit seolah tubuhnya nggak ngerasa berat sama sekali. Padahal habis latihan berat, tapi dia tetap bisa bergerak ringan. Hebat banget. Dia benar-benar kayak monster.
Yume duduk perlahan. Jujur aja, dia pengin bisa bangkit secepat itu juga, tapi ada beberapa bagian tubuh yang masih sakit.
Harus terus dilatih, nih.
Tapi kalau dipikir-pikir, waktu pertama kali datang ke pulau ini, Yume mungkin udah nggak bisa gerak sama sekali di titik kayak gini.
“Ayo cari makan!”
Momohina masih sanggup langsung nyelonong masuk hutan habis latihan sampai senja, dan Yume sekarang udah bisa—entah gimana caranya—ikutin dia.
Yume memang makin berkembang.
2. Kekuatan Akan Membuatku Kuat
Mantis-go berlayar meninggalkan markas utama Perusahaan Bajak Laut K&K di kota pelabuhan Roronea, yang terletak di Kepulauan Zamrud, dan memulai pelayaran ke arah timur.
Secara garis besar, mereka menuju ke timur, lalu terus ke arah timur lagi, melintasi apa yang disebut sebagai Laut Biru, atau Samudra Biru. Jika mereka mengikuti Kepulauan Karang hingga ke ujung timur, maka pantai barat Benua Merah akan terlihat.
Benua Merah dihuni oleh berbagai macam ras: orang-orang berekor, orang-orang berlengan panjang, orang-orang bertelinga tinggi, orang-orang bermata tiga, orang-orang bermata banyak, orang-orang berkepala besi, orang-orang berbulu lebat, orang-orang berkulit duri, orang-orang bertulang bulu, orang-orang tanpa bayangan, orang-orang berbentuk bola, dan masih banyak lagi. Ada banyak negara di sana, dan masing-masing dipimpin oleh rajanya sendiri.
Perjalanan dari Kepulauan Zamrud ke Kepulauan Karang saja sudah sangat jauh. Dari sana ke Benua Merah jaraknya bahkan lebih jauh lagi. Namun, sekitar dua ratus tahun yang lalu, ketika sebuah armada dari Kerajaan Arabakia menemukan Kepulauan Karang, pulau-pulau itu sudah berpenghuni, dan bahkan telah memiliki pelabuhan. Rupanya, orang-orang bermata banyak dari Benua Merah telah lebih dulu mencapai Kepulauan Karang.
Dulu, orang mengira bahwa hanya ada satu daratan besar di dunia ini yang disebut Grimgar. Itu adalah pengetahuan umum—dan ternyata, sepenuhnya keliru.
Setelah mengetahui keberadaan Benua Merah, orang-orang mulai menyebut sisi Laut Biru yang satu ini sebagai Grimgar. Sejak itu, sejarah Grimgar dan Benua Merah mulai berubah, dengan Kepulauan Karang sebagai titik persimpangan di antara keduanya. Sebelum mereka hancur, kerajaan Arabakia dan Ishmal sempat menjalin hubungan dengan beberapa negara di Benua Merah, dan berdagang dengan mereka.
Benua Merah bukanlah legenda, fiksi, mimpi, atau ilusi.
Namun begitu, Benua Merah terletak sangat jauh, dan lautan terbuka dipenuhi ancaman serta bahaya. Di tengah samudra, tempat tak ada tempat berlindung, bahkan badai yang terlalu sering terjadi pun bisa membawa maut. Tanpa nakhoda dan navigator yang terampil dan berpengalaman, juga kru yang solid, mustahil untuk mencapai Kepulauan Karang—apalagi Benua Merah. Bahkan kapal-kapal yang sudah berkali-kali menyeberang ke sana tetap bisa tenggelam bila memang sudah waktunya.
Yume telah berulang kali diperingatkan bahwa tak ada jaminan keselamatan, dan ia memahaminya. Tapi apakah ia benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan? Mungkin ia memang tak memikirkannya terlalu dalam. Sementara itu, Momohina dan para kru Mantis-go di bawah komando Ginzy bertindak seolah mereka hanya berlayar seperti biasa. Tak ada sedikit pun tanda kekhawatiran. Kalau pun ada yang terasa, justru antusiasme. Yume bahkan tak pernah terpikir sesuatu yang buruk akan terjadi.
“Udah dua tahun, ya…?”
Yume menggores-goreskan tongkat pengaduk api ke pasir, berniat menulis angka, tapi entah kenapa justru membentuk pusaran.
Mereka berburu sampai tengah malam, lalu membawa hasil tangkapan mereka kembali ke pantai—sejumlah tupai terbang hitam, rakun bermata besar, dan seekor burung-naga berjalan. Yume membedah semuanya di sana, sementara Momohina menyalakan api. Bagian-bagian dari tupai terbang hitam dan rakun bermata besar yang bisa dimakan setelah dimasak sudah mereka santap. Hanya burung-naga berjalan yang mereka siapkan untuk dimasak, tapi karena mereka berdua sudah cukup kenyang, mereka memutuskan tidak melanjutkannya.
Momohina berbaring terlentang. Yume melirik ke arahnya, mengira dia sudah tertidur karena begitu diam, tapi ternyata matanya masih terbuka.
Yume menggambar lebih banyak pusaran di pasir dengan tongkatnya.
“Udah dua tahun, ya? Atau Yume salah? Soalnya pas baru nyampe sini, Yume nggak ngitungin bener-bener.”
“Kayaknya sih bener,” jawab Momohina, samar.
Dalam perjalanan menuju Kepulauan Karang, Mantis-go dihantam badai besar. Yume tidak tahu banyak soal laut, tapi tampaknya mereka apes karena terjebak topan, atau siklon, atau angin ribut—entahlah apa namanya, yang jelas badai semacam itu biasanya nggak muncul di musim itu. Mereka nggak bisa berbalik arah dan kabur, jadi satu-satunya pilihan adalah bertahan sampai badai berlalu. Di dalam kapal Mantis-go, semua bekerja keras untuk menghadapinya. Memindahkan kargo, mengikat barang-barang—Yume membantu sebisanya. Kalau dia nggak sibuk, rasa gelisah itu jadi tak tertahankan.
“Badai itu… rasanya kayak baru kemarin.”
“Aku udah lupa total soal itu. Ho, ho, ho.”
Berbeda dengan Momohina yang tertawa aneh, Yume sama sekali tidak mungkin melupakannya.
Angin mendadak bertiup kencang, hujan mengguyur Mantis-go tanpa ampun, dan kapal itu terombang-ambing hebat. Tapi bukan sekadar bergoyang—rasanya lebih seperti jungkir balik dan diputar-putar.
Waktu itu, hanya ada kru inti yang berjaga di atas geladak. Yume, tentu saja, berada di dalam kapal. Meski begitu, lantai tetap basah kuyup. Air sudah masuk ke dalam, dan tubuh Yume pun basah sepenuhnya. Teriakan terdengar di mana-mana—yang ini rusak, yang itu hancur. Semuanya kacau. Sulit sekali untuk tetap tenang, dan kalau dia hanya duduk diam, rasanya dia akan menangis.
Ia ingat pernah memohon pada seseorang—siapapun itu—agar mengizinkannya melakukan sesuatu. Tapi ia tak ingat lagi siapa yang menjawabnya.
Atas perintah orang itu, Yume berlari ke ruang kargo, tersandung dan membentur kepalanya, lalu membantu mengangkat papan kayu. Ia menahannya sementara orang lain memaku papan-papan itu ke dinding.
“Kita tamat, kita tamat!” teriak seseorang.
“Kapal bakal tenggelam kalau begini terus,” ujar yang lain dengan suara jelas.
Mayoritas kru bekerja mati-matian untuk mencegah hal itu terjadi. Tapi Yume juga melihat satu orang yang mentalnya runtuh, menangis dan berteriak, “Aku menyerah! Sudah terlambat!”
Ada pula yang malah minum-minum, dan akhirnya dipukul oleh rekannya sendiri. Pria itu membalas dengan marah, “Biarin aja! Ini akhir hidup kita! Kau pikir aku bisa nerima ini tanpa minum dulu?!” sambil mencoba merebut kembali botol minumannya dengan kasar.
Mengapa Yume naik ke geladak lagi? Ia tak ingat. Beberapa anggota kru saat itu sedang naik ke atas, berkata sesuatu tentang tiang layar yang tampak akan patah, atau bahwa mereka harus segera menangani sesuatu, dan mereka butuh orang. Tak ada alasan khusus yang mengharuskan Yume ikut dengan mereka. Ia sudah cukup ketakutan, jadi ia pun tak bisa menjelaskan apa yang membuatnya naik ke geladak, tempat segalanya jelas akan terasa jauh lebih buruk.
Namun, kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin ia memang tak siap hanya duduk diam menunggu nasib, jadi ia berusaha melakukan apa pun yang bisa ia lakukan. Intinya, Yume tak ingin mati. Ia sedang berjuang melawan itu.
Rupanya, Momohina sempat mencoba menghentikannya di tengah jalan, tapi Yume tak menyadarinya. Begitu ia sampai di geladak, hujan langsung menghantamnya dari samping. Atau mungkin posisi Mantis-go sedang miring ke arah datangnya gelombang. Bagaimana nasib kru yang lebih dulu sampai di geladak sebelum dirinya? Ia tak tahu. Yume langsung tersapu begitu saja oleh hujan atau gelombang itu. Ketika sadar, ia sudah berada di laut, dan Momohina sedang memeluknya erat-erat.
Momohina bilang ia sudah mencoba memperingatkannya untuk tidak naik, tapi Yume tak mendengarkan, jadi ia menyusulnya. Lalu, mereka berdua pun ditelan lautan bersama.
“Kamu tahu, Momo-san, kalau waktu itu Momo-san nggak ada, Yume pasti suuuuuper cepat tenggelam deh. Iya kan?”
Tak ada jawaban. Hanya suara napas halus dari seseorang yang sedang tidur. Mata Momohina terpejam rapat. Ia tampak benar-benar terlelap.
Yume terkekeh pelan, meletakkan rantingnya, lalu merebahkan diri.
Bintang-bintang bertaburan di langit malam yang hitam legam begitu jelas, sampai terasa menyilaukan. Yume sering berpikir sendiri bahwa bintang-bintang di langit pulau ini terlihat enak dimakan. Bintang besar yang berwarna kuning itu pasti manis, dan yang pucat di sebelahnya pasti asam. Ia yakin masing-masing punya rasa sendiri.
Yume tertidur sambil membayangkan memasukkan bintang-bintang itu ke mulutnya, membayangkan rasanya satu per satu—tanpa menyadari kapan tepatnya ia memejamkan mata.
Saat terbangun, cahaya sudah cukup terang. Pasti bukan waktu sebelum fajar. Ini jelas sudah pagi. Api unggun telah padam.
Yume bangkit duduk. Momohina sudah berada di tepi pantai, memutar-mutar lengan, menekuk lutut, dan melakukan pemanasan lainnya.
“Selamat pagi, Momo-san.”
“Ohhh. Selamat pagiii.”
Momohina tersenyum pada Yume sambil tetap menggerakkan tubuhnya. Yume pun membalas senyum itu.
Tak ada aturan tentang kapan mereka harus tidur, kapan harus bangun, atau apa yang harus dilakukan saat terjaga. Tak ada cara untuk tahu sekarang jam berapa, dan cuaca pun berubah-ubah sesuka hati. Ada kalanya mereka bisa menemukan makanan, dan ada kalanya sama sekali tidak. Bahkan jika mereka mencoba membuat jadwal, kemungkinan besar semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Saat waktunya latihan tiba, mereka akan fokus sampai selesai, tapi di luar itu, mereka santai saja. Bahkan dalam hal latihan pun, jika cuacanya benar-benar buruk, mereka akan menundanya. Dan kalau mereka melihat binatang yang tak ingin dilewatkan, mereka akan langsung beralih berburu.
Pulau ini, seperti yang bisa diduga, dikelilingi oleh laut. Laut biru tua membentang melampaui cakrawala, seolah-olah tak ada ujungnya.
Jika mengelilingi garis pantainya sekali putaran, jaraknya sekitar enam puluh kilometer. Pulau itu kurang lebih berbentuk hati, dan setelah bersusah payah menghitung luasnya, Yume dan Momohina menyimpulkan bahwa luasnya kira-kira tujuh puluh kilometer persegi.
Di bagian timur pulau terdapat gunung berapi aktif, dan kadang-kadang asap tipis mengepul dari kawahnya. Bagian barat pulau lebih datar secara keseluruhan.
Selain aliran-aliran kecil, pulau ini memiliki enam sungai utama beserta anak-anak sungainya. Sebagian besar wilayahnya tertutup hutan lebat, sementara bagian tepi laut didominasi pantai berangin dan tebing-tebing curam. Di sisi barat dari cekungan di bagian tengah selatan, terdapat pantai berpasir—dan di sanalah mereka memutuskan untuk menetap.
Meskipun sempat terjebak dalam badai yang mengerikan itu, mereka cukup beruntung menemukan papan untuk berpaut, dan berhasil selamat. Mereka terombang-ambing selama tiga hari tiga malam—tidak, lima hari? Atau mungkin enam? Apa pun itu, mereka telah hanyut cukup lama sebelum akhirnya terdampar di pulau tak berpenghuni ini. Itu rasanya nyaris seperti keajaiban. Tidak—bukan nyaris. Itu benar-benar sebuah keajaiban.
Yume naik ke geladak karena ia tidak ingin mati, hampir saja mati karena kebodohannya, dan sekarang malah menikmati hidup di pulau ini setelah selamat berkat keberuntungan. Hidup di sini memang tidak sepenuhnya menyenangkan, tapi kalau ia menerima segala kesulitan, kesedihan, kesepian, dan semua hal lainnya… dia rasa, ia bisa bilang bahwa ia menikmati hari-harinya di sini.
Ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak bisa kita apa-apakan. Mau mengeluh atau mengamuk sekalipun, kalau sesuatu memang tak bisa diubah, ya tak akan berubah. Begitulah adanya.
Meskipun ia tahu itu, ada kalanya—terutama saat hari cerah seperti ini—ia tetap saja terpaku menatap laut di kejauhan. Bisa disalahkan, kah? Sama seperti tak bisa menahan senyum saat makan sesuatu yang enak, air mata pun sulit dicegah saat memikirkan teman-teman yang telah terpisah darinya. Dan memang tak perlu ditahan. Ia tak ingin kecewa, jadi lebih baik tidak terlalu berharap. Kalau terus menatap laut, pikirannya malah menerawang ke apa yang ada di seberang sana, dan itu hanya membuatnya makin berharap. Tapi meski ia sadar akan hal itu… ia tetap saja berharap, dan tetap menatap laut.
“…Oh.” Yume berkedip pelan.
Ia berdiri dan melangkah menuju tepi pantai. Yume benar-benar tidak memperhatikan langkahnya sama sekali. Pandangannya hanya terpaku pada laut.
“Hwuh?” gumam Momohina dengan suara kebingungan.
Ombak datang. Tapi Yume terus berjalan, seolah tak peduli. Dalam sekejap, air laut sudah mencapai lututnya.
Yume menyipitkan matanya. Ketajaman penglihatannya adalah satu hal yang tidak bisa dikalahkan Momohina.
Ia melihat sesuatu. Tampak seperti titik kecil. Ada sesuatu yang mengapung di laut. Bentuknya tak bisa dikenali dengan jelas. Jadi yang bisa ia katakan hanyalah itu sesuatu. Awalnya, ia pikir itu cuma imajinasinya saja. Saat masih di tengah laut, dan beberapa waktu setelah terdampar di pulau ini, ia sering sekali mendengar dan melihat hal-hal aneh. Tapi belakangan kejadian itu semakin jarang. Ini bukan hal semacam itu. Ini tidak terlihat seperti ilusi.
“Hei, Momo-san.”
“Ada apa, Yumeryunryun?”
“Yume, dia pikir dia lihat sesuatu jauh di sana. Menurut kamu itu apa, ya?”
Momohina berjalan mendekat ke samping Yume.
“Hmmm, itu kecil banget. Aku juga nggak yakin. Tapi aku juga lihat sesuatu.”
“Kamu bisa lihat, kan?”
“Kamu kira itu pohon besar, mungkin?”
Momohina bilang begitu, lalu tertawa. Tawa itu terdengar dipaksakan, seperti mencoba menipu dirinya sendiri. Jarang sekali Momohina tertawa seperti itu. Momohina sendiri sadar akan hal itu, dan tampak sedikit malu.
“Mungkin… dan ini cuma mungkin saja… tapi… Yume, dia rasa itu bukan pohon.”
“Kalau bukan pohon, kamu kira apa, Yumeryun?”
“Sebuah p—” Yume mulai mengucapkannya, tapi tiba-tiba menahan tenggorokannya. Kata itu tak bisa keluar. Ia bisa menghembuskan napas, tapi suaranya tak keluar. Ada apa ini?
“Ada apa?”
Momohina mengusap punggungnya. Yume tak bisa menjawab. Ia hanya mengerang sambil menatap benda di laut itu. Apa yang tadi ia kira? Pe—pe… Pe? Kata yang menggambarkan benda itu tidak kunjung muncul di pikirannya.
Tapi tetap saja, Yume merasa benda itu pasti itu.
Kamu tahu yang mana!
Saat Momohina mengusap punggung Yume dengan telapak tangannya, ia berkata, “Kamu kira itu perahu, ya?”
“Itu dia!”
“Mwuh?!”
“Itu! Kata itu! Perahu! Itu perahu! Benda di sana, Yume pikir itu perahu! Tapi cuma kemungkinan, ya!”
Saat ia terus bicara seperti bendungan yang menahan kata-katanya akhirnya jebol, ia teringat pernah bermimpi seperti ini sebelumnya. Tepat saat ia berpikir, Hore! Perahu datang! Perahu datang! Syukurlah! Sekarang kita bisa pulang! tiba-tiba ia terbangun dan menyadari, Oh, itu cuma mimpi toh, dan merasa kecewa.
“Tunggu dulu, tunggu dulu, Yumeryun! Tendang dulu! Eh, bukan itu… maksudku, tenang dulu!”
“Ya, iya, kamu benar. Kita harus tenang dulu. Kalau kita keburu heboh, bisa-bisa jadi kacau balau. Tangan dulu, tangan dulu… Eh, bukan itu, maksudku, tenang dulu…”
“Kamu sama sekali belum tenang, ya?! Gimana kalau kita berenang dulu saja?”
“Serius?!”
“Nyuhahaha! Ayo berenang saja!”
“Yume nggak mau berenang. Belum sekarang, tahu nggak?”
“Kamu benar-benar yakin itu perahu?”
“Masih susah lihatnya. Belum jelas, paling nggak…”
Yume dan Momohina memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Panas menyengat. Matahari perlahan naik, dan udara makin terik. Tanpa bicara banyak, keduanya mulai berjalan lebih dalam ke laut. Apakah benda itu benar-benar makin mendekat? Kalau ukurannya makin kecil, sebentar lagi pasti hilang. Tapi juga tidak semakin besar. Mungkin memang sudah berhenti di sana?
Mereka sudah cukup jauh memasuki laut sampai kaki mereka hampir tidak lagi menyentuh dasar. Momohina mulai berenang.
“Momo-san, kamu benar-benar mau berenang sejauh itu?”
“Aku nggak akan sampai sejauh itu. Jelas itu nggak mungkin. Aku cuma mau berenang sedikit saja. Lagipula, nggak ada hal lain yang lebih asyik buat dilakukan.”
Yume juga sempat berpikir untuk melakukan itu, tapi tak ada mood sama sekali.
Meski itu memang perahu, mereka bisa saja meninggalkan pulau tanpa pernah mendarat. Kalau itu terjadi, rasanya perahu itu bakal jadi harapan terakhir mereka. Bukan berarti Yume punya alasan kuat buat percaya itu perahu. Dia bahkan belum yakin itu perahu atau bukan.
Bentuknya memang seperti perahu dengan layar putih, tapi bisa saja itu sesuatu yang lain, hanya kebetulan mirip.
Yume sudah banyak berpikir tentang nasib Mantis-go. Dalam bayangannya yang paling buruk, kapal itu tenggelam, dan kemungkinan itu cukup besar. Badai itu sangat hebat, dan Mantis-go sudah rusak saat Yume terlempar ke laut.
“Menurutmu gimana?” pernah Yume tanya ke Momohina.
“Aku nggak tahu,” jawabnya. “Aku bukan orang laut, kamu tahu? Maksudku, aku memang kapten, tapi aku nggak pernah mengerjakan apa-apa.”
“Eh, serius?! Kamu nggak pernah?”
Momohina, seperti Yume, suatu hari tiba-tiba terbangun di Grimgar. Bersama Momohina ada seorang anak laki-laki bernama Kisaragi dan seorang gadis bernama Ichika, dan sama seperti Yume, mereka tidak ingat apa-apa selain nama mereka.
Momohina punya Kisaragi dan Ichika, sementara Yume punya teman-temannya. Kenapa dia sampai memutuskan berpisah dari mereka? Yume juga sudah banyak merenungkan hal itu. Jika dia bisa memutar waktu dan mengulang semuanya, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan ikut naik kapal yang sama dengan Haruhiro dan yang lain, lalu pergi ke kota bebas Vele?
Kapal itu tampaknya tidak semakin mendekat. Itu hanya terlihat seperti kapal, dan Yume belum bisa memastikan itu memang kapal, tapi dia mulai percaya. Sesuatu itu pasti kapal.
Pada akhirnya, itu berarti dia memang ingin percaya. Yume belajar hal itu selama di pulau itu. Mungkin bukan cuma Yume saja. Kebanyakan orang tidak percaya sesuatu karena masuk akal, tapi karena mereka ingin mempercayainya.
Pada suatu saat, Yume benar-benar yakin bantuan akan datang.
Pada saat lain, dia yakin bantuan tidak akan datang, dan mereka akan terdampar di pulau itu sampai mati.
Dia tidak punya alasan untuk percaya salah satunya.
Saat dia tidak bisa melanjutkan tanpa percaya bantuan akan datang, dia percaya. Ketika lebih mudah untuk percaya itu tidak akan datang, dia pun percaya itu.
Alasan benda yang mengapung di laut pada jarak yang tak pasti itu kini terlihat seperti kapal bagi Yume adalah karena dia ingin mempercayainya sebagai kapal. Yume melihat apa yang ingin dia lihat.
Yume memutuskan untuk berenang seperti Momohina. Saat dia melakukan gaya dada dengan santai semampunya, pikirannya terus berputar: Itu kapal. Bantuan akhirnya datang. Dan, Tidak mungkin itu kapal. Bantuan tidak akan datang.
Yume ingin menjadi lebih kuat. Tapi bukan hanya soal membangun otot atau stamina, memperbaiki teknik, belajar gerakan baru, dan meningkatkan potensi bertarungnya. Hal-hal itu memang penting, tapi dia tahu itu bukan cara untuk benar-benar menjadi kuat.
Yume ingin punya keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Yang tak akan condong ke kiri atau ke kanan hanya karena keadaan saat itu.
Atau jika pun sempat condong, bisa segera kembali ke posisi semula, dan meski goyah sekuat apapun, tak akan tetap begitu.
“Momo-saaaan.”
“Apa?”
“…Momo-saaaan.”
“Aku bilang, apa?”
“Itu kapal.”
“Hm?”
“Yang itu, pasti itu kapal.”
Yume berhenti berenang dan mulai mengapung di air.
Layar putih, badan kapal, tiang-tiangnya—semua bisa dia lihat.
“Itu kapal. Kita bisa pulang. Kita bisa pulaaaang…”
3. Bach dan Rose
Kapal itu menurunkan sauh di kejauhan dan mengirim perahu kecil. Di dalam perahu itu ada lima orang, dan semuanya memiliki tiga mata. Mereka adalah orang-orang bermata tiga dari Benua Merah.
Kalau bukan karena mata ketiga yang terletak di dahi mereka, mereka akan terlihat sama seperti manusia biasa, seperti Yume atau Momohina. Rambut mereka merah kusut, kulitnya berwarna perunggu, mungkin karena sering terpapar sinar matahari, dan kelima orang itu tampak laki-laki semua.
Yume dan Momohina sudah berjalan ke pantai untuk menyambut orang-orang bermata tiga itu, tapi begitu pria-pria itu melihat mereka, mereka langsung berteriak dan mengayunkan pedang putih mereka untuk menyerang. Yume agak terkejut, tapi Momohina malah tampak terhibur.
“Delm, hel, en! Balk! Zel, arve! Blast, boom!”
Mantera Blast yang tiba-tiba dilontarkan Momohina tak melukai orang-orang bermata tiga itu. Mantera itu hanya membuat air laut dan pasir di bawahnya terpental ke udara.
Itu memang disengaja. Momohina jarang menggunakan sihir. Sebagai mage dengan kekuatan fisik luar biasa, Momohina kadang menggunakan kekerasan, tapi sejatinya dia adalah pejuang kebebasan yang mencintai kedamaian. Lagipula, kenyataannya Yume dan Momohina tak akan pergi dari sini tanpa ikut kapal itu, jadi mereka tak bisa membunuh awaknya meski diserang.
“Yumeryun! Segera mulai penekanan! Kecepatan penuh!”
“Aye, aye, sir!”
Mereka berdua dengan cepat melucuti senjata orang-orang bermata tiga yang panik itu, dan setelah beberapa pukulan dan tendangan untuk menghilangkan niat mereka melawan, mereka mencoba bernegosiasi. Masalahnya, kata-kata mereka tidak dimengerti.
“Ugyaga gukyago zukyazukya.”
“…Hei, Momo-san, kamu ngerti nggak dia ngomong apa?”
“Nggak sama sekali! Enggak! Aku nggak tahu!”
Kalau mereka tidak mengerti bahasa mereka, ya tidak banyak yang bisa dilakukan. Namun, mereka tidak bisa begitu saja menyerah. Dengan gerakan tubuh, mereka mungkin berhasil menyampaikan bahwa mereka terdampar di pulau tak berpenghuni dan sedang menunggu pertolongan. Mungkin juga mereka paham keinginan Yume dan Momohina untuk naik ke kapal mereka, lalu dibawa ke Kepulauan Karang, Benua Merah, atau tempat lain mana pun. Itu yang Yume ingin yakini.
Dua dari lima orang bermata tiga itu tetap tinggal di pulau, sementara Momohina, Yume, dan tiga pria yang tersisa menaiki perahu kecil dan kembali ke kapal induk. Perahu kecil itu sebenarnya bisa muat tujuh orang kalau dipaksa, tapi entah kenapa begitulah kenyataannya.
“Momo-san, kenapa menurutmu dua orang itu tinggal di pulau?”
“Hmm, entahlah. Jagajaga kali?”
“Jagajaga itu siapa?”
“Aku juga nggak tahu! Hahaha!”
Momohina dan Yume bisa naik ke kapal dengan lancar. Selain pria bermata tiga itu, awak kapal terdiri dari orang-orang bermata banyak, yang memiliki mata seperti serangga memenuhi setengah wajahnya; orang-berlengan-panjang, dengan lengan yang hampir menyentuh tanah; dan orang-berkulit-duri, yang tampak seperti landak laut berjalan. Tapi kaptennya adalah orang ber-telinga-panjang, dengan telinga panjang seperti kelinci.
Meski telinganya panjang menjulang, wajah sang kapten mengingatkan pada anjing galak. Namun anehnya, ia tidak tampak sok berkuasa. Justru ada sedikit kesan pengertian darinya—walau tetap saja, ada kendala bahasa yang sulit ditembus. Mereka mencoba tetap melanjutkan percakapan meski tak saling paham, tapi situasi mulai runyam, dan akhirnya sang kapten marah. Mau tak mau, mereka terpaksa bertarung.
“Kalau memang harus begitu, ya sudah! Hajar habis-habisan, Yumeryunryun!”
“Siap, laksanakan!”
Mereka berdua menghajar tiga belas anggota kru sampai terlempar ke laut. Sembilan belas lainnya dibuat tak sadarkan diri—termasuk si kapten bertelinga panjang. Sekitar empat orang mengalami patah tulang atau cedera parah, tapi delapan belas sisanya kehilangan semangat bertarung dan menyerah. Yume sendiri hanya mengalami luka-luka ringan, sementara Momohina keluar tanpa satu gores pun.
“Oke! Kapal ini sekarang milik Perusahaan Bajak Laut K&K—K! M! W! Momohina! Tancap gas penuh!”
“Waaah, Momo-san! Kamu keren banget! Wooo!”
“Duh, jangan muji gitu dong… Atau jangan-jangan, aku emang sekeren itu?! Iya, iya juga, ya?!”
Setelah berhasil merebut kapal, Momohina dan Yume sadar mereka tidak bisa mengemudikannya sendiri. Mau tak mau, kru kapal harus dilibatkan. Setelah mengevakuasi orang-orang yang terlempar ke laut dan menjemput dua kru yang tertinggal di pulau, mereka mengecek siapa saja yang bisa diajak bicara. Hasilnya: hanya ada satu pria bermata banyak yang bisa mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa mereka. Bahkan tidak bisa dibilang fasih, tapi Yume masih bisa sedikit mengobrol dengannya.
Dengan pria bermata banyak bernama Nyagoh sebagai penerjemah, mereka menyampaikan keinginan mereka kepada kapten bertelinga panjang dan krunya. Balasannya: mereka diperbolehkan ikut sampai ke Kepulauan Karang.
“Kalau gitu, kita siap jalan!! Ayo gerak, gerak, geraaak!”
Dan begitulah, kapal itu pun berangkat.
Namanya, katanya, adalah Moccha Joe. Atau mungkin Mwachattsa Jowo.
Juru bahasa mereka, Nyagoh, mencoba menjelaskan, “Laaaut… ngambaaang… sobeeeh… mahhh…” tapi ucapannya sama sekali tidak bisa dimengerti.
Karena susah dilafalkan, Momohina pun memutuskan untuk mengganti namanya.
“Hei, Yumeryun. Gimana kalau kita namain kapal ini Si-Nggak-Guna?”
“Hm. Si-Nggak-Guna, ya?”
“Kurang oke?”
“Yah…”
“Si-Nggak-Guna. Menurutku sih cocok banget.”
“Kalau Momo-san udah ngerasa cocok banget, ya… mungkin emang cocok aja kali, ya?”
“Oke deh, mulai sekarang namanya Si-Nggak-Guna!”
Dengan Mwachattsa Jowo yang sekarang dikenal sebagai Si-Nggak-Guna, mereka melaju lancar menuju Kepulauan Karang.
Yah. Seharusnya begitu.
Dalam perjalanan, sang kapten bertelinga panjang dan para anak buahnya melakukan pemberontakan. Tak lama setelah itu, kru lainnya ikut memberontak bersenjata.
Untungnya, mereka berhasil menggagalkan kedua insiden itu tanpa korban jiwa. Tapi pertengkaran antar awak terus berlanjut, dan kapal hampir tenggelam beberapa kali karena cuaca buruk.
Akhirnya, saat mereka tiba di pelabuhan Kepulauan Karang, segerombolan orang bermata tiga, bertelinga panjang, bermata banyak, dan berlengan panjang naik ke atas Si-Nggak-Guna. Para kru yang sebelumnya tunduk pada Momohina langsung membelot dan memihak mereka.
“Sekarang aku kesaaaal. Nyelesaikan semuanya pake kekerasan tuh primitif banget. Aku bener-bener mendidih, nih. Taaaapi! Kalian masih harus nunggu sejuta abad lagi buat bisa ngalahin aku!”
“Sejuta abad?! Wah, itu sih masih cepet banget, ya?!”
Mereka berdua benar-benar menunjukkan kemampuan yang luar biasa, menghajar para bajak laut itu satu per satu tanpa ampun.
Yume bisa bergerak sesuka hatinya, ke mana pun dia mau, sementara Momohina selalu siap melindunginya dari belakang. Sebanyak apa pun musuh yang datang, rasanya mereka nggak akan kalah. Sama sekali nggak. Tapi jumlahnya memang kebangetan, dan entah sudah berapa yang mereka tumbangkan, tetap saja terus bermunculan.
Melindungi Si-Nggak-Berguna bakal jadi hal yang sulit. Bahkan kalau mereka berhasil menumpas para bajak laut dan mempertahankan kapal itu, mereka tetap nggak bisa mengemudikannya sendirian. Jadi, rasanya percuma juga.
Akhirnya, Momohina dan Yume terpaksa menyerah dan meninggalkan Si-Nggak-Berguna, lalu naik ke daratan. Pulau itu ternyata bukan cuma punya pelabuhan, tapi juga sebuah kota. Katanya sih, itu markas para bajak laut yang sekarang sedang memburu mereka.
Penduduk lokal langsung menyambut mereka dengan teriakan, lemparan batu, dan sampah. Mereka juga menaruh peti dan barel di jalan, menghalangi langkah mereka. Situasinya mulai terasa seperti “bunuh atau dibunuh”, tapi nggak semua warga di sana preman, jadi mereka nggak bisa sembarangan membantai orang.
Akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dulu dari kota dan bersembunyi di dalam hutan.
Belakangan, mereka baru tahu kalau pulau ini berada di bagian paling luar Kepulauan Karang, dan menjadi sarang sekelompok bajak laut bernama Titechitike, yang konon dalam salah satu bahasa dari Benua Merah berarti: “muntahan iblis yang tolol.”
Para bajak laut benar-benar haus darah, dan mereka menyisir seluruh pulau, mencari tanda-tanda keberadaan dua orang itu. Tapi tentu saja, Momohina dan Yume tidak berniat hanya jadi buruan pasrah. Mereka menghajar siapa pun bajak laut yang datang menghampiri, mengambil barang-barang mereka, lalu mengusir mereka pulang—karena hidup cuma sekali, dan orang-orang ini benar-benar perlu belajar menghargai nyawa mereka.
“Aku cuma membunuh apa yang aku makan!”
Itulah prinsip hidup Momohina, dan Yume sepenuhnya sependapat. Bolehkah memburu binatang di hutan untuk dimakan? Kenapa dia enggan memakan manusia—atau makhluk yang wujudnya menyerupai manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tentu saja, pernah terlintas di benaknya. Tapi tidak ada keharusan untuk memaksakan diri membunuh atau memakan sesuatu yang tidak ia inginkan. Lagipula, meskipun para bajak laut itu tak dijadikan santapan, mereka datang membawa barang-barang yang bisa dimakan juga. Meskipun diburu ke dalam hutan, tampaknya para bajak laut bukanlah pemburu sejati, jadi pulau ini masih menyimpan banyak mangsa alami. Di sana-sini juga ada mata air yang jernih, cukup untuk membuat tenggorokan mereka lega seketika.
Mereka sama sekali tak kesulitan bertahan hidup. Tapi tak lama kemudian, para bajak laut Titechitike mulai meninggalkan makanan dan kebutuhan sehari-hari di dalam hutan.
“Apa ini maksudnya…?”
Apakah ini maksudnya? Apa mereka mulai menyembah Momohina dan Yume layaknya dewa? Jujur saja, meski Yume mungkin belum sampai ke titik itu, Momohina memang memancarkan aura bak dewi pulau. Rambut mereka sudah tumbuh sangat panjang, kulit mereka kecokelatan karena terbakar matahari, dan pakaian asli mereka sudah lama rusak. Sekarang mereka hanya mengenakan pakaian seadanya—kain non-woven yang dililitkan di dada dan pinggang mereka. Tapi anehnya, Yume malah terlihat seperti gadis liar dari suku pedalaman, sementara Momohina tampak seperti resi bijak.
Mungkin mereka lebih cocok tetap tinggal di pulau ini sebagai “dewi-dewi Titechitike”?
Mana mungkin.
Mereka akhirnya berhasil keluar dari pulau terpencil itu. Yume dan Momohina ingin pulang.
Kalau mereka terus membuat para bajak laut gelisah, bisa-bisa malah bikin masalah, dan Yume juga mulai merasa agak kasihan pada mereka. Jadi mereka memutuskan untuk menyusuri pulau dan melihat apakah ada jalan lain. Pulau di sebelah ternyata cukup dekat. Yume meminta bantuan Momohina, dan mereka pun merakit rakit seadanya dalam waktu singkat. Kadang, memang harus nekat duluan. Mereka menyeberang selat itu dengan rakit, dan berhasil dengan mudah.
“Yumeryun, kamu jenius banget! Kamu keren! Kamu yang paling hebat sedunia! Harusnya kamu jadi presiden!”
“Nyeheheheheh. Yume sih nggak ngerasa ngelakuin hal sehebat itu.”
“Ayo terus maju kayak gini! Iyaaa!”
Mereka menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Kalau mereka bisa sampai ke pulau besar yang ramai, mungkin mereka bisa menemukan orang-orang dari Grimgar, bukan dari Benua Merah. Harapan mereka seperti itu. Seharusnya ada, bukan? Tidak—pasti ada! Tak mungkin tidak!
Pulau terbesar di Kepulauan Karang itu bernama Atunai, dan di sana terdapat sejumlah pelabuhan. Di salah satu pelabuhan itu—Indelica—Yume dan Momohina akhirnya, akhirnya, menemukannya.
“Wah! I-Itu kan… Ba-Ba-Ba-Ba-Bachrose!”
Mata Momohina hampir melompat keluar dari kepalanya.
“Unuh? Bakso…?”
“Bukan! Yumeryun, itu si Ba-Ba-Black… eh, bukan, bukan itu! Umm, uhh, ya! Bachrose!”
“Ohhh. Bachrose. Itu toh. Sekarang semuanya masuk akal.”
“Kau juga tahu soal itu, Yumeryun?”
“Nggak, sama sekali nggak!”
“Kau nggak tahu?!”
Keduanya langsung berlari ke dermaga tempat Bachrose-go bersandar, secepat yang kaki mereka mampu.
Bachrose-go adalah kapal besar yang tampak kokoh, tapi tetap elegan. Dicat merah marun dan hijau, tubuhnya seperti kuil yang dipersembahkan pada dewa seni—atau mungkin musik—sementara tiangnya menjulang tinggi, seperti tombak yang ingin menembus langit. Hiasan di haluannya membentuk sosok wanita bersayap berwarna keemasan, berkilau, dan terlihat seolah siap menari kapan saja.
Orang yang berdiri di dekat Bachrose-go itu bukanlah makhluk bermata tiga, atau bertelinga panjang, melainkan seorang pria manusia yang tampak seperti pelaut. Momohina langsung melesat ke arah pria itu.
“Wah, Momo-san, tunggu—”
Yume mencoba menghentikannya. Percuma saja. Momohina terlalu cepat. Tak ada cara dia bisa menghentikannya. Momohina melesat sambil berteriak, “Hyaaah!” dan mendaratkan tendangan terbang tepat ke tubuh pria itu.
“Aaaak!”
Pria itu jatuh ke laut.
Yume langsung berjongkok di tepi dermaga dan menatap ke bawah, ke arah pria itu yang kini menggelepar di air. Sepertinya dia pelaut, jadi seharusnya bisa berenang, tapi dia malah panik.
“…Momo-san.”
“Mokeeee?!”
Sepertinya Momohina juga kaget. Tapi kenapa dia menjerit kayak monyet dikejutkan petir, padahal dia sendiri yang menendangnya ke laut? Sama sekali nggak masuk akal.
“Kenapa kamu nendang dia…?”
“O-Oalah! Aku kebablasan, ya? Salah sendiri nih, refleks!”
“Kebablasan? Itu sih namanya nyerang orang, tahu nggak?”
“Soalnya aku kenal dia. Jadi nggak tahan, gitu… Saking senengnya.”
“Ohhh. Jadi kenal. Ya udah deh. Tapi tetep aja… normalnya, kamu nggak bakal nendang orang yang kamu kenal, ‘kan?”
Momohina menjulurkan lidah dari ujung mulutnya, malu-malu.
Sementara itu, pria di air berteriak, “T-Tolongin aku!” atau semacamnya. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa dia tenggelam. Saat Yume sedang berpikir mungkin mereka memang harus menolongnya, tiba-tiba terdengar teriakan dari atas dek Bachrose.
“Kamu!”
“…Hoh?”
Begitu mereka menengadah, seorang pria berjenggot sedang menatap ke bawah ke arah Yume dan Momohina dari sisi kapal Bachrose. Kumisnya megah banget, tapi kesan pertama Yume cuma satu: Ya ampun, nggak cocok banget deh…
Pria itu mengenakan penutup mata hitam di mata kanannya. Mantel hitam yang ia selempangkan di pundaknya—bukan dikenakan dengan benar—memiliki hiasan perak dan bertabur permata. Terlihat mahal. Tubuh pria itu sendiri relatif kecil, jadi mantelnya tampak agak kebesaran. Rasanya seperti pakaian itu yang sedang “memakai” dirinya, bukan sebaliknya.
Pria itu menghela napas kecil, lalu berkata, “Ah…”
“Ah!” seru Momohina.
“…Ah?”
Yume memandangi pria itu, lalu ke Momohina, lalu kembali lagi ke pria itu.
Pria itu menarik rambutnya dengan tangan kanan, lalu mengembuskan napas sebelum bergumam, “Kalau bukan Momohina…” dengan nada lesu seperti orang yang baru bangun tidur dan sedang membahas cuaca pagi.
“Kisaragicchon…”
Apakah Momohina kecewa? Tidak, bukan itu. Wajahnya tampak… lelah. Suaranya pun pelan—terlalu pelan untuk ukuran Momohina. Sepertinya ia benar-benar tak menyangka akan bertemu pria ini di tempat seperti ini. Saking terkejutnya, bukan cuma tenaganya yang hilang—jiwanya pun seperti ikut melayang.
“Kisaragicchon,” ulang Momohina. Mungkin ia mulai pulih dari rasa kagetnya, karena setelah itu ia berseru, “Yaaaay!” sambil melompat-lompat di tempat.
“Yaaaay. Itu Kisaragicchon. Yaaaay.”
“Eh, dengerin dulu, woy.”
Kisaragicchon menghela napas panjang, lalu meraih bagian luar pagar kapal dengan tangan kirinya. Apa itu sarung tangan? Tangan kanannya telanjang, tapi tangan kirinya tampak tertutup sesuatu. Tapi dari ukurannya, tangan kiri itu jauh lebih besar, dan tampaknya terbuat dari logam. Berarti… itu bukan sarung tangan, dong.
“Berapa kali harus aku bilang, hentikan panggian pakai ‘-cchon’ itu? Tapi ya sudahlah, terserah.”
“Kamu yang asli, Kisaragi-cchon yang sesungguhnya, kan?”
“Jelas aja! Masa aku rela ada cowok lain yang sekeren dan sehebat aku?”
“Enggak mungkin!”
Momohina tertawa, lalu tiba-tiba melesat lari.
“Romoh?!”
Yume mengeluarkan suara aneh, tapi tubuhnya langsung bereaksi dan berlari mengejar Momohina tanpa pikir panjang. Tujuan Momohina: jalur naik ke Bachrose. Kecepatan larinya gila. Dia menapaki tanjakan dengan langkah ringan, dan dalam sekejap, Yume sudah jauh tertinggal.
Begitu sampai di geladak, Momohina langsung memeluk Kisaragi-cchon.
“Waaaahhh. Ini Kisaragi-cchon! Kisaragi-cchon! Waaaahh. Waaaahh. Waaaahhh…”
“Udah kubilang juga, ini aku.”
“Tapi! Tapi, tapi, tapi! Ini beneran Kisaragi-cchon! Uhh… waaahhh…”
“Ya ampun, keras kepala banget. Tapi ya sudahlah, terserah.”
Dengan wajah pasrah, Kisaragi-cchon membalas pelukannya dengan erat. Mungkin Momohina sedang menangis.
Yume mengendus pelan, lalu buru-buru menutup mulut dengan tangannya. Hampir saja dia ikut terisak. Rasanya kalau dia sampai menangis sekali saja, mungkin itu bukan masalah besar, tapi dia tak mau menangis sekarang. Momo-san, aku ikut senang buat kamu, pikirnya, dan perasaan itu benar-benar datang dari lubuk hatinya. Ia boleh saja menangis, tapi kalau dia melakukannya sekarang, mungkin itu bukan jadi pelepasan, melainkan malah bikin hati makin sesak. Entah kenapa, dia merasa seperti itu.
4. Potret Seorang Pahlawan
Bachrose-go adalah kapal milik Perusahaan Bajak Laut K&K.
Dan bukan cuma itu—kapal itu juga milik Adipati Agung Deres Pain.
Tentu saja, Yume sama sekali tak tahu apa itu “adipati agung”, atau siapa itu “Deres Pain”. Ia belum pernah melihat, belum pernah mendengar, dan—tentu saja—belum pernah memakan satu pun dari mereka. Meski begitu, katanya Deres Pain itu seorang tokoh, jadi kemungkinan besar bukan makanan. Tapi walau secara teknis mungkin tergolong “manusia”, Deres Pain bukanlah manusia dalam arti sempitnya.
Ada sebuah kota bernama Igor. Letaknya bukan di Benua Merah, juga bukan di Kepulauan Karang, melainkan di utara Grimgar, di sepanjang garis pantai. Kota pelabuhan ini cukup besar. Selevel dengan Kota Bebas Vele, dan dulunya sempat berjaya sebagai gerbang laut bagi Kerajaan Ishmal.
Namun, Kerajaan Ishmal kini tinggal nama. Itu sudah runtuh—atau lebih tepatnya, dimusnahkan. Wilayah yang dulunya merupakan kekuasaan Ishmal kini sebagian besar dikuasai oleh para undead.
Kota pelabuhan Igor tidak sepenuhnya dipenuhi undead sejauh mata memandang, tapi mayoritas penghuninya berasal dari ras-ras yang tergabung dalam Aliansi Para Raja—seperti orc dan undead—yang jelas-jelas memusuhi umat manusia.
Sosok yang dikenal dengan nama Deres Pain adalah penguasa Igor, dan ia menyebut dirinya Adipati Agung.
Adipati Agung.
Sekarang, itu baru gelar yang terdengar sok penting. Tapi dia bukan cuma sok—dia memang penting. Saat mendengar bahwa dia adalah penguasa Igor, mudah membayangkan dia hanya semacam wali kota dari sebuah kota kecil, dan Yume pun awalnya mengira begitu. Tapi nyatanya, derajatnya setara dengan seorang raja dari negara yang cukup besar.
Setelah No-Life King mati—meskipun seharusnya tidak bisa mati karena memang tidak hidup sejak awal—tinggallah empat atau lima undead yang benar-benar berpengaruh, dan Deres Pain adalah salah satunya.
Kisaragi, alias Kisaragicchon, mencuri kapal bangsawan agung itu dan menjadikannya miliknya sendiri. Nggak masuk akal, sih. Tapi sudahlah, namanya saja Bachrose-go, pasti keren.
Kapal itu memang sekeren itu, jadi ketika Kisaragi mendirikan Perusahaan Bajak Laut K&K, dia menjadikan Bachrose-go sebagai kapal andalan mereka. Kapal andalan adalah kapal tempat orang paling penting berada, memberi komando ke semua orang—jadi otomatis kapal itu juga jadi simbol dari K&K.
Oh, ya. Meskipun Kisaragi yang memulai K&K, dia bukan presidennya. Bukan juga ketua atau jabatan sejenisnya. Presiden perusahaannya adalah seorang wanita bernama Anjolina Kreitzal, yang memang sudah jadi bajak laut sejak awal. Dia juga yang menjadi kapten dari kapal Bachrose-go.
Kisaragi memimpin Bachrose-go—bersama ratusan kapal lain milik K&K—untuk mencari Momohina, dengan Yume sebagai bonus tambahan.
Meski begitu, K&K tetap harus menjalankan aktivitas mereka seperti biasa—berdagang, membuka jalur baru, bertempur, dan menjarah. Semua itu tak bisa mereka abaikan. Karena itulah, setiap kapal hanya bisa mencari Momohina dan Yume di sela-sela kesibukan mereka.
Tentu saja, mengatakan lebih mudah daripada melakukannya. Bagaimanapun juga, Momohina dan Yume hilang di laut. Dan laut itu penuh bahaya. Kehilangan satu kapal selama pencarian akan jadi musibah. Lagi pula, mereka terlempar dari Mantis-go ke laut di tengah badai. Kalau dipikir secara logis, kemungkinan mereka selamat sangat kecil. Bahkan nyaris tidak ada. Ya—bisa dibilang nol.
Jadi, tidak ada gunanya mencari. Maka dari itu, ya… tidak ada yang mencari. Tidak ada pilihan lain. Kalau rekan-rekan Momohina sampai memutuskan seperti itu, siapa pun takkan bisa menyalahkan mereka. Jujur saja, saat terdampar di pulau terpencil itu pun, Yume pada dasarnya sudah menyerah. Dipikir-pikir, harapan bahwa ada seseorang yang masih mencari mereka terasa nyaris mustahil.
Yah… memangnya siapa juga yang bakal repot-repot nyari?
Namun, Kisaragicchon dan kawan-kawannya tetap melanjutkan pencarian.
Alasan terbesar mereka adalah karena Mantis-go ternyata tidak tenggelam, dan sang kapten—Ginzy—berhasil kembali ke Kepulauan Zamrud bersama para penyintas lainnya. Yang dicari K&K bukan cuma Momohina dan Yume. Ada juga awak kapal lain yang terjatuh ke laut bersama mereka—dan mereka berniat mencari semuanya.
“Aku udah menduganya dari awal—mengenalmu, rasanya nggak mungkin kamu beneran mati. Dan bukan cuma aku aja yang mikir gitu. Semua orang yang kenal kamu juga punya perasaan yang sama.”
Kumis Kisaragi—yang begitu mencolok sampai-sampai tampak seperti tidak seharusnya berada di bawah hidungnya—bergetar saat ia mengucapkan itu. Tentu saja, yang ia bicarakan adalah Momohina.
Ngomong-ngomong, setelah itu Bachrose-go langsung berlayar kembali dari Indelica menuju Kepulauan Zamrud. Tapi Momohina tiba-tiba bersikap agak canggung terhadap Kisaragi. Kalau Kisaragi memanggil namanya, dia hanya akan menjawab dengan, “Nyaa,” atau, “Mphuh,” lalu kabur. Bahkan saat dia sesekali mengajaknya bicara, dia tak pernah menatap matanya langsung. Dari tempat Yume berdiri, ia tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, Padahal kamu peluk dia erat banget, bahkan sambil nangis segala, tapi… mungkin justru karena itu kamu jadi malu sendiri dan sekarang jadi jaim ya? Yume masih bisa sedikit mengerti perasaan-perasaan seperti itu.
Momohina tampak terobsesi dengan bermain petak umpet dengan Kisaragi, dan akibatnya Yume jadi jarang dilatih seperti yang ia harapkan. Waktu luangnya di kapal pun jadi banyak. Ia kadang membantu kru sedikit-sedikit, tapi perasaannya terhadap pekerjaan itu agak hambar. Semua tugasnya terlalu mudah—belum selesai ia merenung soal kenapa perasaannya hambar, eh, pekerjaannya sudah kelar. Karena terlalu cepat menyelesaikan tugas, kru kadang menatap Yume seolah dia malah bikin repot.
Saat ia lelah terus bergerak sendiri—seperti sekarang—Yume biasanya duduk di sisi kapal, menatap ke laut. Bukan karena sedang memikirkan sesuatu yang penting. Tapi ia juga tidak mengusir pikiran-pikiran yang datang begitu saja. Meski cuaca tidak buruk, ombak tetap tinggi dan menggoyang kapal. Tapi itu tak membuatnya takut atau mabuk laut. Ia sudah terbiasa. Ia sempat mengobrol sedikit dengan kapten kapal, Anjolina. Wanita itu serius, dewasa, dan ditakuti oleh krunya—dalam arti yang baik. Yume merasa, tak peduli seberapa tua dirinya nanti, ia tak akan pernah bisa menjadi seperti Anjolina. Ia bisa mengerti kenapa yang menjadi presiden K&K dan kapten Bachrose-go adalah Anjolina, bukan Kisaragi.
Namun, meskipun Anjolina menjabat sebagai presiden, yang sebenarnya mengarahkan jalannya K&K jelas-jelas adalah Kisaragi. Ia seorang pemimpin, tapi bukan pemimpin dalam arti konvensional. Itu tidak jelas, atau mungkin setengah hati. Tapi semua orang di K&K menerima bentuk kepemimpinan yang aneh itu.
Tidak semua pemimpin itu sama. Seperti halnya manusia yang beraneka ragam, pemimpin pun datang dalam banyak bentuk.
“…Itu juga berlaku untuk pemimpin Yume dan yang lainnya,” gumam Yume pelan, lalu menundukkan kepala.
Ia terus memikirkan teman-temannya selama di pulau itu. Ia pernah menangis sesegukan, meraung-raung juga. Seharusnya, ia hanya pergi selama setengah tahun. Hanya setengah tahun, lalu ia akan ke Altana. Yume sudah meminta teman-temannya untuk menunggunya di sana. Tapi ia mengingkari janji tersebut. Waktunya bukan setengah tahun yang berlalu—sudah lebih dari dua tahun sekarang. Sebentar lagi bahkan akan menginjak tahun ketiga.
Mereka pasti sudah muak menunggu. Atau mungkin, mereka bahkan sudah berhenti menunggu. Bukan karena Yume tidak percaya pada mereka, tapi jika ia terlambat selama ini, tentu saja mereka akan mengira sesuatu telah terjadi padanya.
Sebenarnya, Yume berharap mereka memang sudah berhenti menunggu. Ia tidak keberatan jika mereka melupakannya. Ia ingin mereka melupakannya. Pikirannya itu membuat hatinya perih. Tapi tak apa, asal hanya Yume yang merasa sedih. Kalau hanya Yume yang bersedih, ia masih sanggup menahannya.
Setiap kali memikirkan teman-temannya, dadanya terasa begitu sesak hingga ia sulit bernapas.
Apa yang terasa sakit, bagaimana sakitnya, dan mengapa—itu semua hal yang tak ingin ia pikirkan. Dan memang tidak bisa. Rasanya sakit. Terlalu sakit untuk ditahan.
Saat itulah ia menyadari seseorang sedang mendekat. Karena suara angin dan ombak, langkah kaki itu nyaris tak terdengar, tapi orang itu berjalan sambil mengetukkan sesuatu yang keras ke pagar kapal.
Yume mendongak.
Itu adalah Kisaragi. Benda keras itu ternyata adalah tangan kirinya. Kisaragi telah kehilangan tangan kirinya, dan menggantinya dengan tangan prostetik. Penutup mata di mata kanannya juga bukan sekadar aksesori. Semua itu memberi kesan seperti bajak laut, apalagi dengan kumisnya yang mencolok. Tapi karena bagian janggut lainnya hampir tak ada, dan wajahnya halus sekali, kumis itu jadi kelihatan aneh. Bahkan terkesan palsu.
“Hei.”
Kisaragi mengangkat tangan prostetiknya. Mungkin itu jenis prostetik khusus. Meski tampak kaku, gerakannya sangat mulus, hampir seperti tangan sungguhan.
“Hei.”
Saat Yume menirukan senyumnya dan melambaikan tangan balik, Kisaragi menyipitkan mata tiba-tiba, dan kumisnya ikut melengkung sedikit.
“Ah…!”
“Hm?”
“Denger deh… kumis itu… jangan-jangan…?”
“Oh, ini?”
Kisaragi menjepit kumisnya dengan tangan kanan—lalu menariknya.
Kumis itu langsung copot.
“Kumis palsu.”
“…Beneran, ya? Yume juga sempat mikir, Momo-san juga kayaknya pernah pakai kumis palsu, lho.”
“Serius?”
“Iya. Waktu pertama kali ketemu. Kayaknya dia niru kamu, Kisaragicchon.”
“Kamu juga mau manggil aku begitu? Tapi ya sudahlah, terserah.”
“Kamu sering bilang ‘Tapi ya sudahlah, terserah,’ ya? Kisaragicchon.”
“Nggak juga. Aku cuma bedain mana hal yang penting dan mana yang nggak kupeduliin.”
“Hrrmm. Terus kenapa sih kamu pakai kumis palsu, Gicchon?”
“Sekarang malah disingkat? Tapi ya sudahlah, terserah. Waktu aku ke Benua Merah, orang-orang ngira aku masih bocah. Tapi kalau ada rambut di mukaku, aku kelihatan kayak orang dewasa. Itu nyelametin aku dari banyak ribetnya urusan, lho.”
“Jadi… ini kayak ngomongin cewek punya dada gede, gitu ya?”
“Ada juga perempuan dewasa yang rata, kan.”
“Oh, ya? Iya juga, ya? Dada Yume juga kecil. Momo-san juga. Tapi, tahu nggak? Kapten Anjolina itu… mantul-mantul.”
“Kamu mau terus ngomongin soal dada?”
“Enggak juga, sih. Tapi… dada gede tuh enak kalo disentuh. Ngomong-ngomong soal dada, Shihoru juga punya, kan.”
Yume langsung menutupi dadanya dengan kedua tangan. Dia nggak bisa berkata apa-apa.
Jelas, bagian tubuh Yume yang satu itu jauh berbeda dari milik Shihoru. Hampir nggak ada tonjolan. Nggak terasa kenyal, apalagi lembut. Rasa iri yang menggebu muncul begitu saja. Yume suka dada Shihoru. Paha dan perut Shihoru juga bagus, tapi dada Shihoru itu beda kelas. Dia pengin nyentuh. Pengin ngebenamkan wajahnya dalam-dalam.
Apa suatu hari dia bakal bisa?
“Shihoru? Dia salah satu temanmu, ya?”
Saat Kisaragi bertanya, Yume mengangguk. Hanya itu yang bisa dia lakukan, mengangguk naik-turun. Kalau dia maksa ngomong, suaranya pasti bakal keluar aneh.
“Aku pernah dengar soal kalian. Waktu aku pergi, salah satu dari kalian katanya nenangin naga-naga di Kepulauan Zamrud, ya? Pahlawan dari Roronea. Penunggang Naga. Haruhiro, kan, namanya?”
Iya.
Haru-kun, dia emang nggak kelihatan kayak pemimpin, tapi dia pemimpin yang sesungguhnya. Dia selalu mikirin Yume… dan semua orang juga. Lebih dari dia mikirin dirinya sendiri. Itu luar biasa. Dia pemimpin terbaik buat Yume, dan buat semuanya juga.
Yume mengembungkan pipinya. Wajahnya mungkin sudah memerah seluruhnya. Ia ingin sekali bilang sesuatu, ingin mengatakannya dengan baik-baik, tapi tak ada satu pun kata yang keluar. Sungguh, yang bisa ia lakukan hanya mengangguk.
“Gak usah dipikirin.”
Kisaragi meletakkan tangannya—tangan yang asli, bukan yang prostetik—di atas kepala Yume. Tangannya tidak besar. Meski begitu, kepala Yume terasa pas saja di sana.
“Kamu muridnya Momohina, kan? Berarti kamu juga bagian dari keluargaku. Pertama-tama, aku bakal nganter kamu balik ke Grimgar. Kalau butuh yang lain, tinggal bilang. Emang sih, ada hal-hal yang gak bisa kulakuin. Tapi gak banyak. Andalin aku aja.”
Iya.
…Iya.
Apa boleh dia mengangguk begitu saja? Kisaragi baru saja bilang, “Andalin aku.” Kalau dia mengangguk, itu berarti dia benar-benar akan mengandalkannya, akan menggantungkan dirinya pada Kisaragi. Tapi bahkan di tengah keraguannya, ada dorongan dalam hati yang membuatnya ingin mengangguk.
“…Gicchon.”
“Iya?”
“Yume tuh…”
Dia mau nangis, dan karena itu, dia gak bisa lanjut ngomong.
Yume masih merasa seperti akan menangis kapan saja. Hatanya dipenuhi rasa haru, tapi air mata itu tak kunjung keluar, walaupun seolah-olah sudah di ujung. Lama-lama dia merasa, Mungkin gak perlu nangis deh.
Itu pasti karena Kisaragi.
“…Gicchon. Kamu lumayan keren juga, ya?”
“Yah, kadang emang ada yang bilang gitu.”
Kisaragi menjawab singkat sambil menarik kembali tangannya dari kepala Yume.
“Aku kan satu-satunya pahlawan besar yang tiada duanya.”
5. Patah Hati
Bachrose-go berhasil kembali ke pelabuhan di Roronea tanpa hambatan. Saat itu, Momohina sudah berhenti lari dan sembunyi dari Kisaragi. Sebaliknya, dia mulai terus menempel pada pria itu sampai-sampai Kisaragi berkata, “Kamu nempel terus, menjauh sana.” Tapi meskipun berkata begitu, Kisaragi tidak pernah benar-benar menolaknya, jadi Momohina tetap tidak mau jauh-jauh darinya. Sampai-sampai dia tidur malam pun melilit erat tubuh Kisaragi.
Momo-san memang sayang banget sama Gicchon, ya?
Yume juga menyukai Kisaragi. Kalau saja dia bertemu pria itu sebelum bertemu Haruhiro dan yang lainnya, mungkin dia sudah memilih ikut bersamanya. Tapi semakin besar rasa sukanya pada Kisaragi, semakin dia sadar betapa pentingnya Haruhiro dan teman-temannya baginya.
Yume mencoba menenangkan diri dan memikirkannya baik-baik. Dengan semua yang telah terjadi, tidak ada jaminan dia bisa bertemu kembali dengan Haruhiro dan yang lain. Bisa saja ia berhasil, bisa juga tidak. Tapi sekarang, Yume sudah tidak takut lagi.
Ketika membayangkan bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat teman-temannya lagi, rasanya seperti ada yang merobek jantungnya, memelintir lehernya, dan mencabik-cabik tubuhnya. Sakit sekali. Tapi Yume tidak berniat menutup mata dan menghabiskan hari-harinya hanya dengan harapan kosong bahwa ia ingin bertemu mereka lagi. Ia memilih untuk menggenggam harapan itu erat-erat. Ia akan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan menetapkan tujuan dan melangkah ke arahnya. Ia tidak boleh membiarkan rasa takut menghentikannya.
Para petinggi di Perusahaan Bajak Laut K&K—kecuali kepala divisi undead, Jimmy—sedang tidak berada di tempat. Mereka tengah sibuk mengambil alih kapal ke sana kemari, sebagian untuk mencari keberadaan Momohina.
Para perwira K&K terdiri dari direktur pelaksana Giancarlo; Ichika si HPW (konon singkatan dari Healing Partner Woman, entah kenapa itu dijadikan jabatan); Mirilieu si EDBDM (Elf Dengan Bagian Dada Mengecewakan—benarkah itu gelar resmi?); serta Heinemarie si DNW (Dwarf Nokturnal Wanita—kalau diterjemahkan secara bebas, bisa dibilang ‘Perayap Malam Kerdil’. Rasanya tak pantas dijadikan jabatan, tapi begitulah kenyataannya).
Sahuagin tak tahu malu bernama Ginzy juga masih ada, menjabat sebagai kapten kapal Neo Mantis-go. Ia, tentu saja, belum tahu bahwa Momohina dalam keadaan selamat. Saat mengetahui kabar itu nanti, ia pasti akan sangat senang.
Setelah persediaan dilengkapi, dan diiringi sorakan dari para bajak laut serta warga Roronea, Bachrose-go pun segera berlayar meninggalkan pelabuhan. Kisaragi tidak secara langsung berkata, “Kau pasti buru-buru, ya?” pada Yume—tapi jelas maksud tindakannya ke situ.
Ia sudah sangat terlambat. Berlari-lari sekarang pun tak akan membantu, tapi tetap saja, ia ingin secepat mungkin menginjakkan kaki di daratan Grimgar. Andai bisa, ia pasti sudah berubah jadi burung dan terbang langsung ke Altana.
Tujuan Bachrose-go bukanlah Kota Brbas Vele, apalagi Igor, melainkan pelabuhan yang sama sekali berbeda.
Pelabuhan itu bernama Nugwidu—nama yang cukup sulit diucapkan—dan terletak jauh di selatan Vele. Di sekitar Nugwidu, sejak zaman dahulu, tinggal sekelompok orang aneh yang disebut kaum Zwiba. Konon, mereka telah membentuk semacam negara kecil sendiri. Kaum Zwiba memiliki bahasa, adat istiadat, dan budaya yang benar-benar berbeda, dan sama sekali tidak berbaur dengan ras lainnya. Jika kaum Zwiba melihat seseorang yang bukan dari kalangan mereka, mereka akan langsung menyerbu, menangkap, dan—percaya atau tidak—memakannya.
Yume sudah lama tahu bahwa kaum Zwiba itu aneh dan sangat berbahaya, jadi ia selalu berusaha menghindari mereka sebisa mungkin.
Namun, kenapa Kisaragi bisa tahu soal kaum Zwiba? Ternyata dia pernah ditangkap oleh mereka dan nyaris dimakan hidup-hidup.
“Soalnya, kamu tahu kan kondisi lenganku? Begitu mereka lihat, mereka langsung bingung dan bilang, ‘Ini kok aneh, ya? Boleh nggak sih makan orang kayak gini?’ Terus, waktu mereka masih sibuk mikir… entah gimana, akhirnya kami malah jadi temenan.”
Apa yang harus terjadi sampai seseorang bisa berteman dengan orang-orang yang sempat mencoba memakannya? Yume benar-benar tak bisa membayangkan.
Yang jelas, sekarang kapal Bachrose-go sedang menuju pelabuhan di Nugwidu.
Bangsa Zwiba sangat tertutup terhadap orang luar, sampai-sampai mereka tidak mengembangkan teknologi untuk membangun kapal besar atau pelabuhan. Menurut Kisaragi, kapal Zwiba—selain kapal nelayan—yang keluar dari Nugwidu tidak pernah kembali. Bisa jadi mereka berasal dari seberang lautan dan tengah berusaha kembali ke tanah asal mereka.
Kisaragi bilang, daripada menuju Vele, lebih cepat kembali ke Altana lewat Nugwidu. Dari Nugwidu, dia bisa menuju barat ke Dataran Quickwind, lalu terus ke arah selatan menuju Pegunungan Tenryu. Selama terus mengikuti arah itu, mustahil tersesat.
Bagi Yume, ucapan Kisaragi terdengar seperti jaminan mutlak, dan ia tak punya alasan untuk meragukannya. Ia sama sekali tidak merasa cemas. Justru, ia sangat antusias ingin bertemu dengan bangsa Zwiba.
Momohina tetap tinggal di atas Bachrose-go. Ia akan terus melatih Yume sampai mereka tiba di Nugwidu, menyempurnakan pelatihan yang tersisa.
Mereka berlatih di atas kapal yang terus bergoyang—berlari dan melompat-lompat di dek. Setelah hari pertama perjalanan yang melelahkan tapi memuaskan, keesokan paginya Yume terbangun di dalam kabin, di atas hammock.
Mungkin karena terlalu lama hidup nyaris telanjang di pulau sebelumnya, memakai pakaian sekarang terasa merepotkan. Apa pun yang ia kenakan, pada akhirnya akan ia lepas saat tidur. Hari ini pun, ia kembali terbangun tanpa sehelai benang pun. Karena tidak bisa terus seperti itu, ia mengenakan atasan pendek yang hanya cukup menutupi dadanya, dan celana super pendek. Setelah itu, ia membasuh wajah dan berkumur sedikit.
Saat ia naik ke geladak, matahari baru saja terbit. Tapi karena tak ada apapun yang menghalangi di atas laut, sinarnya sudah membuat segalanya terang. Yume lebih suka laut saat masih sedikit lebih pagi dari ini—ketika matahari baru hendak muncul di balik cakrawala. Laut saat matahari terbenam juga indah, tapi kadang-kadang malah membuatnya merasa kesepian.
Harusnya tadi dia bangun lebih awal. Dengan sedikit kecewa, dia berjalan menyusuri geladak, sampai akhirnya melihat seorang pria di dekat haluan. Pria itu telanjang dada, tampaknya sedang melakukan pemanasan atau semacamnya.
Siapa itu?
Punggung pria itu menghadap ke arahnya, jadi wajahnya tidak terlihat. Yume tahu semua kru Bachrose-go. Pria ini bukan bagian dari kru.
Tubuhnya luar biasa. Otot-otot di punggungnya membentuk bayangan yang mirip wajah monster mengerikan. Tapi meski posturnya tinggi, ia tidak terlihat besar. Tidak ada yang berlebihan. Tubuhnya terbentuk oleh latihan ekstrem—seperti sebilah pedang yang diasah sempurna.
Tanpa sadar, Yume mematung dan terus menatap.
Pria itu mulai menggerakkan lengannya perlahan, memutar bahu, meregangkan persendian, membungkuk, lalu berdiri dengan satu kaki. Gerakannya tidak istimewa. Itu biasa saja. Tapi entah kenapa, Yume tidak bisa memalingkan pandangan sedetik pun.
Pria itu kuat.
Kuat dalam arti sebenarnya.
Jantungnya berdegup kencang. Seluruh tubuhnya terasa seperti dialiri sengatan halus. Apa dia ingin pipis? Tidak, bukan itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang memeluk atau mencengkeramnya dari dalam.
Pria itu berbalik.
Saat itulah Yume menyadari rambut pendeknya berwarna perak.
“Ah, kamu, ya.”
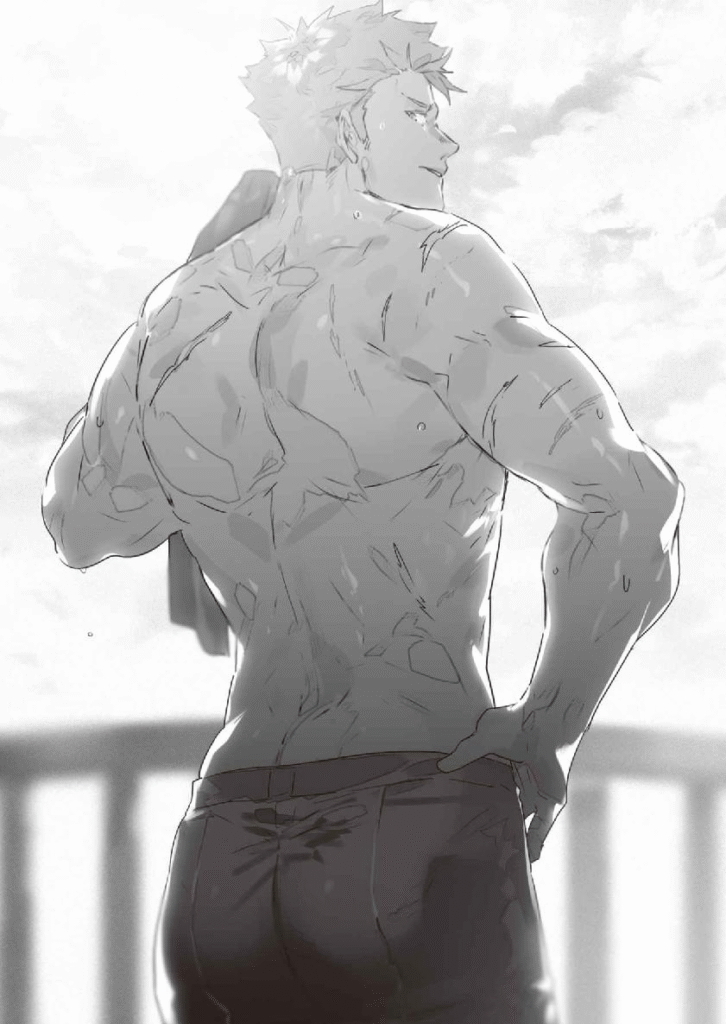
“Fwuh.”
Yume hendak memanggil namanya, tapi entah kenapa, kata itu tak keluar dari mulutnya.
Dia mengenalnya. Mereka datang ke Grimgar di hari yang sama. Mereka memang bukan teman dekat, tapi tetap bisa dibilang rekan seperjuangan, setidaknya dalam arti yang luas.
Sudah lama sejak terakhir mereka bertemu. Tapi itu bukan cuma soal dia. Yume sudah lama hanya bersama Momohina. Rasanya sudah cukup lama juga sejak ia melihat siapa pun selain dirinya.
“…Kamu naik kapal ini? Kamu juga…? Haaaah? Kenapa?”
“Aku sempat tinggal di Benua Merah. Aku punya perjanjian dengan K&K. Aku menunggu kapal menuju Grimgar dari Kepulauan Zamrud.”
“Ohhh… Oke. Jadi kamu numpang kapal ini, ya? Gitu, ya… Yume nggak tahu sama sekali. Dia baru nyadar sekarang.”
“Tapi aku tahu. Aku nggak sengaja dengar kabar soal Kisaragi yang berhasil menemukan dua perempuan yang hilang setelah kapalnya kena masalah.”
“Oh. Kalau kamu lagi di Roronea, pasti dengar, ya…? …Tapi kalau kamu udah tahu, kenapa nggak bilang?”
“Aku sempat lihat kalian kemarin, tapi kamu dan Momohina lagi heboh loncat-loncat, muter-muter.”
“Ohhh, lagi latihan, ya. Iya sih… …Umm, uhh, err…”
Kenapa dia selalu tegang tiap kali mau sebut nama itu?
Ada yang aneh dengan Yume. Apa, sih, masalahnya? Ia coba pikirkan, tapi kosong. Pokoknya, repot juga kalau nggak bisa nyebut nama orang yang udah jelas-jelas berdiri di depan mata. Mau nggak mau, dia harus maksa diri buat mengucapkannya.
“Renji!”
Begitu dia memanggil, Renji berkedip.
“…Apa?”
“Umm, eh… Yume mau nanya, apa kamu tahu sesuatu tentang Haru-kun dan yang lain? Soalnya Yume sempat pergi buat latihan, terus ada kejadian itu, yang soal kapal, sama badai… Udah lama banget dia nggak ketemu mereka.”
“Aku udah di Benua Merah sekitar setahun, dan sebelum itu pun sudah hampir setahun nggak balik ke Altana.”
“Oh, ya? Wah, berarti kamu emang nggak tahu, ya?”
“Aku dengar Haruhiro pernah naik naga di Kepulauan Zamrud. Kayaknya kalian berpisah setelah itu, ya?”
“Iya… Itu udah lama… lama banget, ya…?”
“Yah, dia kan si Penunggang Naga.”
Saat Renji tiba-tiba tersenyum, rasa tegang di hati Yume seketika mencair.
Dia kira Renji tidak pernah senyum, orangnya kaku dan susah didekati. Atau mungkin waktu yang berlalu lah yang mengubah Renji.
“Dia nggak bakal mati semudah itu. Kamu aja bisa selamat, kan.”
“…Mm-hm. Iya. Kalau yang bilang kamu, entah kenapa kedengarannya menyakinkan.”
“Kamu maksudnya ‘meyakinkan’?”
“Ya itu, yang itu. Meyakinkan.”
Tiba-tiba, Yume terpikir sesuatu. Renji sudah berubah. Yume juga merasa dirinya bukan lagi seperti sebelum dia terdampar di pulau ini. Mungkin nggak ada yang benar-benar tetap. Orang-orang pun pasti berubah.
Haruhiro dan yang lainnya… mungkin mereka juga udah sangat berbeda sekarang.
“Aku dulu pikir aku cukup jago menilai orang.”
Tatapan mata Renji tertuju jauh ke kejauhan.
“Aku salah. Kupikir kalian itu sampah. Bukan soal bisa kugunakan atau tidak. Kalian pasti mati dalam waktu singkat. Ada si Manato itu, kan? Dia benar-benar apes. Mati cepat. Moguzo… Kalau dia selamat, dia pasti bakal makin kuat. Tapi siapa pun yang terlibat sama kalian, pasti mati. Semuanya. Satu per satu. Aku yakin itu dari awal. Aku tidak pernah ragu, bahkan sedikit pun.”
Kata-kata yang mengalir dari mulut Renji seperti tetes hujan besar—bening, kosong, tak bermakna.
Mereka pecah saat menyentuh tanah. Tapi itu bukan wadah, cuma suara, cuma kata-kata. Jadi tak ada yang tersisa.
“Kalian semua akan mati. Bukan karena aku meremehkan. Aku cuma percaya begitu adanya. Seperrti kalau air disiram ke api, apinya padam. Aku tidak pernah bimbang. Itu omong kosong. Kalau kau punya waktu buat ragu, lebih baik terus melangkah. Kamu akan lebih maju. Mau ragu soal apa? Nggak masuk akal.”
“Renji.”
“Apa?”
“Kamu… habis ngalamin sesuatu ya?”
“Nggak.”
Renji menundukkan kepala, menekan tangannya ke pelipis seperti sedang menggaruk rambut peraknya. Senyum tipis tergantung di bibirnya. Seolah-olah yang bisa dia lakukan cuma menertawakannya.
“Gak ada yang terjadi. Aku ya aku. Gak lebih, gak kurang. Cuma itu. Semoga kamu bisa ketemu party-mu lagi.”
“…Iya. Makasih.”
Renji sempat mengangkat tangannya sedikit saat pergi. Itu saja yang Yume lihat darinya hari itu, tapi bayangan itu terus melekat di pikirannya sepanjang waktu.
Keesokan harinya, Yume berjalan mengelilingi kapal, mencari Renji. Kapal Bachrose-go memang besar. Tapi tetap saja, tidak seluas kastel atau serumit labirin. Di tangga dalam kapal, ia tidak menemukan Renji, tapi ia bertemu dengan pria lain yang berambut cepak dan cukup ia kenali.
“Hohhh! Umm, eeh, siapa ya namanya…?”
“Ron.”
Ron, pria berambut cepak itu, menatap wajah Yume, sedikit menundukkan dagunya, lalu menurunkan pandangannya. Ia menghela napas.
“Aku heran kamu bisa keliling-keliling dengan pakaian… segitu terbukanya di tengah kapal yang isinya cowok semua, yang udah kelamaan nggak lihat cewek.”
“Hah? Terbuka? Pakaian?”
“Bukan ‘terduka.’ Terbuka. Maksudku… ya, agak menggoda gitu, tahu kan?”
“Hmm, menggoda ya? Seksi, gitu maksudnya?”
“…Iya, semacam itu. Nggak, malah beneran itu maksudku.”
“Mwohh. Yume baru kali ini dibilang seksi.”
“Yah, tergantung selera sih. Kebetulan aku memang suka tipe cewek kayak kamu.”
“Berarti Ronron tipe cowok yang suka cewek kayak Yume, ya?”
“I-iya, gitu deh. Tapi jangan langsung ngomong gitu juga dong… Malu, tahu nggak. Eh, padahal aku sendiri yang bilang duluan, ya? Sial… Sekarang jadi kedengeran kayak aku lagi nembak kamu!”
“Ronron mau bunuh Yume?”
“Bukan nembak beneran! Emangnya aku mau bunuh buat apa?! Dan nggak, aku nggak ngaku apa-apa tentang jatuh cinta! Ngimpi! Lagian, siapa yang bilang kamu boleh manggil aku Ronron? Itu, um, ya gitu deh… biasanya buat orang yang lebih deket… k-kayak cewek sama cowok yang s-sedang jadian? Buat… n-nonjokin perasaan mereka…”
“Dengerin deh, Yume udah pernah dikoreksi soal ini, tapi itu bukan ‘nonjokin perasaan’, tapi… itu lho… nunggingi perasaan…?”
“Hah? Nunggingi perasaan…?”
“Numpangin perasaan? Bukan itu ya?”
“Apapun yang kamu maksud, semuanya salah.”
“Yume juga mikir gitu, sih.”
“…Ngobrol sama kamu itu capek, ya. Kayak hidup di dunia lain. Tapi entah kenapa, aku malah agak suka…”
“Yaaa? Yume juga seneng ngobrol sama kamu. Jadi… suka juga, dikit… mungkin?”
“Eh, eh, eh. Ini semacam pengakuan cinta terbalik, gitu? Serius? Maksudku, aku sih lagi kosong sekarang. Eh, bukan maksudnya aku nggak laku, ya. Jelas aku laku. Cuma sibuk terus aja. Gak pernah sempat seriusin apa-apa…”
“Oh!”
“A-apa?! Kamu mau jadian sekarang juga?!”
“Hmm, jadi gini… Yume tuh lagi ngelakuin sesuatu. Baru inget. Kemarin pagi, dia ngobrol sama Renji.”
“Oh, ujung-ujungnya Renji lagi, ya?! Selalu dia! Baik cowok maupun cewek! Renji, Renji, Renji, Renji, RENJIIIIII!!”
Ron tiba-tiba membenturkan kepalanya ke dinding. Keras banget sampai Yume cuma bisa melongo. Butuh waktu sampai dia kepikiran buat nyegah, dan pada saat itu Ron udah berhenti nabrakin kepalanya sendiri.
“…Kau tahu? Aku ngerti, kok. Maksudku, aku juga suka Renji, dengan caraku sendiri, oke? Bukan cinta, lebih kayak… kagum banget sama dia. Jadi aku paham perasaan itu. Saking pahamnya sampai sakit rasanya…”
Ron menyandarkan dahinya ke dinding, mengepalkan kedua tangan. Entah kenapa dia terlihat sangat frustrasi. Dia bahkan menggertakkan gigi sampai terdengar jelas.
Yume menarik Ron dari bahu dan dagunya. “Ayo, sini!” Ia menarik Ron lebih dekat, memaksanya menatap wajahnya. Dari yang bisa Yume lihat, dahi Ron memerah, tapi untungnya tidak berdarah.
“Oke. Sepertinya kamu baik-baik saja.”
“…B-Berhenti!”
Ron menepis tangan Yume dan memalingkan muka.
“A-Aku bisa jatuh padamu, lho…”
“Hmm? Jatuh ke mana?”
“Jatuh… di hati.”
“Hmm. Emangnya bisa ya jatuh gitu? Kayak… wusss, gedebuk.”
“…Aku lagi jatuh sekarang. Parah banget, oke? Gimana kalau nanti aku nggak bisa ngelupain kamu lagi…?”
“Yume malah lebih senang kalau kamu ingat dia, bukan lupa dia.”
“Itu maksudku… Cara kamu ngomong kayak gitu…”
Yume sebenarnya nggak sepenuhnya ngerti maksud Ron. Saat ia memiringkan kepalanya, Ron berdeham pelan, seakan ingin meredakan suasana dan kembali ke topik semula.
“Dengar… soal Renji.”
“Iya. Menurutmu dia di mana sekarang?”
“Bisa nggak… kamu biarin dia sendiri dulu?”
Nada suara Ron berubah drastis. Jadi serius.
Yume menatap wajah Ron. Ia sempat berpikir Ron mungkin akan menangis. Tapi ternyata tidak. Ekspresinya aneh. Matanya kosong, tapi wajahnya berkedut, seolah mau senyum tapi nggak jadi. Keningnya berkerut, dan dia juga terlihat marah.
“Kau pasti belum tahu. Dia nggak bakal cerita sendiri. Memang begitu orangnya, Renji itu.”
“Cerita…? Tentang apa?”
“Kau ingat Sassa?”
“Yang cewek itu, kan? Yang satu tim sama kalian.”
“Nama aku kamu lupa, tapi Sassa kamu ingat? …Yah, sudahlah. Jadi, Sassa itu…”
“Sassa kenapa…?”
Sebelum Ron sempat menyelesaikan kalimatnya, Yume sudah merasa ia tahu apa yang akan Ron katakan.
Dan ternyata itu persis seperti yang ia duga.
6. Kita yang Tak Bisa Sendiri
Dia tak pernah melupakan saat pertama kali kehilangan seorang rekan.
Itu sudah terjadi lama sekali, jadi rasa sakitnya tidak lagi menghantui setiap saat. Tapi setiap kali mengingat Manato, Yume selalu ingin melolong seperti serigala di bawah cahaya bulan.
Yume memang menyukai serigala. Sayangnya, dia bukan serigala, jadi dia tak bisa benar-benar melolong. Dia tak tahu kenapa suara lolongan serigala terdengar begitu sepi, tapi mereka hidup dalam kawanan, dipimpin oleh sepasang alfa. Jika ada anggota yang tersesat atau mati, mereka akan melolong berulang kali. Itu yang dikatakan gurunya di guild hunter, jadi Yume tahu itu bukan sekadar cerita kosong. Serigala-serigala itu mungkin sedang memanggil kembali mereka yang telah pergi. Yume sendiri ingin sekali bertemu kembali dengan teman-temannya, sampai rasanya ia juga ingin melolong. Tapi apapun yang dilakukan, yang mati tak akan bisa kembali.
Kehilangan yang kedua pun menyakitkan. Bahkan mungkin lebih menyakitkan ketika mereka kehilangan Moguzo. Mereka sudah bersama lebih lama. Tidak, lebih dari itu—dibanding kehilangan satu orang yang kau sayangi, kehilangan dua jelas lebih menyakitkan. Rasanya seperti luka lama yang kembali disayat.
Setelah itu, Yume beberapa kali bertemu Renji di dek, tapi mereka hanya saling menyapa sekilas. Dari kelihatannya, Renji pun jarang berbicara dengan rekan-rekannya sendiri: Ron, Adachi si mage berkacamata, dan Chibi sang priest.
Renji, Ron, Adachi yang judes dan susah didekati, Chibi-chan yang pendiam—atau lebih tepatnya, begitu sunyi hingga nyaris tak terdengar suaranya—serta Sassa yang kini telah tiada, semuanya datang ke Grimgar pada hari yang sama dengan Yume dan kelompoknya. Apa yang bisa menyatukan mereka? Mungkin bisa dibilang mereka seangkatan? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Yume tidak akan berpura-pura tak peduli—karena sejujurnya, dia memang ingin tahu. Tapi meskipun mereka menceritakan segalanya, apa yang bisa dia lakukan? Kalau mereka ingin berbagi, Yume akan mendengarkan dengan senang hati. Tapi memaksa mereka untuk membuka diri rasanya tidak benar.
Yume mengabdikan dirinya berlatih bersama Momohina.
Yume yang dulu mungkin akan melamun, atau menyibukkan diri dengan hal-hal lain supaya tak perlu memikirkan Haruhiro, Renji, atau yang lainnya. Apa yang dia lakukan sekarang memang mirip, tapi ada bedanya.
Sebanyak apapun ia memikirkannya, ada hal-hal yang memang tak bisa ia lakukan. Hal-hal itu harus ia sisihkan, dan untuk sisanya—ia harus berusaha sekuat tenaga. Hanya itu yang bisa ia lakukan.
Pada malam sebelum kapal Bachrose-go merapat di Nugwidu, Yume menjalani latihan tanding tanpa batas waktu melawan Momohina.
Tak ada syarat khusus untuk menang. Mereka sudah terlalu sering bertarung bersama. Keduanya tahu kapan seseorang menang atau kalah. Tapi itu bukan intinya. Dalam pertarungan serius, Yume nyaris tak punya peluang untuk menang melawan Momohina. Yang penting di sini adalah: bisakah ia membuat Momohina mengakui dirinya? Dalam arti tertentu, ini adalah ujian kelulusannya.
Mereka saling berhadapan di geladak, lalu menyentuhkan punggung tangan mereka dengan ringan. Begitu Yume berpikir, Oke, saatnya menyerang, Momohina langsung menangkap pergelangan tangannya. Sebelum Yume sempat berseru kaget, tubuhnya sudah dilempar. Dari awal saja dia sudah berada di posisi yang kurang menguntungkan, dan giliran menyerang belakangan membuat segalanya makin kacau. Yume panik. Tapi bahkan dia pun bisa menyadari itu, jadi dia berusaha menenangkan diri sebaik mungkin.
Saat ia mencoba menjaga jarak, Momohina langsung menutup celah dan menangkapnya. Dengan mudah, Momohina mengunci persendiannya. Yume kembali dilempar.
Momohina berbeda dari biasanya. Wajahnya datar sepanjang waktu. Gerakannya pun—entah bagaimana—terasa asing. Seolah Yume sedang menghadapi sosok Momohina yang tak ia kenal.
Yume tak tenang—dia kesal. Bukan, lebih dari itu. Dia marah.
Seharusnya bukan begini. Yume berniat melawan Momohina dengan sepenuh hati. Bagaimanapun juga, Momohina-lah yang telah membentuk cara bertarung Yume dari awal. Dialah yang mengajari semua yang sekarang bisa ia lakukan. Meski kepribadiannya tidak cocok untuk jadi pengajar, bagi Yume, Momohina sudah seperti sosok ibu.
Dan karena itu, pertarungan ini tak seharusnya berjalan seperti ini.
Momohina tetap diam, dan gerakannya cepat serta licin.
Emosi Yume semakin memuncak. Dia tahu betul itu akan menjadi bencana, tapi dia tak bisa menahannya. Saat emosinya terbakar, seluruh tubuhnya ikut menegang. Gerakannya pun jadi terlalu lurus—terlalu mudah ditebak.
Itu adalah kekalahan yang menyedihkan. Bukan sekadar kalah telak—dia benar-benar dihancurkan.
Dia dipenuhi memar di sekujur tubuh, dengan nyeri di bahu, lengan, pergelangan tangan, dan jari-jarinya—ditambah beberapa tulang yang patah. Chibi-chan menyembuhkannya dengan sihir cahaya, jadi luka-luka fisiknya memang tak tersisa, tapi perasaan murung tetap menghantui. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia merasa sebegitu tak berdaya—mungkin sejak awal pelatihan di pulau dulu.
Tapi, dia paham apa yang ingin ditunjukkan Momohina padanya.
“…Jadi bukan cuma soal kekuatan dan teknik, ya? Tapi juga soal siapa lawan kita?”
“Betul banget! Itu baru Yumeryun-ku! Intuisimu tajam juga, ya. Bagus, bagus! Kamu ngerti maksudnya!”
Momohina menepuk kepala Yume. Sosok ceria yang biasanya pun sudah kembali.
Selama ini, Yume berlatih langsung di bawah Momohina. Tak berlebihan rasanya kalau dibilang Momohina tahu segalanya tentang dirinya. Dan meski Yume mengerahkan seluruh kemampuannya melawan lawan seperti itu, hasilnya tetap saja—dia dihancurkan tanpa ampun. Kalau Yume benar-benar ingin menunjukkan seberapa besar kemajuan yang dia raih, setidaknya dia harus mencoba satu serangan yang bisa mengejutkan Momohina, walau hanya sedikit.
Berbeda dengan Yume yang menjalankan semua yang diajarkan dengan tingkat kepatuhan konyol, Momohina justru memperagakan berbagai lemparan dan teknik kuncian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Yume dibuat bingung, terpancing, dan kehilangan ritme—persis seperti yang diharapkan. Tak mampu menanggapinya dengan benar, dia pun berakhir dengan penampilan yang memalukan.
Padahal dia sudah belajar lebih keras dari siapa pun. Membangun ototnya, mempercepat refleksnya, menyempurnakan tekniknya. Tapi tetap saja—semua itu belum cukup.
Tergantung siapa lawannya dan bagaimana cara dia bertarung, bentuk sebuah pertempuran bisa berubah drastis. Intinya, bahkan petarung lemah pun bisa menang melawan yang kuat—asal tahu cara bermainnya dengan tepat. Setidaknya, kemungkinan itu ada.
Sebaliknya, kalau petarung kuat bertindak terlalu sombong, bisa saja yang lemah menjebaknya. Bahkan kalau si kuat tidak lengah sekalipun, kadang-kadang si lemah bisa melakukan sesuatu yang tak terduga dan menjatuhkannya.
Apa pun bisa terjadi kapan saja. Tidak ada yang mutlak.
Itulah pelajaran terakhir yang diajarkan Momohina pada Yume.
Yume tidur nyenyak di dalam tempat tidurnya yang tergantung seperti ayunan. Ketika dia bangun dan naik ke geladak, daratan tampak di kejauhan. Dia menitikkan air mata, hanya sedikit. Yume akhirnya kembali.
Bachrose-go menjatuhkan jangkar di pelabuhan Nugwidu sekitar tengah hari.
Orang-orang Zwiba mungkin akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Banyak dari mereka berkumpul di dermaga saat kapalnya mulai mendekat. Tapi mereka tidak bersorak, tidak melambaikan tangan. Bukan hanya diam, mereka juga terlihat… tak biasa. Mereka humanoid, tapi kulit mereka berwarna abu-abu kehitaman seperti batu, dan tak sehelai rambut pun tumbuh di kepala mereka. Mata mereka hitam legam, tanpa bagian putih sedikit pun, dan wajah, lengan, kaki—hampir seluruh tubuh mereka—dipenuhi pola garis-garis biru dan kuning. Pakaian mereka didominasi warna cokelat, ungu, dan warna gelap lainnya. Masing-masing membawa tongkat panjang dan ramping. Tanpa pengecualian. Tongkat-tongkat itu bukan dari kayu, tapi logam. Mengilap, dengan ujung yang berbeda-beda bentuknya.
Saat Kisaragi menjulurkan tangannya dari sisi kapal dan mengacungkan jempol ke arah mereka, para Zwiba serempak menghentakkan ujung tongkat mereka ke tanah dua kali.
“Malu-malu semua, ya?”
Apa benar itu masalahnya? Dalam hati, Yume sebenarnya agak takut turun dari kapal. Tapi begitu melihat Kisaragi dan Momohina menuruni tangga kapal seperti tidak ada apa-apa, memberi jempol lagi ke para Zwiba, lalu mulai menepuk-nepuk bahu mereka, Yume pun merasa sepertinya aman-aman saja.
Begitu ia turun dan mendekat, yang langsung terasa adalah aroma manis dan lembut dari para Zwiba—seperti kue baru matang dari oven. Bukan cuma warnanya yang aneh; kulit mereka juga punya tekstur seperti batu. Mata mereka yang hitam memiliki garis-garis keemasan di belakangnya. Cara mereka bergerak pelan sambil menoleh ke arahnya terasa begitu asing, dan begitu indah sampai-sampai Yume refleks mengembuskan napas takjub. Kaki mereka telanjang tanpa alas, dan tangan serta kaki mereka masing-masing punya tujuh jari.
Bagi Yume, semua Zwiba tampak sama. Ia tak bisa membedakan mereka satu per satu. Tapi ada satu Zwiba yang lebih pendek, dengan pola putih di seluruh kepala. Tongkat yang ia bawa pun tak berwarna—bening seperti kaca. Saat Kisaragi berbicara padanya dengan banyak gerakan tangan dan tubuh, untuk pertama kalinya Yume mendengar bahasa mereka.
“Uhh. Tohh. Nhh. Tohhto. Muhh. Ohh. Nhh. Tohhto. Nhh. Tohh. Uhh. Tohh.”
Tentu saja, Yume sama sekali tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Ia sudah pernah mendengar banyak bahasa sebelumnya, tapi bahasa para Zwiba jelas termasuk yang paling aneh. Siapa sangka ada orang yang bicara seperti itu? Dunia ini memang luas.
Hari itu, para Zwiba mengundang Kisaragi, Momohina, Yume, dan Tim Renji ke dalam sebuah bangunan besar, dan menyambut mereka di sana.
Meski begitu, “penyambutan” itu sebenarnya hanya berupa makanan dan minuman yang dihidangkan di atas lantai batu yang luas dan kosong tanpa hiasan apa pun—tanpa nyanyian, tanpa tarian. Makanan yang disajikan didominasi oleh ikan, sayuran hijau, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Jumlahnya melimpah, dan semua hidangan terasa seperti dibuat untuk menonjolkan rasa alami dari bahan-bahannya. Bumbunya ringan sekali, bahkan hampir tak terasa. Tak ada yang asin. Minumannya pun seperti jus buah yang dicampur air hingga rasanya nyaris hilang.
“Mereka nggak punya minuman keras gitu, ya…?” gumam Ron dengan nada kecewa, tapi tampaknya Zwiba memang tak punya kebiasaan minum alkohol. Mereka juga tak suka bernyanyi atau menari, dan cenderung menghindari berbicara di depan orang lain. Yang paling mereka sukai adalah berbaring diam di lantai, tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau terlalu lama begitu, mereka bisa tertidur, jadi mereka biasanya berhenti sebelum benar-benar lelap. Begitulah cara Kisaragi menjelaskan mereka.
Malam itu, semuanya tidur di ruangan yang sama. Para Zwiba tidak menggunakan alas tidur, bantal, atau semacamnya, jadi Yume pun tidur langsung di atas lantai batu. Saat terbangun, ia mendapati dirinya sudah berselimut. Sepertinya seseorang menyelimutinya saat ia tertidur. Saat matanya menyapu ruangan yang gelap, ia melihat dua Zwiba sedang berjalan pelan-pelan membawa selimut sambil tetap menggenggam tongkat mereka. Setelah itu, Yume kembali terlelap dalam tidur yang dalam.
Untuk membantu Yume dan Tim Renji dalam perjalanan mereka kembali ke Altana, kaum Zwiba menyiapkan naga-kuda sebagai tunggangan. Naga-kuda adalah sejenis naga kecil yang berjalan dengan dua kaki belakang mereka. Biasanya, naga-kuda yang dibesarkan dalam penangkaran akan dipotong sayapnya. Namun, naga-kuda milik Zwiba dibiarkan memiliki sayap utuh, memungkinkan mereka meluncur dalam jarak pendek atau bahkan berlari di atas air. Yume pernah mendengar kalau naga-kuda tidak akan patuh atau mau ditunggangi kalau sayap mereka tidak dipotong. Tapi naga-kuda milik Zwiba ternyata jinak dan bersahabat.
Yume dan Tim Renji dilepas kepergiannya oleh Kisaragi, Momohina, kru Bachrose-go yang dipimpin oleh Kapten Anjolina, serta lebih dari seratus orang Zwiba, saat mereka berangkat dari Nugwidu pada pagi hari.
Berpisah dengan Momohina membuat hati Yume sedikit berat, dan ia sempat khawatir akan terbawa suasana. Tapi Momohina dan Kisaragi justru bersikap santai seolah-olah itu hal sepele, sehingga Yume pun bisa meninggalkan mereka sambil tersenyum.
“Sampai ketemu lagi, Yumeryun!”
“Iya, sampai jumpa.”
“Sampaikan salam untuk teman-teman satu party-mu, ya.”
“Momo-san, Gicchon, kalian juga sampaikan salam Yume buat teman-teman kalian. Kayak Ginzy, dan Giancarlulun. Oh, sama Jimmy-chan juga, ya.”
Adachi, si mage berkacamata, dengan percaya diri mengatakan bahwa dia tahu jalan kembali ke Altana dan tak mungkin tersesat. Jadi Yume memutuskan untuk mempercayakan arah pada Adachi. Lagi pula, selama mereka mengikuti Pegunungan Tenryu ke arah barat, seharusnya semuanya akan baik-baik saja.
Saat kuda-naga milik kaum Zwiba menghadapi medan yang tidak rata, mereka akan mengepakkan sayap dan melayang rendah sambil terus bergerak ke depan. Mereka sering melakukannya, dan sensasi melayang yang unik itu sempat membuat Yume merasa mual, tapi ia cepat terbiasa. Renji jelas baik-baik saja, begitu juga Ron dan Chibi-chan. Adachi saja yang sempat pucat pasi, hanya bisa komat-kamit, “Mual banget, sumpah, mual banget…” Meski begitu, dia tetap mengikuti rombongan tanpa tertinggal.
Kuda-naga itu bergerak dengan kecepatan yang cukup baik, tapi kalau sudah lapar, jangan harap mereka mau bergerak satu langkah pun. Mereka hewan omnivora, dan bisa makan apa saja—daun dan batang tanaman, akar, serangga, hewan kecil, bangkai—pokoknya nyaris segalanya. Jadi mereka bisa dilepas begitu saja untuk berburu atau mencari makan sendiri, tanpa perlu disiapkan pakan. Mereka akan mengunyah apa pun yang ada di sekitar, lalu kembali sendiri begitu kenyang.
Suatu kali, Ron kesal dan mencoba menyeret kembali kuda-naganya saat masih makan. Hasilnya si kuda-naga ngambek dan tidak mau ditunggangi lagi. Akhirnya masalah itu diselesaikan dengan menukar tunggangan dengan Yume, tapi dari situ mereka sadar kalau makhluk itu bisa keras kepala juga. Harus hati-hati.
Yume dan Tim Renji akan terus bergerak sampai tunggangan mereka berhenti sendiri. Kalau sudah begitu, mereka ikut berhenti, lalu makan atau tidur. Cuma Adachi yang mengeluh karena katanya “bikin jadwalku kacau.” Tim Renji memang sudah terbiasa bepergian jauh.
Bepergian bersama mereka seperti ini membuat Yume bisa melihat dengan jelas bentuk kelompok mereka, juga kepribadian masing-masing anggotanya. Mempelajari dan mencoba memahami mereka sempat menjadi hal yang menarik baginya.
Ron memang kadang menyebalkan, tapi saat mereka sedang berjalan dan tidak beristirahat, dia hampir tidak pernah bicara. Malah sering menawarkan diri untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan kasar. Adachi, yang terlihat cerdas, lebih sering berperan sebagai tempat berdiskusi bagi Renji. Sementara Chibi-chan adalah tipe pendiam yang mendukung kelompok lewat banyak hal kecil yang nyaris tak terlihat.
Renji sendiri terasa sangat mengintimidasi, dan dia bisa membuat rekan-rekannya patuh tanpa perlu adu mulut. Yume dulu mengira kelompok mereka seperti itu—Renji yang dominan, yang lain tak bisa melawan. Tapi sekarang… rasanya tidak seperti itu. Setidaknya, bukan yang ia lihat saat ini.
Memang benar kalau Renji punya aura yang kuat dan menakutkan. Ia tidak ramah sama sekali. Bahkan pada rekan-rekannya sendiri, dia bicara secara langsung dan to the point. Ia tak pernah bercanda, tak pernah tertawa, dan tidak basa-basi. Meski dikelilingi teman seperjalanan, Renji terasa seperti orang yang benar-benar sendirian. Tapi Ron dan yang lainnya sudah menerima sifat itu. Mereka tahu Renji tidak suka jika orang lain terlalu mencemaskan dirinya, jadi mereka sengaja membiarkannya sendiri. Meski begitu, mereka tetap mengajak bicara saat dibutuhkan—dan Renji pun tidak mengabaikan mereka ketika itu terjadi.
Apa yang terjadi pada Sassa pasti termasuk bagian dari semua itu. Renji sedang terluka. Kalau ada orang luar yang tidak tahu latar belakangnya, mungkin mereka tidak akan mengira begitu, tapi Renji benar-benar terpukul—dengan caranya sendiri. Ron, Adachi, dan Chibi-chan pun pasti sama. Mereka tidak memperlihatkan kesedihan, tidak terlihat khawatir, juga tidak berbicara soal masa lalu. Mereka hanya terus melangkah menuju Altana. Mungkin memang seperti itulah cara mereka menjalani perjalanan selama ini. Bersama Sassa. Salah satu rekan mereka yang berharga telah tiada. Tapi mereka tidak menangisinya. Mereka menerima kenyataan itu dalam diam.
Pada hari ketiga setelah mereka berangkat dari Nugwidu, mereka memasuki Dataran Quickiwnd. Kata Adachi, kalau tidak ada halangan, mereka akan tiba di Altana dalam empat atau lima hari lagi. Tak seberapa lama.
Menjelang matahari terbenam, naga-kuda mereka berhenti di padang terbuka, dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana.
Di tim Renji, Adachi yang bertugas memasak. Ia paling rewel soal rasa, dan siapa pun yang masak selain dia pasti bakal dikomentari. Katanya, itulah yang membuat dia akhirnya ditunjuk jadi koki. Malam itu, mereka makan bubur dengan daging kering, sayuran, dan jamur. Wanginya luar biasa menggugah selera. Adachi punya banyak bumbu dan rempah-rempah, dan bisa mengolah bahan seadanya jadi makanan enak. Kemampuannya benar-benar patut diacungi jempol.
Ron selalu langsung mendengkur pelan begitu berbaring. Dia bisa tidur di mana saja, kapan saja, selama diizinkan.
Chibi-chan kadang-kadang meringkuk menjadi bola kecil lebih mungil dari biasanya, lalu di detik berikutnya sudah duduk, atau malah menghilang, lalu muncul lagi. Tingkah laku Chibi-chan selalu terasa penuh teka-teki, tapi rekan-rekannya sama sekali tak menganggapnya aneh. Yume sering mencoba mengajaknya bicara setiap kali ada kesempatan, namun sembilan dari sepuluh kali, jawaban Chibi-chan tak pernah lebih dari, “Iya,” atau, “Nggak.” Percakapan pun tak pernah berkembang menjadi sesuatu yang berarti.
Meski tak benar-benar mengerti Chibi-chan, Yume bisa merasakan kesungguhan dan ketulusan dalam setiap tindakannya. Chibi-chan adalah tipe orang yang rela memberikan segalanya demi teman-temannya. Saat Sassa masih ada, formasi Tim Renji terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan. Mungkinkah ada hubungan khusus antara Chibi-chan dan Sassa, seperti yang biasa terjadi dalam kelompok seperti itu? Yume sempat memikirkannya, dan ia tak bisa menahan diri untuk berharap bisa membicarakannya secara langsung dengan Chibi-chan. Tapi mungkin itu sudah termasuk ikut campur urusan orang lain.
Renji selalu menata barang-barangnya dengan rapi, menggunakan salah satunya sebagai bantal, dan selalu tidur dengan posisi yang sama. Ia hanya memakai peralatan makan dan perlengkapan mandinya sendiri. Ia mencukur jenggot dengan teliti, dan menyisir rambutnya rapi, meskipun rambutnya pendek. Ia melakukan semua kebiasaannya dengan urutan dan cara yang sama setiap hari. Yume baru sadar sekarang—Renji ternyata orang yang sangat teratur.
Yume selalu menjalani segalanya sesuka hati. Dia minum sebanyak yang bisa ia minum saat ada kesempatan, dan hal yang sama berlaku untuk makanan—meski begitu, dia bukan tipe yang pilih-pilih. Dia tidur ketika malam tiba, bergerak ketika hari mulai terang, tapi kalau harus melakukan sebaliknya pun, dia tidak masalah. Kalau dia ingin tidur, biasanya bisa. Dan kalau tidak bisa… ya, berarti harus tetap terjaga sampai rasa kantuk datang. Rasanya, sejak tinggal di pulau ini, dia jadi makin semaunya sendiri.
Kelihatannya malam ini akan jadi salah satu malam di mana ia tak bisa tidur.
Renji juga sedang berbaring, tapi mungkin matanya bahkan tidak tertutup. Mereka sedang berada di tengah ladang gelap gulita, dan apinya sudah mereka padamkan, jadi tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Tetap saja, Yume bisa merasakan kehadirannya.
“Renji.”
“Iya.”
Renji langsung menjawab. Ternyata benar, dia memang belum tidur.
“Kenapa kamu pergi ke Benua Merah?”
Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yume langsung menyesal. Bukan itu maksudnya. Dia tidak berniat menyinggung soal Sassa. Itulah sebabnya dia mencoba membicarakan hal lain. Tapi Renji baru saja kembali dari Benua Merah. Kemungkinan besar, di sanalah Sassa kehilangan nyawanya. Yume takut pertanyaannya malah membuka luka lama.
“Karena di sini rasanya sesak.”
Tapi mungkin dia tidak perlu khawatir. Renji menjawab dengan cepat.
“Ada seorang pria di Altana, Garlan Vedoy namanya. Katanya dia ingin ketemu dengan kami. Dia itu semacam markgraf—semacam bangsawan gitu—dari Kerajaan Arabakia, dan tinggal di sebuah rumah tinggi sekali yang namanya Menara Tenboro. Ketika aku menolak, Britney dari Kantor Korps Relawan langsung ribut. Itu mengesalkan sekali. Sampai-sampai aku bilang, kalau si pria itu ingin ketemu aku, ya suruh aja dia turun dari menaranya sendiri.”
“Woo… Jadi, um, Pedoy-san…?”
“Vedoy.”
“Si Vedodin-san itu akhirnya turun, nggak?”
“…Nggak. Dari omongan Britney sih, katanya dia marah banget. Entah dia pikir dirinya siapa, yang jelas dia nganggep dirinya penting banget. Aku paling nggak tahan sama orang model begitu, sampai bikin mual.”
“Yah, kamu kan bukan… orang Grimgar, ya? Yume juga bukan, sih. Pasti kesel banget, ditarik-tarik ke urusan Grimgar kayak gitu.”
“Benar. Nggak cuma Vedoy, para prajurit relawan lainnya juga malah kayak ngerecokin.”
“Makanya kalian ke Benua Merah, ya?”
“Aku maksa mereka ikut egoismeku.”
Renji kelihatan kayak mau ngomong sesuatu setelah itu, tapi ditelannya lagi.
Sebenarnya Yume tahu dia harus diam… tapi dia nggak bisa nahan diri.
“…Tapi kelihatannya nggak semua orang ngerasa begitu. Mereka nggak ngelakuin sesuatu cuma karena kamu nyuruh. Yume bisa lihat kalau semua orang tetap bersamamu karena mereka memang mau jadi temanmu.”
“Itu sudut pandangmu.”
“Yahh. Kamu benar juga. Yume nggak bisa yakin soal apa pun… selain dirinya sendiri.”
“Mana mungkin kamu tahu apa yang dirasakan orang lain.”
“Kalau begitu, bukannya aneh juga kamu sok tahu dan mutusin sendiri apa yang mereka rasakan?”
“…Iya juga.”
“Memang susah sih nanyain langsung ke orang, ‘Gimana perasaan kalian?’ Tapi, kalau kamu bareng mereka, kamu bisa tanya kapan aja, kan?”
Renji tertawa kecil, lalu berkata, “Iya,” sekali lagi.
“Maaf, ya. Aku tahu kamu kepisah dari teman-temanmu, dan sekarang sendirian.”
“Yume nggak benar-benar sendirian, kok.”
“…Huh?”
“Kamu ada di sini, terus yang lain juga. Sebelumnya ada Momo-san. Lalu Gicchon datang dan nyelamatin kami. Jadi Yume nggak sendiri.”
“…Gitu ya?”
Setelah itu, Renji terdiam. Yume tahu dia belum tertidur. Tapi matanya sendiri mulai berat. Saat kesadarannya mulai memudar, sesaat sebelum benar-benar tertidur, Yume merasa mendengar suara Renji.
“Yang benar-benar sendirian itu cuma orang-orang yang udah mati, ya…?”
7. Ingat Aku
Di kejauhan, tampak sebuah kota berdinding. Yume tidak merasa nostalgia saat melihatnya. Perasaannya lebih ke, Lucu juga, kecil gitu ya?
Altana bukanlah kota yang terbentuk secara alami—dari orang-orang yang berkumpul, membangun rumah, mengolah lahan, memelihara ternak, lalu populasinya tumbuh sedikit demi sedikit. Sebaliknya, kota ini berawal dari sekelompok kecil orang yang diusir ke selatan Pegunungan Tenryu oleh Aliansi Para Raja. Mereka membangun sebuah benteng kokoh demi melindungi diri dari serangan musuh. Dari situlah Altana bermula.
Sekarang, memang ada ladang, padang rumput, dan desa-desa kecil di sekitar Altana, membentuk gambaran khas antara kota dan wilayah penyangganya. Tapi pada awalnya, tempat ini hanyalah sebuah benteng yang berdiri sendiri.
Dulu, pusat wilayah Grimgar ada lebih jauh ke utara. Di sekitar sini, satu-satunya pemukiman besar hanyalah kota Damuro. Itulah sebabnya, setelah Aliansi Para Raja berhasil merebut Damuro dan Tambang Cyrene, mereka kehilangan minat terhadap wilayah perbatasan ini. Ras-ras kuat seperti orc dan undead pun mundur ke utara, meninggalkan wilayah ini pada para kobold dan goblin. Goblin mengambil alih Damuro, sementara kobold menguasai Cyrene, menjadikannya basis kekuatan masing-masing.
Kerajaan Arabakia sendiri sudah lama menyuap goblin Damuro agar menutup mata terhadap pembangunan Altana. Itu konon alasan mengapa kerajaan belum juga mengirim pasukan untuk merebut kembali Damuro.
Semua ini, Yume sadari, sebenarnya tidak terlalu ia pahami juga.
Saat pertama kali menjadi prajurit relawan, Yume telah membunuh banyak goblin di Damuro. Awalnya terasa salah, tapi lama-kelamaan ia terbiasa. Kalau sekarang ada goblin menyerangnya, dia bisa menghabisinya tanpa ragu. Tapi berbeda dengan waktu itu, kini Yume bisa berpikir, Apa ini benar-benar nggak apa-apa?
Suatu hari, ia terbangun di Grimgar, lalu berakhir menjadi prajurit relawan. Ia sebenarnya tidak membenci goblin. Walau bentuknya mirip manusia, mereka bukan manusia, dan Yume tak bisa memahami bahasa mereka. Tapi mereka juga tidak semenakutkan orc. Mereka biasa terlihat di Damuro, dekat Altana, dan karena itu mudah diburu. Maksudnya, dulu mereka adalah musuh berbahaya. Manato—teman mereka—tewas karena sekelompok goblin dan satu hobgoblin. Tapi mereka sudah membalaskan dendam itu. Yume telah membunuh banyak goblin. Mungkin saja mereka juga punya teman dan keluarga.
Kelompok Forgan—yang dipimpin orc bernama Jumbo—bahkan punya pawang binatang goblin bernama Onsa. Yume sendiri suka binatang. Mungkin kalau dalam keadaan lain, dia bisa akrab dengan Onsa. Tapi mereka tak akan pernah bisa jadi teman.
Karena goblin adalah musuh.
Benarkah begitu?
Yume bukan penduduk Kerajaan Arabakia yang telah ditaklukkan oleh Aliansi Para Raja. Ia sebenarnya tidak punya alasan untuk memusuhi para orc, undead, goblin, atau kobold. Altana bukanlah kampung halamannya.
Namun tetap saja, saat mereka semakin dekat, Yume berpikir, Rumah Yume di sini.
Dari penampilannya, Altana masihlah Altana. Bukit di sebelahnya masih dipenuhi nisan, dan menara tersegel yang menjulang di atas kota itu tetap seperti yang ia ingat.
Hari sudah sore, jadi mungkin ia akan menunda sampai besok, tapi terpikir olehnya untuk mengunjungi makam Manato dan Moguzo. Sudah cukup lama ia tak ke sana. Ia tak bisa sempat-sempatkan sebelumnya.
Meskipun ia pergi, mereka tak akan ada di sana menemuinya. Sekalipun ia punya banyak hal yang ingin ia ceritakan, mereka tak bisa mendengarnya. Tapi bagi Yume, mengenang mereka dan sesekali datang berziarah tetap memiliki makna.
Bagaimana ya cara Tim Renji mengenang Sassa? Renji mungkin enggan membicarakannya. Mungkin nanti ia akan tanya ke Ron atau Adachi.
Altana terlihat tak berubah dari kejauhan, tapi saat mereka mencoba masuk lewat gerbang utara, ternyata ada banyak prajurit dari Pasukan Perbatasan di sana, dan semuanya langsung ribut begitu melihat mereka.
“Hei, bukankah itu Renji?”
“Itu Renji, kan?”
“Renji kembali!”
“Itu Serigala Perak!”
“Renji! Serigala Perak kembali ke Altana!”
Para prajurit di sekitar gerbang dan di atas tembok mengangkat pedang atau tombak mereka ke udara, mengepalkan tangan ke atas sambil berseru ‘banzai,’ dan menyambut dengan gegap gempita. Yume hanya bisa melongo.
“…Ka,u populer banget ya, Renji? Apa itu… segila perak?”
“Serigala Perak.”
Adachi melirik Yume penuh jijik dari balik kacamatanya. Yume merasa Adachi mungkin sebaiknya tidak secepat itu menatap rendah orang lain secara terang-terangan.
“Rambut Renji kan perak? Makanya dia dipanggil begitu.”
“Wooooh. Keren juga. Tapi ‘Penunggang Naga’-nya Haru-kun juga nggak kalah hebat, lho.”
“…Iya sih, Penunggang Naga itu cukup keren.” Ron menaikkan alis dengan ragu. “Tetap aja, ini aneh. Maksudku, penjagaannya ketat banget.”
Chibi-chan menoleh ke sekeliling, pandangannya agak tertunduk. Sekilas memang tak terlihat, tapi gadis itu jauh lebih waspada dibanding kebanyakan orang.
Apa yang dipikirkan Renji saat melewati gerbang itu, melajukan kuda-naganya tanpa menoleh sedikit pun ke arah para penjaga? Ron dan yang lain mengikuti di belakangnya. Yume sempat ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk tetap ikut mereka sedikit lebih lama. Ada satu tempat yang harus ia kunjungi segera setelah kembali ke Altana. Tim Renji katanya juga akan ke sana lebih dulu.
Altana itu kecil. Bahkan masuk dari gerbang utara, mereka bisa langsung sampai ke distrik selatan dalam waktu singkat.
Bangunan yang mereka tuju mengibarkan bendera dengan simbol bulan sabit merah di atas latar putih, dan di depannya ada papan nama. Begitu melihat papan itu, Yume berseru, “Huh?! Mereka ganti papan nama, ya?! Huh?!”
“…Huh?” Ron kelihatan nggak ngerti maksudnya, tapi mata Chibi-chan langsung membelalak, dan ia menarik napas tajam, sementara Adachi bergumam, “Dia benar.” Renji sendiri kelihatan tak peduli. Buat dia, itu nggak penting.
Plang itu dulunya bertuliskan, “Tntra Prbtsn Altn Krps Prjrt Relwn Red Mon.” Tapi sekarang sudah diperbaiki jadi, “Tentara Perbatasan Altana – Korps Prajurit Relawan Red Moon.” Seharusnya seperti itulah bunyinya dari awal, hanya saja beberapa huruf di papan lama sudah memudar.
Begitu mereka menambatkan kuda-naga mereka di kandang dan masuk ke dalam, mereka menemukan sejumlah pria dan wanita yang terlihat seperti prajurit relawan di aula utama. Semua langsung ribut begitu melihat Renji, tapi tampaknya mereka semua agak segan, tak ada satu pun yang berani menyapanya.
“Renji…?”
Pria di balik meja, dengan tangan bersilang di dada, memiliki sorot mata yang berkilau dalam warna biru muda. Rambutnya masih hijau seperti biasa, dan ia mengenakan lipstik hitam serta pemerah pipi. Pakaian norak yang dikenakannya, serta gerakan tubuh yang gemulai, masih sama seperti saat pertama kali mereka bertemu, tapi entah kenapa, ada yang terasa sedikit berbeda.
“Britney.”
Renji tidak mengabaikan Britney. Sebenarnya, alasan dia datang ke kantor ini memang untuk melaporkan bahwa dia telah kembali.
Renji menaruh satu tangan dengan ringan di atas meja.
“Sudah lama. Kau tambah tua, ya, sejak terakhir kita bertemu?”
“Oh, jangan bilang begitu.”
Britney menutup wajahnya dengan kedua tangan.
“Aku sensitif soal itu. Aku ini orang penting sekarang. Nggak kayak kamu yang bisa hidup bebas dan liar, aku punya banyak yang harus dipikirkan. …Apalagi akhir-akhir ini.”
“Wahhh!”
Saat Yume bertepuk tangan tanpa sadar, mata Britney membelalak.
“A-A-Ada apa, tiba-tiba begitu?!”
“Oh, iya. Bri-chan, kamu jauh lebih tua dari Yume dan yang lain, ya? Ya wajar sih…”
“Jangan bilang ‘ya wajar sih’ sambil pasang muka puas begitu! Kurang ajar banget. Sungguh deh… Hah? Kamu… Eh, ini ada apa, ya?”
Britney menatap satu per satu—Renji, lalu Adachi, Ron, Chibi-chan, dan terakhir Yume—sambil menghitung mereka dengan jarinya.
“Jumlahnya sih benar, tapi formasinya berubah. Yume, kamu kan dulunya di kelompok Haruhiro, ya? Tapi aku dengar-dengar, grup Haruhiro itu sekarang MIA.”
“Em ai…?”
Yume memiringkan kepala dan berkedip-kedip pelan.
Tanah seperti berguncang.
Bukan, ternyata Yume-lah yang berguncang.
Chibi-chan buru-buru menopangnya. Yume nyaris terjatuh.
“Sassa sudah mati,” kata Renji datar. Lalu ia menoleh sedikit, mengangguk ke arah Yume. “Kalau dia, kami kebetulan bertemu di Kepulauan Zamrud. Sepertinya waktu itu dia sudah tidak bersama Haruhiro dan yang lain.”
Britney mengangkat bahu.
“Kok jadi ribet begini, sih. Jangan bikin hidupku makin susah, apalagi pas keadaan lagi darurat begini…”
“Darurat, maksudmu?” tanya Adachi.
“Deadhead jatuh.”
“Apa?” Renji mengerutkan kening. “Kalau Pos Lonesome Field dan Riverside?”
“Masih bertahan. Korps Prajurit Relawan sekarang memusatkan kekuatannya di Riverside. Lonesome enggak punya fasilitas untuk bertahan dalam pertempuran, jadi kemungkinan besar sudah dikosongkan.”
“Lalu kenapa kamu masih di Altana?”
“Soalnya masih ada prajurit relawan—kayak kalian ini, sayang-sayangku—yang belum bisa kami lacak. Kajiko dan Shinohara sudah di Riverside. Mereka pasti bisa mengurusnya.”
“Kajiko dari Wild Angels dan Shinohara dari Orion, ya…”
Adachi memasang wajah sulit. Yume mengenal keduanya. Mereka adalah prajurit relawan senior yang memimpin klan-klan besar.
“Lagipula, Tentara Perbatasan hanya mempekerjakanku sebagai kepala kantor ini.”
Britney mengeluarkan sebilah pisau entah dari mana, tersenyum miring sambil memutarnya di tangannya.
“Korps Prajurit Relawan bahkan nggak punya pemimpin. Kau pasti sudah lama tahu, tapi sejauh menyangkut Arabakia, prajurit relawan itu cuma pion yang bisa dibuang kapan saja.”
“Dan Tentara Perbatasan dengan barisan kroco-kroconya itu yang jadi pasukan utama mereka, ya…”
Ron mendecakkan lidahnya, kesal.
Suasana di kantor jadi sunyi dan tidak nyaman. Para prajurit relawan lainnya menunduk lesu.
Yume tahu seharusnya ia mendengarkan Britney. Ini pasti pembicaraan penting, tapi entah kenapa, semua itu nggak masuk ke kepalanya.
“Yume mau jalan dulu.”
“Tunggu, sayang.” Britney berusaha menghentikannya. Tapi Yume tetap keluar dari kantor tanpa ragu.
Setelah itu ia berjalan ke beberapa tempat, tapi dia sama sekali tidak ingat ke mana saja.
Matahari sudah rendah di langit. Yume berdiri di depan rumah penginapan para prajurit relawan. Baru ia ingat, kuda-naganya masih diikat di kantor tadi. Haruskah ia kembali menjemputnya? Tapi dia malas.
“Em ai e, ya…”
Apa maksudnya tadi? Seharusnya dia nanya lebih banyak ke Britney soal itu.
Ya. Belum terlambat. Yume bakal balik ke kantor lagi.
Kakinya terasa seperti ranting rapuh, enggan untuk bergerak. Atau mungkin, telapak kakinya telah menumbuhkan akar. Yume tahu. Sebenarnya, ia sudah tahu sejak meninggalkan kantor itu.
Yume tak ingin tahu. Tentang apa yang terjadi pada Haruhiro dan yang lainnya. Ia takut mengetahui kebenarannya. Meski begitu, ia harus tahu. Itu pun ia sadari.
Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap juga. Ia tak bisa terus berpura-pura tak tahu. Tapi meskipun jawabannya ada di luar sana, Yume tak punya keberanian untuk menghadapinya. Itulah sebabnya ia terus menundanya.
“Yume, ini nggak bener, tahu…”
Di dalam rumah penginapan tua itu, kenangan akan hari-hari dan bulan-bulan yang ia habiskan bersama rekan-rekannya berputar di kepalanya.
Pernah suatu kali, Manato berkata padanya—bahwa di antara mereka semua, mungkin justru Yume-lah yang paling berani. Yume hanya bisa tertawa getir mengingatnya. Manato jelas melebih-lebihkan. Ia bukan gadis pemberani. Ia hanya sering menerjang begitu saja tanpa pikir panjang. Sebenarnya, ia ceroboh. Yume tidak punya kekuatan untuk terus maju meski diliputi rasa takut. Ia manja. Lemah dan rapuh.
Sampai sekarang pun, kelemahan itu masih tinggal di dalam dirinya.
Ia ingin bisa berbicara secara jujur dan to the point. Tapi alasan kenapa ia sering melantur mungkin karena ia butuh bantalan itu—untuk meredam kenyataan. Ia ingin bisa diandalkan, tapi tetap saja tak mencoba menyelesaikan segalanya dengan cepat. Pada akhirnya, apa ia pikir dirinya sudah cukup seperti ini? Sama sekali tidak.
Sebelum malam sepenuhnya turun, Yume sudah meninggalkan rumah penginapan. Dia harus menjadi kuat—dan itulah yang ingin dia capai. Tapi cuma berharap tak akan cukup untuk membuatnya kuat. Manusia bisa berubah. Hanya saja, bukan dalam semalam.
“Sampai Yume bisa jadi kuat, Yume cuma bisa terus ngelakuin yang terbaik sebagai Yume yang lemah ini.”
Guild hunter terletak di distrik utara, dekat gerbang utara. Bangunannya dikelilingi pagar kayu, dan di halaman belakang ada kandang-kandang anjing serigala. Para hunter memang kurang suka keramaian kota, jadi seringkali hanya ada satu orang yang berjaga di sana. Yume masuk begitu saja tanpa dihentikan siapa pun, dan langsung menyapa anjing-anjing serigala di dalam kandang. Hampir semua tampak asing baginya—kecuali satu.
“Hei, Poochie. Lama nggak ketemu. Yang lain udah pada diambil, ya?”
Poochie menjilat-jilat jari Yume dari balik jeruji, sambil mengeluarkan rengekan manja. Apa dia memang selalu sejinak ini?
“Eh? Jangan-jangan, Poochie udah tambah tua, ya? Makanya sekarang jadi baik?”
“Hei.”
Sebuah suara datang dari atas.
Hmm, rasanya ini pernah kejadian sebelumnya, deh…
Begitu Yume mendongak, tampak seorang pria berjanggut menyembulkan kepalanya dari jendela atas.
“…Hah? Kau—”
“Uwaaah!” Yume sontak melompat kecil. “Master! Syukurlah Master ada di guild! Soalnya… ya, masuk akal juga sih kalau ternyata enggak!”
“Eh… tunggu. Kau itu dari mana aja… Eh, bukan. Sejak kapan kau… Bukan juga. Sebenarnya selama ini kau ngapain, hah…?”
“Kita punya sekandang hal buat dibahas hari ini!”
“Maksudmu segudang…?”
“Oh iya, itu. Seudang buat dibahas.”
“Bukan itu, segudang. Tapi ya, mau bahas kandang atau udang juga, aku nggak keberatan sih. Tapi tunggu, kamu…”
Tiba-tiba, nada suaranya berubah jadi agak lirih. Ada apa? Masuk angin? Guru Yume, hunter veteran Itsukushima, sedang mengusap matanya dan terdengar seperti menahan isak.
“Kamu benar-benar…”
“Hmm?”
Yume menggosok matanya dengan kedua tangan. Rasanya lembap. Itu air mata. Yume baru sadar kalau dia sedang menangis. Oh.
Ternyata Itsukushima juga menangis. Ohhh. Ya, Yume memang cengeng. Tapi, masa gurunya juga? Nggak mungkin… kan?
“Maaf ya, Master. Yume bikin Master khawatir, ya?”
“J-J-Jangan bodoh! Siapa juga yang… Yah, aku memang agak khawatir sih. M-Maksudku, aku dengar kelompokmu sempat dilaporkan hilang, kan? Tapi bukan berarti aku nanya-nanya orang soal kamu atau semacamnya, ya! Aku bukan tipe yang begitu. Aku cuma… dengar aja, kebetulan.”
“Yume pengen ketemu Master. Karena udah lama banget.”
“…I-Iya. A-Ah! Tapi tadi maksudku bukan begitu, ya! Bukannya aku pengen ketemu kamu sampai-sampai nongkrong terus di guild nungguin kamu muncul entah dari mana! Aku cuma… setuju aja udah lama nggak ketemu…”
“Master itu rumahnya Yume.”
“A-Aku rumahmu…?”
“Bukankah waktu itu Master yang bilang? Di akhir pelatihan dasar. ‘Kapan pun kau mau kembali, pintunya selalu terbuka.’”
“…Aku bilang begitu, ya? Sepertinya, memang pernah. Tapi aku ingat, kok. Entah kenapa, obrolan kecil kita selalu menempel di kepala. Aku ini… yah, semacam sosok ayah buatmu, kan?”
“Iya. Itu sebabnya Yume pulang.”
“Begitu ya.” Itsukushima mengangguk beberapa kali, lalu mengembuskan napas panjang. “…Begitu. Selamat datang kembali, Yume.”
“Yume sudah pulang, Master.”
“…Apa yang terjadi? Tapi kalau kau belum siap bicara, atau memang tidak bisa cerita, tidak apa-apa.”
“Banyak hal. Rasanya ingin cerita semuanya, tapi… mulai dari mana, ya? Yume juga bingung.”
“Tak apa. Tak perlu buru-buru. Pelan-pelan saja.” Itsukushima tersenyum. “Karena kau sudah pulang sekarang.”
Yume merasa ingin menangis. Ingin mandi. Ingin makan sepuasnya. Ingin tidur nyenyak. Yume benar-benar lemah. Tapi mungkin… sekarang setelah bertemu lagi dengan Itsukushima, dia bisa menjadi sedikit lebih kuat. Melihat wajahnya, mendengar suaranya—itu pasti cukup untuk membuatnya bisa bertahan sedikit lebih lama. Yume yang lemah harus mulai membangun kekuatannya, sedikit demi sedikit.
“Yang pasti, sekarang Yume tahu…”
Itsukushima beberapa kali menyentuh wajahnya, lalu membalikkan badan, menatap ke arah lain.
“Kalau belum makan malam, ayo makan.”
“Yume lapar banget.”
“Oke, akan kumasak se—”
Apakah Itsukushima atau Yume yang menyadarinya lebih dulu? Mungkin saja mereka menyadarinya di saat yang sama.
Itsukushima mengeluarkan suara terkejut, “Eh…?” Sementara itu, Yume menoleh ke arah utara. Guild Hunter terletak dekat gerbang utara, jadi dari sana tembok benteng yang mengelilingi Altana menjulang tinggi di hadapan mereka. Walaupun mereka belum pernah naik ke sana, sekarang tentara Pasukan Perbatasan sudah berada di atasnya, bersiap menghadapi musuh. Sebelum teriakan para prajurit terdengar, Yume lebih dulu melihat puluhan cahaya terbang melesat, seakan membelah kegelapan malam. Segera setelah itu, pekikan kasar dari para prajurit menyusul, dan jejak-jejak cahaya itu jatuh di sisi dalam tembok.
Salah satunya menancap di atap bangunan markas guild hunter. Api mulai menjalar.
“Anak panah api?!”
“Itu panah yang kebakar!”
Sesaat kemudian, serigala anjing di kandang melolong, lalu mulai panik. Denting lonceng terdengar nyaring, clang, clang, clang. “Serangan musuh! Serangan musuh!” teriak para prajurit dari atas tembok.
“Tunggu di sini!” kata Itsukushima pada Yume sebelum menghilang dari jendela. Sepertinya dia berniat turun ke bawah. Yume mencoba menenangkan serigala anjing yang menggonggong tak karuan. Beberapa dari mereka sampai menabrakkan diri ke jeruji kandang, dan Yume terpaksa membentak mereka.
“Ahhh…!” Ia melihat seorang prajurit jatuh dari atas tembok. Yume tidak sampai panik, tapi ia memahami bahwa Altana sedang diserang. Situasinya memang gawat. Tapi panik tidak akan membantu siapa pun.
“Yume!”
Itsukushima keluar dari bangunan itu. Di punggungnya tergantung busur dan tabung anak panah, dan ia membawa satu set lagi di tangannya.
“Kau nggak punya busur, kan? Pakai ini.”
“Siap, Pak!”
Yume menerima busur dan tabung anak panah dari Itsukushima. Satu-satunya senjata lain yang dibawanya hanyalah sebuah pisau besar, tapi sepertinya itu tidak jadi masalah.
Anak-anak panah berapi masih terus beterbangan melewati tembok. Satu-dua jatuh di halaman. Salah satunya mengenai kandang anjing serigala dan memantul. Yume segera menginjaknya untuk memadamkan api.
“Master, kalau terus begini, bukannya para anjing serigala bisa dalam bahaya?”
“Saat ini ada delapan ekor di sini. Tapi kalau dilepas ke jalan begitu saja, itu akan…”
“Lepasin aja! Nyaa, Yume mau ngelepasin mereka!”
Tak ada gembok di sana, jadi Yume membuka satu per satu kandangnya. Anjing-anjing serigala itu langsung melompat keluar. Saat Yume sibuk membukakan kandang, Itsukushima ikut membantu.
Sebelumnya, anjing-anjing itu tak mau mendengarkan Yume, tapi ketika Itsukushima meniup peluit dan menepuk-nepuk kepala mereka, semuanya langsung tenang. Yume sangat terkesan. Itulah guru Yume—memang hebat.
Yume meninggalkan Itsukushima di halaman bersama anjing-anjing itu, lalu pergi memeriksa jalan. Ia melihat para prajurit Pasukan Perbatasan menuju gerbang utara, sepertinya hendak bergabung dalam pertempuran. Beberapa prajurit relawan juga tampak di sana-sini.
“Master!” seru Yume saat ia berlari ke arah jalan.
“Oke!” sahut Itsukushima sambil memimpin para anjing serigala untuk mengikutinya.
Ide untuk membantu para prajurit sama sekali tidak terlintas di benaknya. Gerbang utara sudah kacau. Ia mencoba berbalik ke selatan, tapi suara yang luar biasa keras membuat Yume spontan menoleh.
Gerbang utara setengah terbuka. Prajurit-prajurit tergeletak di mana-mana.
“Mereka udah nembus?!” seru Itsukushima.
Yang jelas, bukan Pasukan Perbatasan yang membuka gerbang utara. Itu sudah pasti. Tidak mungkin mereka melakukannya. Musuh pasti menemukan cara untuk membukanya dari luar secara paksa. Itu berarti mereka akan membanjiri kota—tidak, bahkan bukan ‘akan.’ Sekeliling gerbang diterangi api penjaga dan lampu-lampu di dinding, jadi meskipun beberapa sudah jatuh, cahayanya masih cukup terang.
Sesosok besar membawa pedang besar yang muncul dari balik gerbang jelas bukan manusia. Tubuhnya kekar, kulitnya hijau—seorang orc. Orc itu menebas punggung salah satu prajurit yang sudah jatuh. Yang muncul berikutnya bukan orc, melainkan undead. Tombak undead itu menembus tubuh prajurit lain.
Pasukan Perbatasan Kerajaan Arabakia tampak tinggal selangkah lagi dari melarikan diri. Dengan kondisi seperti itu, mereka tidak mungkin bisa melawan balik.
“Yume, ke gerbang selatan!”
“Ya!”
Itsukushima berlari memimpin delapan anjing serigala, dan Yume mengikutinya. Menara tinggi bernama Menara Tenboro, tempat tinggal margrave, terletak hampir di tengah kota Altana. Distrik selatan ada di sisi lain alun-alun besar yang mengelilinginya.
Itsukushima langsung berlari ke arah Menara Tenboro. Ia mengambil rute paling pendek yang bisa ditempuh.
Yume menoleh ke belakang, cemas akan apa yang terjadi di dekat gerbang utara. Dari arah itu, sesuatu yang berwarna hitam melesat cepat ke arah mereka. Wujud-wujud itu tampak seperti binatang berkaki empat—sekumpulan hewan liar. Tapi lebih dari itu, satu—tidak, beberapa di antara mereka—tengah mengincar Yume secara langsung.
Serigala. Mereka sehitam malam.
Serigala hitam.
Ia tak bisa lari. Mereka pasti mengejar dan menyusul. Yang terdepan akan menerkam, lalu sisanya akan mengerubungi. Dalam sekejap saja, Yume akan tercabik-cabik. Apa yang harus ia lakukan? Tak perlu berpikir panjang.
Yume menghentikan langkahnya. Ia menarik napas. Mengembuskannya. Lalu, setelah menarik napas sekali lagi, tubuhnya secara naluriah mengambil posisi bertarung.
Serigala hitam terdepan sudah sangat dekat. Ia pasti akan menggigit lehernya—atau mungkin pergelangan tangan atau kakinya. Yume melangkah menyerong ke depan, menancapkan pisaunya ke leher serigala hitam itu. Serigala itu menjerit kaget sambil terpental. Langsung setelahnya, serigala hitam lain melompat menerjang. Yume menggunakan tangan kirinya untuk menekan kepala binatang itu ke bawah. Karena serigala itu sudah di udara, tidak perlu banyak tenaga. Kepalanya membentur tanah, dan suara erangan kesakitan terdengar dari mulutnya.
“Yume?!” seru Itsukushima. Suaranya tidak dekat. Ia berada agak jauh.
Kalau boleh jujur, Yume sebenarnya ingin melihat bagaimana keadaan Itsukushima dan anjing-anjing serigala itu. Tapi dia memilih untuk lebih dulu menangani para serigala hitam. Saat dia menumbangkan serigala hitam ketiga dan keempat, para orc dan undead mulai mendekat, jadi ia segera menarik anak panah dan memasangnya di busur. Ia menendang seekor serigala hitam, lalu melepaskan panah. Panah itu menembus pipi kiri salah satu orc. Targetnya sebenarnya adalah dahi, tapi sedikit meleset. Setelah itu, ia menghentakkan kaki ke punggung serigala hitam lain dan melompat ke udara. Dalam lompatan itu, ia melepaskan panah kedua yang menancap tepat di mata kanan salah satu undead.
Undead itu langsung mencabut panahnya sendiri dan menyerbu ke arahnya. Senjatanya adalah sebatang tombak. Ia menyerang lurus ke depan. Gerakannya bodoh dan terlalu mudah ditebak. Yume menghindar dengan ringan, masuk ke jarak dekat, dan melayangkan tendangan telak ke lutut undead itu hingga hancur.
Ia kembali memasang anak panah. Berputar. Melepaskan. Panah itu menancap di tenggorokan orc yang jaraknya tak sampai lima puluh sentimeter. Meski begitu, orc itu mengaum dan mengayunkan kapak besarnya ke arahnya. Yume menendang bagian ulu hatinya, dan memanfaatkan celah dari serangan itu untuk melepas satu panah lagi, menembus mata orc lainnya. Ia melompat ke samping dan berguling. Saat bangkit dengan satu lutut di tanah, ia menembakkan panahnya dengan posisi busur menyilang. Panah itu pun mengenai sasaran ke dada undead yang memegang dua pedang.
Yume lagi gacor. Serangannya jitu semua, ya.
Itu menunjukkan bahwa penglihatannya masih sangat baik. Rasanya seolah ia punya mata ketiga, atau bahkan keempat. Karena itulah, ia bisa melihat semuanya dengan jelas.
Itsukushima mungkin tadi mencoba membantu Yume. Tapi saat musuh semakin mendekat, ia tidak bisa merapat padanya. Itsukushima dan para anjing serigala tidak terlihat di mana pun di sekitar sini. Mereka cukup jauh. Entah sudah terpisah, atau sedang dalam proses terpisah.
Yume ingin mengejarnya, tapi para orc dan undead mengincar dirinya. Terlalu berbahaya untuk membelakangi mereka hanya demi mencari Itsukushima. Ini salah satu momen di mana ia harus menekan emosinya. Yume yang lama tidak akan sanggup melakukannya. Tapi Yume yang sekarang—dia bisa.
Ia memilih bertahan hidup. Kalau ia tak bisa melewati ini, ia takkan bisa bertemu kembali dengan Itsukushima.
Yume tidak memaksakan diri. Ia hanya fokus pada musuh-musuh yang terus datang silih berganti. Orc dan undead bukan lawan yang mudah, tapi mereka terlalu bersemangat. Bahkan bisa dibilang, kelewat panas. Sementara itu, Yume justru cukup tenang. Kalau ia unggul dalam hal itu, selama selisih kekuatannya tak terlalu besar, ia masih bisa menanganinya.
“…Tapi tetap saja!”
Yume menghindar dari tebasan seorang undead, menjejak dinding bangunan, lalu melepas anak panah. Panah itu menghantam kepala undead yang tidak memakai helm, disertai suara duk yang kencang. Saat masih di udara, Yume melemparkan busur dan tabung panahnya, lalu berguling begitu mendarat. Pedang melengkung milik orc yang hendak membabatnya menghantam batu jalan dan menyalakan percikan api. Anak panahnya telah habis.
Yume berdiri dan mencabut pisaunya. Ia menghela napas panjang. Tubuhnya jauh lebih berkeringat dari yang ia kira.
Sejak tadi, Yume berusaha menjauh dari gerbang utara saat bertarung—meskipun hanya sedikit. Itu harapannya. Tapi posisi sekarang tidak jauh beda dari tempat ia mulai bertarung, bukan? Yah, memang seperti itu kadang kenyataannya. Meski merasa sudah tenang, belum tentu dirinya benar-benar setenang itu.
Yume sama sekali tak peduli pada Aliansi Para Raja ataupun Kerajaan Arabakia. Dia juga tak punya niat khusus untuk melawan orc dan undead. Tapi kalau situasinya sudah seperti ini, dia tak punya pilihan lain.
Masih ada beberapa prajurit relawan yang menahan serangan dari tembok, tapi area sekitar gerbang utara sudah dipenuhi musuh.
Yume sendirian. Tak ada satu pun sekutu di dekatnya. Hanya musuh.
Sekilas pandang saja, ada sekitar sepuluh orc dan undead yang sudah setengah mengepungnya.
Mungkin awalnya mereka meremehkan Yume, menganggapnya cuma manusia lemah yang cuma punya busur kecil. Tapi, yah… justru itu yang paling memudahkan: diremehkan.
Sekarang mereka tak akan memandang Yume sebelah mata lagi. Mereka tahu dia lebih kuat dari yang terlihat. Itulah kenapa lingkaran itu mulai menyempit secara perlahan, hati-hati—dan ketika waktunya tepat, mereka semua akan menyerangnya bersamaan.
Menembus pengepungan ini jelas bukan hal mudah. Yume mengangguk pelan.
“…Oke.”
Memang tidak mudah. Tapi bukan berarti mustahil. Peluangnya mungkin kecil. Tapi bukan nol. Yume memilih untuk percaya pada itu—dan akan berjuang sebaik mungkin.
Yume memindahkan pisaunya ke tangan kiri. Menggenggamnya dengan cengkeraman terbalik, ia tersenyum.
Gaya ini persis seperti Haru-kun, ya?
Ia mengangkat tangan kanannya ke depan, telapak menghadap ke atas, lalu mengisyaratkan mereka untuk mendekat. Meski mereka tak paham bahasanya, siapa pun bisa mengerti makna gerakan itu.
Seekor orc maju, tapi dari sisi kanan Yume, bukan langsung dari depan. Hampir bersamaan, satu undead dari sisi kirinya pun ikut bergerak. Walaupun jumlah mereka sepuluh dan seolah mengepung satu orang, nyatanya bukan benar-benar sepuluh lawan satu. Mereka tak kompak—kalau menyerang serempak, mereka justru akan saling bertabrakan dan bikin kekacauan sendiri. Paling-paling hanya tiga atau empat yang bisa menyerang bersama pada satu waktu.
Yume tidak menyerang orc di kanan atau undead di kiri, melainkan langsung menerjang orc yang berada tepat di depannya. Orc itu menggenggam kapak besar dengan kedua tangan, tapi ragu. Tak peduli seberapa banyak musuh di hadapannya, Yume akan mencari titik terlemah dan mulai menghancurkan dari sana. Dia bertekad menemukan celah untuk bertahan hidup.
“Menyingkirlah!” Begitu mendengar suara itu, entah kenapa perut Yume terasa mengerut sedikit.
Suaranya memakai bahasa manusia. Suaranya, milik manusia. Tapi tetap saja, Yume tidak merasa itu suara dari seorang sekutu.
Para orc dan undead serempak menoleh ke arah gerbang utara. Yume ikut menoleh ke sana.
Ada seorang pria berdiri agak jauh dari lingkaran makhluk-makhluk di sekelilingnya. Tangan kirinya terangkat ke belakang, menggenggam katana yang sisi pipih bilahnya menempel pada punggungnya. Lengan kanannya tak terlihat—karena memang tak ada. Ia hanya punya satu tangan. Dan ia juga kehilangan mata kirinya. Jelas bukan pria muda.
Para orc dan undead mundur, melonggarkan jaring yang mengurung Yume. Jika ia lari sekarang, mungkin saja bisa kabur. Tapi tidak, mustahil. Ia takkan bisa melakukannya.
Pria itu mulai mendekat.
“Aku bisa lihat kamu bakal jadi prajurit relawan yang terkenal suatu hari nanti… Yah, bercanda deh.”
Ia menyeringai, lalu mengarahkan katananya ke Yume.
“Walau tampangku begini, sesekali aku suka juga ngelawan lawan yang tangguh. Tapi ya, kalau kupikir-pikir, tampang kayak gimana sih yang kelihatan suka begituan? Sudahlah. Dengerin, aku nggak akan komentar soal kamu perempuan atau bukan. Jadi, ayo main sebentar sama kakek tua ini, nona kecil.”
Mungkin ini salah satu buah dari latihan bersama Momohina. Meski penampilannya tak meyakinkan, Yume bisa merasakan: pria ini luar biasa kuat. Ia bisa merasakannya—meskipun cara pria itu memegang katananya tampak santai, meski ia hanya berdiri di sana dengan sikap acuh, tak ada satu celah pun terbuka padanya. Santai, tapi sepenuhnya siaga.
Jarak antara mereka masih lebih dari dua meter, namun Yume merasa seolah-olah ujung katana itu sudah menempel di lehernya. Pria itu bisa menebasnya kapan saja. Ia tak bisa kabur. Tubuh Yume terasa menyusut entah sejak kapan.
Takasagi.
Dia manusia, tapi berada di pihak Jumbo sebagai anggota Forgan. Apa itu berarti Forgan adalah musuh? Tidak. Itu tidak penting. Yang harus dia lakukan sekarang adalah fokus. Bahkan jika dia bertarung seolah-olah nyawanya dipertaruhkan, kecil kemungkinan dia bisa mengalahkan pria ini. Dia hanya punya sebilah pisau. Lalu seharusnya dia apa? Tidak ada jawaban yang muncul di kepalanya. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, dia sudah kehabisan pilihan.
“…Oh?” Takasagi memiringkan kepalanya sedikit. “Kita pernah bertemu sebelumnya, nona kecil? Mungkin ini efek usia, tapi ingatanku sudah tidak sebagus dulu. Tapi wajahmu… aku yakin pernah melihatnya di suatu tempat.”
“Memang pernah.”
Yume menyeringai. Mata kanan Takasagi sedikit membelalak, seolah berkata, Tuh, kan. Kuduga begitu.
Saat dia mencoba menjelaskan kapan dan di mana mereka pernah bertemu, Yume sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Bahkan Takasagi tampak sedikit terkejut dengan itu. Tak cukup untuk membuatnya lengah, tapi Yume hanya ingin melakukan apa pun yang bisa dia lakukan.
Takasagi menusukkan katananya ke arah Yume. Yume segera merendahkan tubuhnya, menyelinap di bawah tebasan katana itu, dan mendekat ke arah Takasagi.
Namun Takasagi tidak menarik kembali katananya. Dia juga tidak mundur. Masih ada gagang pedang itu.
Dia mencoba menghantam kepala Yume dengan punggung gagangnya.
Yume tidak menyangka dia akan melakukan itu. Karena itulah, satu-satunya hal yang sempat dia lakukan hanyalah melemparkan tubuhnya ke kanan dan berguling untuk menghindari serangan itu.
“Bagus juga. Lumayan.”
Takasagi mencoba menendang Yume dengan kaki kanannya. Yume tak masalah dengan itu. Ia punya pisau. Kalau ia bisa melukai kaki Takasagi dengan pisau ini, ia akan punya keuntungan.
Tapi ternyata, Takasagi bukan berniat menendangnya menjauh. Bam! Ia malah melangkah masuk dengan penuh tenaga. Inilah dia. Sebuah tebasan dahsyat akan datang.
Yume menjerit tanpa sadar sambil melompat ke samping.
Ia belum terluka. Belum.
Saat ia menoleh, Takasagi sudah mengangkat kembali katananya ke pundak dan memiringkan kepala ke samping.
“Hmm, reaksimu bagus juga. Kamu lulus. Lain kali kutebas yang sungguhan.”
Yume ingin membalas ucapannya, tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar. Ia bahkan tak tahu pasti dalam posisi seperti apa ia berdiri, atau apakah ia masih bernapas dengan benar. Seluruh tubuhnya terasa dingin—sampai ia merasa seperti membeku. Menakutkan. Ketakutan menguasainya, membuat tubuhnya meringkuk. Tapi ia tak boleh seperti ini. Tak boleh.
Ia takkan menang. Bukan melawan lawan seperti ini. Peluang satu banding sejuta pun tak ada. Bertarung secara normal tidak akan berhasil.
Ia harus membulatkan tekad. Harus siap kehilangan satu tangan, atau satu kaki, kalau itu memang harga yang harus dibayar. Tidak, bahkan itu mungkin belum cukup. Hasil terbaik pun mungkin hanya mati bersama-sama dengannya. Apakah ia akan mati sia-sia… atau mati setelah berhasil membunuhnya?
Dalam sekejap, ia telah mengambil keputusan. Ia menyesal karena tak sempat melihat semua orang lagi, tapi ia tak mau terjebak dalam penyesalan itu. Kalau dipikirkan terlalu lama, reaksinya akan melambat. Bahkan di titik ini pun, Yume belum membuang harapan. Meskipun kemungkinan terbaik yang bisa ia capai hanyalah kehancuran bersama, tetap saja ada kemungkinan satu banding sejuta—sebanding semiliar, setriliun—bahwa ia bisa lebih dari itu. Ia tak tahu bagaimana hasilnya sampai saatnya benar-benar tiba.
“Sudah waktunya, Pak Tua Takasagi.”
“…Sudah kuduga. Kau si bocah cewek dari waktu itu, ya?”
“Bukan ‘bocah cewek.’ Nama Yume itu Yume, tahu?”
“Ya, ya. Yume, kan? Ayo sini.”
Takasagi menarik katana ke dada, lalu mengarahkannya ke arahnya. Yume menahan napas. Satu-satunya bayangan masa depan yang bisa ia lihat adalah dirinya tumbang ditebas.
Bagaimana kalau mencuri senjata dari salah satu orc atau undead di sekitarnya dulu? Mungkin Takasagi akan membiarkannya? Tidak, kalau Yume meremehkan pertarungan ini, Takasagi akan kecewa. Ia akan kesal dan frustrasi, lalu menyerah pada Yume. Ia akan menebasnya tanpa ampun.
Saat mereka saling berhadapan seperti ini, ada hal-hal yang bisa dimengerti tanpa perlu diucapkan. Terlepas dari penampilannya, Takasagi sedang kesal. Apa yang membuatnya marah? Kemungkinan besar, pertempuran ini. Takasagi bukan bertarung karena mau. Ia bertarung karena terpaksa. Karena dipaksa untuk ikut dalam perang yang tak sesuai dengan hatinya.
Saat Yume memilih untuk menjatuhkan pisaunya, Takasagi menanggapi dengan senyum tipis.
Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Dalam sekejap, ia akan terbunuh atau nyaris hidup. Tapi rasa takut itu sudah tak ada lagi. Ia harus bisa menghindari tebasan pertama, atau menerimanya dengan cara yang tak mematikan. Jika bisa mendekat, bukan tak mungkin ia punya secercah peluang untuk menang. Dan kalau bukan tak mungkin, itu artinya tetap ada kemungkinan.
Tanpa ragu sedikit pun, Yume melangkah maju. Takasagi mulai menggerakkan katananya.
“Lihatlah jurus rahasiaku.”
Gerakannya melayang—atau mungkin melambai—seperti menari di udara. Apa itu? Entahlah.
“Fall Haze.”
Rasanya seperti ia bisa melihat pedangnya… tapi juga tidak. Ia tak mengerti. Apakah itu cepat, atau justru lambat? Bahkan itu pun tak jelas. Yume terus maju ke arah Takasagi. Ia tak bisa berhenti. Kalau berhenti, ia akan ditembus atau ditebas. Terlalu berbahaya untuk menerjang, tapi tak mungkin mundur.
Pasti karena cara Takasagi mengayunkan pedangnya. Katana itu membuat Yume terhipnotis. Memesona dan mengundang. Jika terus begini, ia akan ditebas bahkan tanpa sempat melakukan apa pun. Tinggal menunggu waktu. Yume akan mati—terdorong rasa takut, tapi juga tergetar oleh keindahan pedang itu.
“Personal Skill!”
Teriakan mendadak itu terasa seperti teguran keras, seolah seseorang baru saja membentaknya, “Jangan mati begitu saja, tolol!” Itu bukan sekadar suara. Itu turun dari langit, seperti bintang jatuh yang menusuk kesadaran.
“Great Foul Waterfall…!”
Bintang jatuh itu menghantam jurus rahasia Takasagi. Bukan, itu bukan sekadar bintang jatuh—bintang jatuh itu memegang katana. Dan katana itu menebas katana milik Takasagi.
“Ugh…!”
Takasagi terpental ke belakang. Hampir saja ia kehilangan cengkeramannya, tapi ia segera menggenggam kembali katana itu dan membalas dengan tebasan mendatar.
“Kurang ajar kau…!”
“Kau mulai keteteran, Pak Tua!”
Bintang jatuh itu—tidak, itu jelas bukan bintang jatuh. Itu seseorang. Manusia, sepertinya. Tapi orang itu berpakaian aneh, mengenakan jubah compang-camping dan topeng aneh yang konyol. Suara laki-laki itu—meski serak sekali—terdengar familiar bagi Yume. Ia mungkin, tidak, hampir pasti tahu siapa pemilik suara itu. Tapi kalau benar, apa yang sebenarnya terjadi di sini?
Takasagi adalah anggota Forgan. Forgan sedang menyerang Altana. Jadi, ya, kalau pria bertopeng itu adalah orang yang Yume pikirkan, tidak aneh dia ada di sini. Dia pasti sudah bergabung dengan Forgan. Meninggalkan Yume dan yang lainnya.
Sejujurnya, Yume tak merasa dia telah mengkhianati mereka. Dia memang bukan orang yang mudah dipercaya, tapi Yume masih mempercayainya. Ia ingin percaya. Memang, kadang-kadang dia bisa terlalu menggila. Tapi dia tetaplah rekan seperjuangannya. Mereka sudah lama bersama. Banyak hal telah mereka lalui. Segala macam hal.
Dia adalah teman yang berharga.
Namun, meski begitu, dia tetap memilih pergi.
Mungkin memang sudah begitulah keadaannya. Mungkin dia memang tak punya pilihan lain. Atau mungkin dia melihat sesuatu dalam Forgan yang tidak bisa Yume lihat. Mungkin dia memang sebegitu membutuhkannya.
Dia selalu tampak tak puas—terus mengeluh tentang ini dan itu. Apa dia benar-benar tak bisa membaca suasana? Atau memang sengaja memilih untuk tidak peduli? Saat suasana sedang bagus, dia akan melontarkan omongan seperti, “Serius, kalian beneran nyaman-nyaman aja kayak gini? Emang kalian pikir semuanya udah beres? Aku sih nggak,” dan mulai menggoyahkan semangat mereka.
Dia sering menjauh dengan kalimat seperti, “Aku di sini bukan buat cari temen. Jangan bego,” tapi tetap saja sikapnya kadang terasa sepi. Yume merasa, dalam caranya sendiri, dia tetap peduli pada teman-temannya.
Apa itu hanya perasaan Yume saja? Apa Yume sudah salah menilainya? Dia ingin tahu. Dia ingin pria itu menjawab langsung.
Apa kamu akhirnya benci sama Yume dan yang lain? Kamu udah nggak peduli lagi, ya?
“Bukan itu masalahnya,” rasanya seolah dia akan menjawab begitu. “Bukan soal suka atau benci. Perasaan-perasaan kayak gitu nggak ngaruh buatku. Tujuanku lebih tinggi dari itu. Jangan samain aku sama orang-orang biasa. Aku nggak benci kalian atau semacamnya.”
Apa yang sebenarnya dia lakukan di sini? Apa itu benar-benar dia?
“Orah, orah, orah, orahhh…!”
Pria bertopeng itu sedang bertarung sengit melawan Takasagi. Gerakannya tampak mencolok, hampir berlebihan, tapi nyatanya justru sangat terlatih dan presisi. Dia mengayunkan katananya dengan bebas dan penuh kreativitas, seolah sedang melukis mahakarya dengan kuas raksasa.
“Sial…!”
Takasagi mulai terdesak. Mungkin itu hanya siasatnya saja, tapi jelas dia berada di posisi bertahan. Yume menyadarinya. Takasagi memang pendekar pedang yang luar biasa, tapi bukan tanpa celah. Bila serangan datang dari arah bawah, tepat di sisi kiri pinggulnya, reaksinya sedikit—meskipun hanya sedikit—lebih lambat dari biasanya. Pria bertopeng itu tidak terus-menerus menyerangnya di titik itu. Dia mencampur berbagai macam serangan lain, hantaman kuat yang bertujuan menahan gerak Takasagi, lalu—sesekali, saat dirasa waktunya tepat—dia kembali mengincar kelemahan tersebut.
Pria bertopeng itu tidak hanya hebat memainkan pedang. Keahliannya saja tak akan cukup untuk membuat Takasagi nyaris tak berkutik seperti ini. Dia benar-benar mengenal Takasagi—dengan sangat baik.
“Oorah!”
Pria bertopeng itu melancarkan serangan rendah ke arah kiri bawah Takasagi. Takasagi mendecakkan lidahnya, namun entah bagaimana berhasil menangkisnya. Tapi saat itu juga, seolah ada saklar yang dinyalakan, pria bertopeng itu langsung mempercepat serangannya.
“Personal Skill! Kilat Dewa Terbang…!”
Nama skill-nya terdengar ngawur, tapi Yume bisa tahu: itu adalah serangan tusukan. Pria itu memegang katana dengan kedua tangan. Sebuah tusukan dua tangan. Terdengar suara angin membelah udara. Bukan sekali. Itu serangkaian tusukan cepat—berulang-ulang. Tapi di mata Yume, semuanya terlihat seperti satu gerakan tunggal.
“Ohhh?! Ohhhh…?!”
Bagaimana Takasagi bisa selamat dari itu? Yume tak tahu. Entah bagaimana caranya, Takasagi mundur sambil menepis katana itu, memutar tubuhnya, dan menghindari seluruh tusukan tersebut. Meski begitu, ia akhirnya terjatuh terduduk dengan keras.
Sekarang, pria bertopeng itu bisa menghabisinya.
Kalau pria bertopeng itu memang orang yang dikenalnya, Yume tahu dia mungkin tidak akan melakukannya.
Dan memang begitu.
Pria bertopeng itu menarik kembali katananya, lalu menyandarkan sisi datar pedang itu di bahunya.
“Berdiri, pak tua.”
Takasagi pun berdiri seperti yang diminta, lalu tertawa terbahak-bahak, penuh tenaga.
“Kau ini muncul di mana-mana, ya. Lidahmu makin tajam juga sekarang, Ranta.”
“Kau…! Jangan panggil nama itu! Aku nutupin wajah bukan tanpa alasan, tahu?!”
“Itu udah jelas, dan kau juga tahu itu.”
“Ti-Tidak, enggak juga!”
Pria bertopeng itu melirik ke arah Yume. Yume ingin memanggil namanya. Berkali-kali, untuk memastikan kalau itu benar-benar dia. Tapi rasanya sekarang bukan saatnya. Kalau mereka berdua saja, mungkin Yume sudah memeluknya. Tapi sayangnya, mereka masih dikelilingi musuh. Namun Yume tidak sendirian lagi. Dia ada di sini. Rekannya. Temannya.
Selama ada Ranta, Yume yakin mereka bisa keluar dari situasi ini.
Karena Ranta itu keras kepala setengah mati.
Dan soal itu, Yume bisa percaya sepenuh hati—tanpa ragu sedikit pun.

Dukung Terjemahan Ini:
Jika kamu suka hasilnya dan ingin mendukung agar bab-bab terbaru keluar lebih cepat, kamu bisa mendukung via Dana (Klik “Dana”)