
1. Bersikap Normal
“Baiklah.” Di halaman rumah penginapan prajurit relawan, Haruhiro kembali menatap koin-koin yang bukan disusun rapi di atas meja, melainkan berserakan di sana. “Haaah…” Ia mengembuskan napas pelan.
Ada koin tembaga. Satu koin tembaga bernilai satu copper.
Ada juga koin perak. Satu koin perak setara dengan seratus copper.
Dan yang itu…
Koin emas.
Tentu saja, terbuat dari emas. Satu koin emas setara dengan sepuluh ribu copper.
Seratus koin tembaga, sembilan puluh sembilan koin perak, dan terakhir dua puluh sembilan koin emas. Jika dijumlahkan, nilainya setara dengan tiga puluh koin emas.
“Aku sudah memikirkannya, dan mendengarkan pendapat kalian semua, tapi… ya. Kita akan membaginya sama rata.”
“Ya iyalah!”
Ranta langsung menyambar lima koin emas.
“Gwehehehehehe! Lima koin emas, dunia kini dalam genggamanku! Inilah saatnya… akhirnya waktuku telah tiba…!”
“Kita semua tahu kamu bakal menghamburkannya buat hal nggak berguna…”
“Huh?! Apa kau bilang sesuatu, Shihoru?!”
“…Nggak juga.”
“Nggak, kau bilang sesuatu! Aku dengar dengan jelas! Kau bilang aku bakal buang-buang duit buat hal bodoh! Aku aja nggak tahu soal itu! Jangan asal menuduh begitu!”
“Kalau begitu, kamu mau pakai buat apa?”
Ketika Merry bertanya dengan nada tajam, Ranta berdeham, membusungkan dada, dan menjawab dengan lantang, “Ehem!” Matanya berkilat penuh semangat.
“Pertanyaan bagus! Aku bakal investasi ke diriku sendiri! Saatnya melakukan inovasi pribadi!”
“Ohh…” Mata Moguzo membelalak. Yume memiringkan kepalanya ke samping.
“Imunisasi pribadi…?”
“Bukan! Itu beda! Dasar bego!”
“Yume nggak mau dibilang bego!”
“Memangnya salah kalau orang bego dipanggil bego, hah?!”
“Orang bego yang suka manggil orang lain bego itu malah bego beneran, dasar bego!”
“Kau barusan manggil aku bego, jadi itu artinya kau juga bego, dasar bego!”
“Murrrrrrrrrrrrrrrrrrrgh…!”
“Hmph!”
Ranta dan Yume sama-sama memalingkan muka dengan kesal di waktu yang bersamaan.
“J-Jadi,” sela Moguzo, sepertinya berusaha menenangkan suasana, “Kamu mau investasi ke apa? Ke skill…?”
“Y-Yep.” Ranta menyilangkan tangan di dada dan menunjukkan ekspresi mengambang—tidak mengiyakan, tapi juga tidak menyangkal. “Y-Ya. Semacam itulah. Tapi, maksudku, ini investasi, tahu? Gimana ya ngomongnya… Aku pakai uang ini buat hal yang bakal berguna di masa depan. Buat tumbuh, jadi lebih dewasa, jadi… ya, laki-laki sejati… gitu deh…”
Shihoru menatap Ranta dengan pandangan jijik yang terang-terangan. Haruhiro langsung menangkap maksudnya. Oh… Jadi tumbuh dewasa. Jadi ‘laki-laki sejati.’ Jadi itu maksudnya.
“Ke ‘itu,’ ya…”
Ketika Haruhiro bergumam pelan, sisi kiri wajah Ranta berkedut.
“A-Apa maksudmu itu? Maksudmu apa, hah?!”
“…Siapa tahu.”
“Bilang aja! Jangan bikin suasana makin canggung begini!”
“Kau sendiri mau pakai uangnya buat apa, Shihoru?”
“A-Aku… aku akan…”
“Woy, jangan pada abaikan aku gitu!”
“Kamu emang suka ribut terus ya, Ranta.”
“Diam! Payudaramu juga kecil terus!”
“Jangan bilang kecil!”
“U-Uhm!”
Kalau Moguzo tidak menyela, mungkin Ranta dan Yume akan terus berdebat seperti itu sampai kapan pun.
“Eh, aku pikir aku mau bawa pedangnya Death Spots ke pandai besi, minta diperbaiki supaya bisa kupakai. J-Jadi… ada yang mau ikut? Kalau tidak keberatan, sih…”
“Aku ikut…” Haruhiro mengangkat tangan. “Aku temani.”
“Kalau begitu, aku juga ikut.”
Itu di luar dugaan. Merry juga menawarkan diri. Dan, tunggu dulu…
Kalau begitu?
Pandangan mereka bertemu. Artinya, Haruhiro sempat melihat ke arah Merry, dan pada saat yang sama, Merry pun ternyata sedang melihat ke arahnya.
Tanpa sengaja, mereka pun saling menatap.
Rasanya agak canggung… atau mungkin memalukan. Haruhiro ingin segera mengalihkan pandangan, tapi itu justru terasa lebih canggung lagi.
Harus gimana, nih…?
Dia jadi panik sendiri. Bingung harus bagaimana. Tapi kalau berlama-lama seperti ini juga aneh. Situasi ini jelas bukan sesuatu yang normal. Dia harus cepat-cepat melakukan sesuatu.
“Y-Yah.” Haruhiro mencoba tersenyum.
Eh, tapi… senyum itu langkah yang tepat nggak, ya? Nanti malah kelihatan aku senang banget. Canggung, nggak sih? Itu bisa disalahpahami… Tapi bukannya aku nggak senang juga, sih. Cuma… boleh nggak ya kelihatan terlalu senang gitu? Tapi kalau sok cool juga malah aneh. Bisa nggak sih bersikap normal aja? Tapi… normal itu yang kayak gimana…?
Haruhiro sendiri nggak yakin, tapi tetap berusaha sekuat tenaga untuk terlihat biasa saja saat berkata, “Ayo bareng, ya…”
“Iya.”
Merry mungkin memang bersikap biasa saja. Tapi… mungkin di raut wajahnya ada sedikit ekspresi Kenapa nih orang?
Jujur, aku sendiri juga nggak tahu…
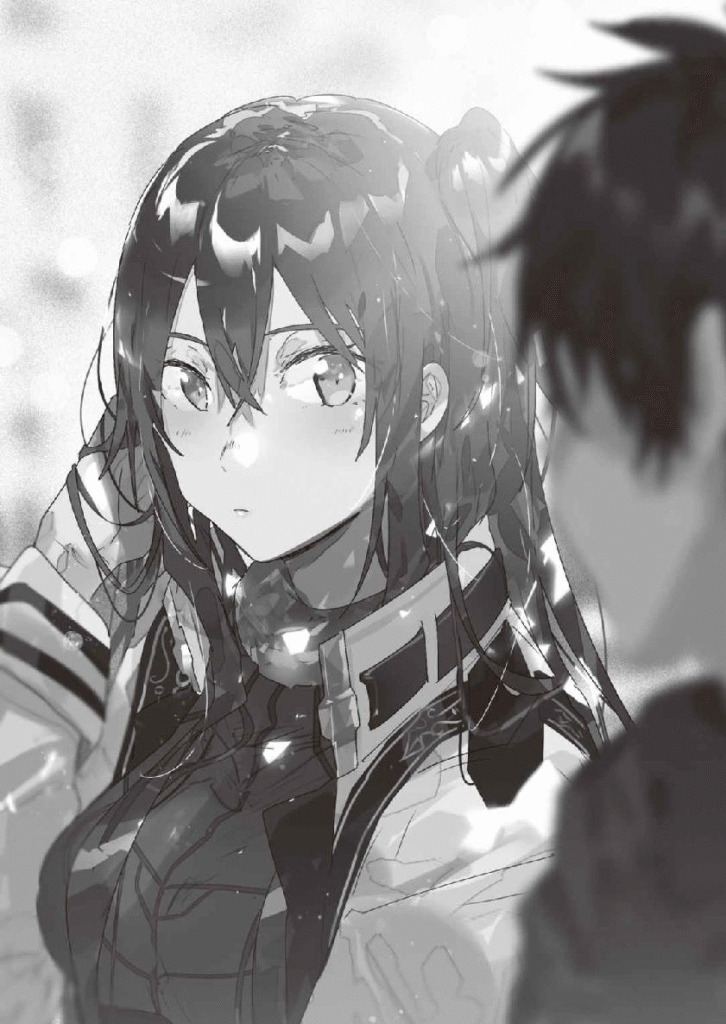
2. Trigon Mimpi
“Haruhiro-kun. Merry-san. Terima kasih, ya, kalian berdua.”
Sambil berjalan di kota para pengrajin dengan membawa pedang milik Death Spots yang terkenal kejam itu, Moguzo tampak benar-benar bahagia. Jarang sekali melihatnya seceria ini.
“Ah, nggak, bukan hal besar kok…” Haruhiro menjawab setengah nggak jelas, lalu tertawa kecil.
“Jangan dipikirin.”
Jawaban Merry singkat dan datar, tapi entah apa yang ia pikirkan saat mengucapkannya. Apa yang ia rasakan? Tak ada yang aneh sebenarnya. Merry bersikap normal. Tapi… “normal” itu berbeda jauh dibanding Merry yang dulu. Ia mulai terbiasa dengan party mereka. Meskipun begitu, tetap ada jarak—bisa dibilang begitu. Misalnya, terasa ada sedikit jarak lebih antara dirinya dengan dua rekan sesama perempuan, Yume dan Shihoru. Tapi perlahan, sedikit demi sedikit, ia sedang berusaha memperkecil jarak itu.
Mungkin karena itulah ia ikut hari ini. Hanya itu. Tidak ada maksud lain di baliknya.
“…Ya. Pasti begitu. Cuma itu.”
“Haru? Barusan kamu ngomong sesuatu?”
“Huh? A-Aku? A-Apa aku ngomong sesuatu…?”
“Aku yang nanya, lho.”
“K-Kamu ya?! Iya. Iya, bener. Umm, nggak kok… A-Aku cuma ngomong sendiri, bisa dibilang. Nggak ada maksud apa-apa. Kadang suka gumam aja gitu…”
“Ohhh.” Merry menampakkan sedikit senyum—hampir tak terlihat—lalu menghela napas pelan. “Sepertinya emang kita suka kayak gitu, ya. Aku juga kadang suka ngomong sendiri.”
“Iya, kan?! Iya, emang begitu. Tapi kenapa, ya? Jadi penasaran juga…”
“A—” Merry sempat ingin bicara, lalu, “Tidak, lupakan saja.” Ia menggelengkan kepala.
“Huh? A-Apa? Bilang aja.”
“Itu cuma…”
“Cuma apa?”
“Aku sering sendirian. Jadi kupikir mungkin karena itu.”
Ugh… Haruhiro merasa ada yang menegang di dadanya.
Jujur saja, rasanya dia ingin berteriak.
Merryyyyyyy…! Tungguuu…! Merryyyyy…?! Jangan bilang begitu…!
Ya, memang Haruhiro sendiri yang bilang, “Bilang aja,” dan membuat Merry mengungkapkan sesuatu yang menyedihkan—bahwa dia sering berbicara sendiri karena terbiasa sendirian. Tapi tetap saja!
Aku nggak bermaksud bikin kamu ngomong kayak gitu… sungguh.
Tapi—sebagai pemimpin party? Mungkin…? Ya. Murni sebagai pemimpin party. Dalam peranku sebagai pemimpin, sudah semestinya aku memperhatikan hal-hal seperti itu. Memperhatikan dan mengamati, kan? Meski itu urusan pribadi dan pribadi banget, tapi kita ini kan rekan seperjuangan? Ya, rekan! Bahkan kalaupun bukan pemimpin, wajar kok khawatir sebagai sesama manusia, kan? Kan?
“Ahh, ehm… K-Kalau lagi kayak gitu…”
“Lagi kayak gitu?” Merry bertanya sambil mengedip, menatapnya dengan ekspresi kosong. Ekspresi itu… maksudnya apa, ya? Merry itu, entahlah… kadang terasa agak dingin. Saat mereka pertama kali bertemu, dia sempat bersikap agak ketus, kan? Memang belakangan ini sudah nggak begitu, tapi dia bukan tipe yang mudah menunjukkan emosi. Dari yang pernah Hayashi ceritakan, katanya dulu Merry adalah orang yang sangat ceria. Tapi kejadian itu… mungkin sampai sekarang masih membayangi dirinya.
Rasa kehilangan itu pasti telah mengubah Merry. Ia terpaksa berubah.
Tidak perlu memaksanya untuk kembali seperti dulu. Tapi suatu hari nanti, Haruhiro berharap Merry bisa tersenyum—tulus—dari lubuk hatinya yang paling dalam.
Itulah, kurang lebih, alasan kenapa ekspresi kosong tadi begitu mengejutkan Haruhiro. Rasanya seperti pertama kali ia melihat sisi itu dari Merry.
Tampak polos. Tanpa noda. Murni… Harus dia sebut apa, ya?
Satu kata yang terlintas: imut?
Imut, ya?
Kayaknya bukan kata yang tepat, tapi juga nggak sepenuhnya salah. Atau malah… terlalu tepat? Tepat sasaran? Seperti pukulan telak di pertandingan bisbol?
“…K-Kalau lagi kayak gitu… U-uh, ya, kalau lagi kayak gitu… Kayak gitu? Huh…?”
Tadi dia ngomongin apa, sih?
Maksudnya kalau lagi kayak gitu tuh yang kayak gimana? Dia barusan ngomong apa, sih? Lupa. Nggak ingat sama sekali. Terus gimana sekarang? Tanya ke Merry? Tapi dia sendiri yang mulai topik ini—aneh dong kalau malah nanya balik. Terus, mikir aja? Ya, dia udah mikir. Udah berusaha mengingat. Tapi tetap buntu.
“E-Eh, pernah ngalamin juga, kan? Maksudku, ya, kadang emang ada saat-saat kayak gitu!”
Mau nggak mau, Haruhiro harus terus maju. Ia berkata dengan nada meyakinkan.
Merry mengernyit sedikit, tampak agak ragu, tapi pada akhirnya, “Ya,” jawabnya singkat.
Itu pasti karena kebaikan hati. Merry sedang mempertimbangkannya. Ia menunjukkan sedikit kebaikan padanya.
Tapi aku yang seharusnya begitu!
Akulah yang harus bersikap baik! Sebagai pemimpin! Sebagai rekannya! Aku tahu Merry sedang menghadapi banyak hal… Lalu kenapa malah aku yang dibantu? Kenapa dia yang berbaik hati ke aku? Gagal total aku sebagai pemimpin. Nggak, bahkan bisa dibilang gagal sebagai manusia. Oke, mungkin itu agak berlebihan. Aku lebay. Tapi, yah, yang penting aku berhasil keluar dari situasi tadi. Jadi ya sudahlah.
“Oh! Itu, di sana.”
Moguzo tiba-tiba berhenti, lalu menunjuk ke sebuah jalan sempit di sebelah kiri mereka. Saat Haruhiro menoleh, ia melihat ujung jalan pendek itu membentuk percabangan seperti huruf T, dan ada sebuah bangunan batu tanpa cat di sana. Di depannya tergantung sebuah papan nama.
Workshop Masukaze, begitu tertulis di papan itu.
“Letaknya agak terpencil, ya?”
“Y-Yah.” Suara Moguzo terdengar agak tegang. Wajahnya juga sedikit kaku. “Kudengar bengkel ini dikelola oleh pandai besi yang sangat berbakat. Tapi orangnya aneh. Maksudku, katanya dia cuma mau ngerjain pesanan yang nggak biasa… semacam itu, deh…”
Haruhiro melirik ke pedang Death Spots yang dibawa Moguzo di atas pundaknya.
“Oh, ya? Yah, mungkin yang kau bawa itu termasuk pesanan ‘nggak biasa’, ya?”
“Mungkin aja. Aku juga kepikiran begitu.”
“Kenapa nggak langsung kita lihat saja?”
Atas dorongan Merry, mereka bertiga berjalan menyusuri jalan sempit itu.
Pintu bengkel Workshop Masukaze terbuat dari baja. Seluruh permukaannya dipenuhi ukiran berpola rumit, dihiasi logam kehitaman yang ditanamkan ke dalamnya. Karya yang sangat detail—bahkan orang awam pun bisa melihat itu. Kalau diperhatikan lebih dekat, papan nama Workshop Masukaze juga terbuat dari besi, dan dihiasi dengan teknik yang serupa.
Begitu mereka membuka pintu dan melongok ke dalam—
“Wah!” Kepala Moguzo langsung terangkat ke belakang karena terkejut. Dan bukan cuma dia. Haruhiro dan Merry juga bereaksi sama.
Di dalam ruangan, dinding dan rak-rak dipenuhi senjata. Itu masih wajar.
Masalahnya bukan senjatanya.
Masalahnya adalah benda besar yang berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dengan tatapan tajam—seekor kuda… logam? Itu… kuda?
Tidak. Itu jelas bukan kuda.
Kalau itu memang seekor kuda, tentu ia akan punya dua kaki depan dan dua kaki belakang. Tapi benda ini tidak. Sebagai ganti kaki, ia memiliki roda. Dua di depan, satu di belakang. Total tiga buah.
Kalau harus diberi nama, mungkin… kuda beroda?
Ekspresi wajahnya, atau lebih tepatnya bentuk kepala yang menempel di lehernya, memang agak mirip kuda—tapi tidak sepenuhnya. “Lalu itu sebenarnya apa?”—mungkin begitu pertanyaannya. Tapi Haruhiro tidak punya jawabannya. Mungkin wajah naga, yang katanya hanya muncul dalam desas-desus, memang seperti ini. Jadi… seekor naga-kuda beroda, mungkin?
“Oh! Selamat datang!”
Seorang pria muncul dari belakang ruangan. Sepertinya di sanalah letak bengkel pandai besinya.
Pria itu berambut panjang dan mengenakan celemek khas perajin. Tubuhnya tidak besar, tapi kekar dan kelihatan ringan gerakannya. Sulit menebak usianya. Jelas lebih tua dari Haruhiro, tapi dia memberi kesan seperti—sepuluh tahun yang lalu dia pasti terlihat sama, dan sepuluh tahun ke depan pun kemungkinan takkan berubah. Begitulah aura tenangnya.
Dilihat dari cara dia tersenyum sambil mengangkat satu tangan dan melangkah ringan ke arah mereka, tampaknya dia cukup pandai bergaul dengan orang. Tapi meski pria itu menatap mereka, tatapan matanya terasa tidak benar-benar fokus—seolah menatap sesuatu di tempat lain.
“Halo, namaku Riyosuke. Aku seorang pandai besi.” katanya sambil menepuk badan naga-kuda beroda itu. “Ada keperluan apa datang ke workshop ini?”
“B-Baik!”
Moguzo segera menurunkan pedang dari pundaknya.
Namun sebelum ia sempat benar-benar melakukannya, mata si pandai besi, Riyosuke, sudah memancarkan kilau aneh—itu tidak wajar.
Dia sedang melihatnya. Dia benar-benar sedang melihatnya. Riyosuke jelas-jelas sedang memperhatikan pedang Death Spots itu.
Kalau ada orang yang menatap Haruhiro dengan pandangan seperti itu, mungkin dia takkan bertahan sepuluh detik. Bahkan lima detik pun tidak.
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Riyosuke melesat ke arah Moguzo dan merebut pedang Death Spots dari tangannya. Ia menggenggam pedang raksasa itu dengan kedua tangan, dan bukannya sekadar menatapnya—ia seperti sedang menjilatnya dengan tatapan penuh nafsu.
Moguzo mundur perlahan, sementara Haruhiro berdiri sejajar dengan Merry—bukan karena dia sengaja, ya? Merry yang lebih dulu mendekat ke arahnya; Haruhiro sendiri tidak bergerak ke mana-mana, oke? Sepertinya Merry pun tidak bermaksud mendekat ke Haruhiro, jadi ya kebetulan saja mereka berdiri berdampingan. Hanya itu, tidak lebih.
Tapi yang lebih penting sekarang, Riyosuke sedang mengamati pedang Death Spots itu. Dari segala sudut. Sambil mengubah jarak pandangnya, membalik-balikkan pedangnya, memiringkannya, benar-benar memeriksanya dengan cermat, seolah terobsesi.
Sampai kapan dia mau melihat pedang itu? Selamanya? Untuk selama-lamanya…?
Setelah menatapnya cukup lama hingga membuat Haruhiro berpikir seperti itu, Riyosuke berbisik pelan, “Menarik…”
“Menarik, benar-benar menarik. Ini berbeda. Dalam idealnya. Dalam sejarahnya. Ini benda yang sangat tua. Hmm… Begitu rupanya. Ini bagian sini begini… Hmm. Oke. Oke. Jadi itu maksudnya… Ah. Hmm. Jadi itu yang mereka lakukan? Ya, ternyata memang begitu. Tidak menyangka mereka akan melakukannya seperti itu. Tapi kalau mereka tidak lakukan itu, maka apa yang terjadi…? Oh… Aku mengerti.”
Riyosuke menoleh pada Moguzo.
“Boleh aku ambil ini?”
“A-Apa…?” Moguzo sampai tak bisa berkata-kata. Wajar saja. Buat apa dia membawa benda itu sejauh ini kalau hanya untuk memberikannya begitu saja?
“Tidak!” Haruhiro buru-buru menyela. “K-Kau nggak boleh mengambilnya! Nggak boleh, oke?! Itu gila! Umm, tapi bukan itu masalahnya—kami ingin kau memperbaikinya, supaya bisa dipakai lagi.”
“Aku bercanda,” kata Riyosuke sambil tersenyum. Namun kemudian, dia menunduk dan mendecakkan lidahnya.
“…Kau barusan mendecakkan lidahmu,” Merry menunjukkannya dengan lembut.
Riyosuke kembali tersenyum. “Itu juga bercanda.”
“Benarkah…?” Haruhiro tanpa sadar mengucapkan isi pikirannya.
“Ya ampun, tentu saja bercanda,” kata Riyosuke, melirik ke arah naga-kuda beroda itu entah kenapa. “Ngomong-ngomong, bagaimana menurut kalian tentang karya ini? Cukup luar biasa, kan?”
Moguzo tampak kewalahan, tapi tetap mengangguk dan berkata, “I-Iya… K-Keren… iya. A-Apakah ini juga buatanmu, Riyosuke-san?”
“Ya. Benar. Aku yang membuatnya. Keren, ya? Begitu… Terima kasih. Aku tersanjung.”
“Itu apa, sebenarnya?”
Saat Merry bertanya, Riyosuke menjawab, “Mari kita balik pertanyaannya. Menurutmu, itu apa?”
“…Seekor kuda?” tebak Merry.
“Ya. Salah satu motifnya memang kuda.”
“Kepalanya… naga, mungkin?” sambung Haruhiro.
“Betul,” Riyosuke mengangguk. “Gambaran di kepalaku memang seekor naga. Aku pernah bertemu satu, dulu, saat masih jadi prajurit relawan. Hanya satu, sih.”
“Oh, jadi dulu kau prajurit relawan?”
“Aku sudah ganti profesi. Sudah lama sekali, juga.”
“Seekor kuda dan… naga?” Haruhiro menatap roda-roda itu. “Kenapa kakinya berupa roda?”
“Ah, itu.” Ekspresi di wajah Riyosuke mendadak lenyap. “Aku melihatnya dalam mimpi. Kurasa mereka berasal dari semacam kendaraan. ‘Trigon’ ini dibuat dengan motif kuda, naga, dan kendaraan itu.”
“Trigon…”
Moguzo menatap Trigon dengan ekspresi serius, lalu menghela napas.
Sementara itu, Haruhiro tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, Terus…? Apa sebenarnya benda ini? Tidak terlihat seperti senjata. Apa ini kendaraan? Mungkin bisa dinaiki di punggung kudanya, tapi terlalu berat untuk ditarik seperti kereta. Atau cuma karya seni yang diam di tempat?
“Yah, ini memang benda mimpi yang berasal dari mimpiku,” kata Riyosuke sambil tersenyum ramah. “Maaf kalau aku bicara soal hal aneh. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Tapi, menyenangkan bisa mengobrol. Aku masih ada pekerjaan, jadi kita cukupkan sampai di sini.”
“Ah, terima kasih…” Moguzo membungkuk sopan, tapi—Tidak, tidak, tidak.
“T-Tunggu dulu!” Haruhiro memanggil Riyosuke.
“Pedangnya! Kenapa kamu diam-diam mau kabur bawa pedang milik Death Spots?!”
“Kau memergokiku, ya?” Riyosuke yang sedang berjalan ke bagian belakang dengan pedang masih dalam pelukannya, menoleh. Tentu saja, dia tetap tersenyum. “Itu cuma bercanda, kok.”
“Kamu jelas-jelas serius…”
“Hanya cukup serius untuk berpikir, ‘Siapa tahu aku beruntung.’ Ha ha ha.”
“Apakah ini tidak apa-apa?” Merry mengerutkan kening, menurunkan suaranya—meskipun tidak cukup pelan hingga Riyosuke tak bisa mendengarnya—dan bertanya pada Moguzo dan Haruhiro, “Kalian yakin mau minta tolong pada orang seperti ini?”
“Um, eh…” Moguzo bergumam, jelas terlihat ragu. Haruhiro pun tak tahu apakah mereka bisa mempercayai pandai besi itu atau tidak.
“Serahkan saja padaku, sungguh.”
Faktanya bahwa satu-satunya yang tampak yakin hanyalah Riyosuke sendiri justru membuat semuanya terasa semakin mencurigakan.
“Aku yakin kalian akan puas dengan hasilnya. Ah, ya. Biar aku ukur dulu, nanti akan kubuatkan perkiraan biayanya. Kalau kalian cocok dengan harganya, aku tidak keberatan dibayar setelah pekerjaan selesai. Jadi, tolong serahkan padaku selama empat hari. Ya, itu cukup. Kalian datang ke tempat yang tepat.”
3. The Boston Crab
Pandai besi Riyosuke dari Workshop Masukaze memang sedikit memaksa, dan harga 40 koin perak untuk memperbaiki pedang besar itu sebenarnya tidak terlalu mahal, jadi Moguzo pun menyerahkannya pada pria itu. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa menolak. Bisa dibilang, “Dia dipaksa menyetujuinya” adalah cara yang paling akurat untuk menggambarkannya.
Selagi menunggu senjata Moguzo selesai diperbaiki, mereka semua memutuskan untuk memanfaatkan waktu dengan mempelajari skill-skill baru.
Moguzo memilih teknik bertarung heavy-armor bernama Steel Guard. Teknik ini memanfaatkan bobot zirahnya untuk menangkis serangan musuh. Mempelajari cara menggunakan baju zirah secara efektif, bahkan saat senjata barunya masih dalam pengerjaan, benar-benar mencerminkan gaya Moguzo.
Ranta mempelajari Dread Aura, sejenis sihir kegelapan yang konon memperkuat dread knight dengan kekuatan Skullhell, atau semacamnya. Skill terakhirnya, Dread Teller, bisa dibilang gagal total—atau setidaknya, Ranta belum bisa menggunakannya secara efektif dalam pertarungan. Tapi menurut penjelasannya, Dread Aura hanyalah sihir penguat sederhana, jadi seharusnya tidak akan merepotkan.
Sementara itu, Yume kabarnya memilih untuk mempelajari jurus Weasel Somersault. Secara teknis, itu dikategorikan sebagai teknik parang, tetapi sebenarnya jurus ini digunakan untuk menghindari serangan musuh dengan salto cepat, atau untuk menciptakan jarak. Walau Yume adalah seorang hunter, ia lebih sering bertarung dalam jarak dekat daripada menggunakan busurnya. Jurus itu pasti akan berguna baginya.
Shihoru sedang mempelajari mantra pengalih perhatian bernama Shadow Complex. Itu adalah sihir Darsh yang berfungsi untuk membingungkan target. Bukan untuk memberikan kerusakan, melainkan untuk mengganggu.
Merry bilang ia berniat mempelajari Protection. Efeknya adalah meningkatkan performa hingga enam orang sekaligus dengan menggunakan berkah dari Lumiaris. Kenapa enam? Karena simbol Lumiaris adalah sebuah bintang segi enam—sebuah hexagram—dan angka itu dianggap suci. Mungkin itu ada hubungannya. Bahkan, ada teori yang menyebutkan kalau mantra ini adalah alasan kenapa kelompok prajurit relawan hanya terdiri dari enam anggota. Mantra itu sudah pasti akan memperkuat tim. Aku ingin memberdayakan rekan-rekanku. Mungkin itu yang ada di benak Merry.
Sementara itu, soal Haruhiro…
“Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh…?!”
“Kamu ceroboh, Kucing Tua.”
“Nggak, tapi sakit banget!”
“Ya jelas. Tentu saja sakit. Aku sedang memutar pergelangan dan sikumu dengan kekuatan penuh.”
“Aaagh, sakit! T-Tunggu—Barbara-sensei! A-Anda… Anda mematahkannya…!”
“Tidak, tidak. Untuk mematahkannya, aku harus begini—nah!”
“Gwah…!”
Barusan… barusan itu bersuara, kan? Pop. Iya, kan? Tulang di siku kanannya…
“AGHHHHHHHHHHHH?! SA-KIIIIIT…?!”
“Cuma bercanda. Bohong kok. Nggak patah, tenang aja. Cuma terkilir. Tinggal kukembalikan ke tempatnya, dan kamu akan sembuh. Gini caranya.”
“Uwah…!”
“Tuh, kan?”
Dengan masih mengunci pergelangan dan siku kanan Haruhiro, Barbara mendekatkan wajahnya sampai pipi mereka nyaris bersentuhan.
“Udah nggak sakit lagi, kan?”
“…S-Sakit kok…? Masih lumayan parah, malah…”
“Kamu benar-benar penakut. Kali ini, aku akan benar-benar mematahkannya. Nih!”
“Agyagh?!”
Kali ini, dia benar-benar mengira tulangnya patah. Tapi entah kenapa, dia melepaskannya begitu saja.
Barbara-sensei berdiri tak jauh dari situ, terkekeh pelan.
Begitu Haruhiro lengah, dia langsung bergerak mendekat. Haruhiro mencoba menghindar. Serius. Bahkan dengan putus asa. Tapi sama sekali tidak berhasil. Dalam sekejap, Barbara-sensei sudah menangkap lengan kanannya, lalu membengkokkan pergelangan dan sikunya hingga ke batas maksimal.
“Ini namanya Arrest. Berapa kali aku harus menunjukkan ini sampai kamu bisa menghafalnya, hmm, Kucing Tua? Kamu belum setua itu sampai harus pikun, kan?”
“…T-Tolong lebih pelan sedikit…”
“Pelan? Apa itu? Kamu mau aku mencabut nyawamu secara perlahan?”
“T-Tidak, bukan begitu maksudku. Aku ingin Sensei mendemonstrasikannya lebih pelan…”
“Oh. Begitu. Ya, masuk akal juga sih.”
Barbara-sensei langsung melepaskannya.
“Huh…?”
Mencurigakan. Terlalu mencurigakan. Mengingat Barbara-sensei, dia pasti akan melancarkan trik lain. Sudah pasti.
Dengan waspada, Haruhiro menatapnya saat Barbara-sensei perlahan meraih lengan kanannya.
“Pertama, begini.”
“Uh… Baik.”
“Kemudian, begini—”
Tidak. Lebih tepatnya, bukan hanya sekadar meraih lengannya.
Barbara-sensei mendekat ke Haruhiro, dan karena gaun tipis yang dikenakannya—yang hanya menutupi sedikit dari kulitnya—kulit telanjangnya pun menempel langsung pada tubuh Haruhiro.
Ini…
“Hm?”
Barbara-sensei memiringkan kepalanya.
“Ada apa, Kucing Tua? Ada bagian yang kamu nggak ngerti?”
“…Nggak. T-Tidak ada bagian yang nggak aku mengerti, sih…”
“Tuh, cocok, kan?”
Barbara-sensei mendorong Haruhiro menjauh, lalu menyodorkan lengan kanannya dengan santai, tanpa sedikit pun rasa khawatir.
“Kalau begitu, kamu coba.”
“A-Aku yang harus coba…?”
“Ya, tentu saja. Pelatihan ini buat ngajarin kamu cara melakukannya, kan?”
“…Benar juga.”
Haruhiro menunduk, menelan ludah. Dalam situasi seperti ini, kalau dia bilang “nggak bisa,” siapa yang tahu apa yang bakal dilakukan Barbara-sensei padanya? Melihat siapa dia, Haruhiro tahu dia nggak akan lolos dengan mudah. Bisa-bisa dia dipaksa melayang-layang di ambang kematian—dan itu bukan hiperbola.
Secara alami, kalau dia mencoba dan gagal, dia bakal dihukum.
Kalau dia nggak mencoba, dia bakal setengah mati.
Neraka di depan. Neraka juga di belakang.
Harimau di gerbang depan, serigala di pintu belakang.
Huh? Bukankah dia bakal hancur bagaimanapun juga…?
Nggak, tunggu, kalau dipikir-pikir mana yang lebih parah… jawabannya jelas. “A-Aku coba.”
Begitu Haruhiro menyatakan keputusan menyedihkannya, Barbara-sensei tersenyum dan menggoyang-goyangkan lengannya pelan.
Dia lumayan menggoda juga, ya… pikir Haruhiro tanpa sadar. Ia buru-buru menahan senyum dan menjaga ekspresinya tetap serius. Meski begitu, kemungkinan besar Barbara-sensei bisa melihat semuanya. Dia jeli menangkap setiap kilatan pikiran, setiap getaran emosi sekecil apa pun.
“Baiklah, serang aku.”
Isyarat tangannya, nada suaranya—keduanya lebih genit dari yang diperlukan. Bahkan lebih dari biasanya. Seolah dia sedang mengundangnya melakukan hal lain sepenuhnya. Hal lain yang mana? Yah, lupakan dulu soal itu. Ini tetap bagian dari pelatihan.
Tenang. Harus tetap tenang.
Ia harus menahan diri dari upaya Barbara-sensei yang mencoba menggoyahkan mentalnya. Melatih keteguhan jiwa dan tetap tenang. Kalau tidak, ia tak akan bisa menggunakan teknik yang sedang dipelajarinya dalam pertempuran yang sesungguhnya.
“…Aku mulai.”
Haruhiro meraih lengan kanan Barbara-sensei dengan kedua tangannya.
Rasanya agak…
Terlihat berotot—atau setidaknya tampak begitu—tapi ternyata cukup lembut.
Lalu kenapa?
Duh. Haruhiro menggeleng cepat. Ia melakukan persis seperti yang diharapkan Barbara-sensei. Atau mungkin tidak, tapi kalau ia lengah hanya karena kelembutan tubuh wanita, bukan hanya akan diejek dengan, “Oh, kucing tua, mulai genit, ya?”—ia bakal disakiti. Dan itu tidak bagus.
Barbara-sensei sudah memakai Arrest padanya lebih dari sepuluh kali sejauh ini. Ia tahu caranya—meski samar. Setidaknya, tubuhnya tahu seperti apa rasanya jadi korban teknik itu.
Aku bisa. Harusnya bisa. Ayo lakukan. Harus kulakukan.
“D-Dapat…!”
Aku pegang tangan Barbara-sensei seperti ini, lalu tekuk sikunya sejauh mungkin, dan—
“Ahn!”
Tiba-tiba saja Barbara-sensei mendesah, membuat jantung Haruhiro berdetak kencang dan fokusnya langsung buyar. Ia tak bisa melanjutkan teknik Arrest-nya.
“Kau! Bodoh…!”
Tentu saja, Barbara-sensei tidak akan membiarkan itu begitu saja.
“Uwah?! Eh…?!”
Tapi… apa yang barusan dia lakukan padanya?
Mungkin dia diputar, lalu dijatuhkan. Ia kehilangan keseimbangan, dan sedetik kemudian tubuhnya membentur tanah dengan keras. Posisinya terbalik. Ada beban menekan punggungnya. Pasti itu bokong Barbara-sensei. Ia menarik kedua kakinya.
“W-Wah! Ah! Barbara-sensei! Aw! Sakit! Ini sakit…!”
“Ya jelas sakit! Itu karena aku sengaja menyakitimu, Kucing Tua! Kau lengah, jadi ini hukumannya!”
Ini teknik itu. Barbara-sensei duduk di punggung Haruhiro, masing-masing kakinya dijepit di bawah ketiaknya.
Apa namanya, ya? Oh, iya.
Boston Crab.
Begitulah namanya. Haruhiro tak tahu itu teknik macam apa, tapi jelas ini bukan teknik main-main.
“Aaaaarghhh! Barbara-sensei! Ini bukan Arrest! Pinggangku! Punggungku rasanya mau patah…! A-Ampuuuun…!”
“Kalau mau aku berhenti, ya teruslah merengek~…!”
“Uwaahahahahhahah…!”
“Lagi! Teruskan~…!”
“Giiiiaaagghhhahahhahahhahahhahhahhh…!”
4. Alasan Kesepian
Itu benar-benar kacau. Tapi yah, Barbara-sensei memang selalu seperti itu. Hanya saja kali ini terasa lebih parah dari biasanya. Tapi… apakah dia seperti itu ke semua muridnya? Atau jangan-jangan, dia memang benar-benar membenci Haruhiro?
“…Tapi dia kelihatan menikmati saat menyiksa aku. Mungkin dia memang suka seperti itu…”
Bagaimanapun juga, berkat Barbara-sensei, Haruhiro akhirnya berhasil mempelajari Arrest. Sistem pelatihan skill dilakukan seperti kamp pelatihan, jadi selama itu dia tidak bisa bertemu dengan rekan-rekannya. Padahal baru beberapa hari saja, tapi entah kenapa ia merasa rindu.
Oh, iya. Dia juga harus mengambil senjatanya Moguzo di Workshop Masukaze. Tapi… bisa jadi Moguzo sudah mengambilnya sendiri?
Sambil memikirkan itu semua, Haruhiro kembali ke rumah penginapan. Dan di sana, kekacauan sudah menantinya.
“Aku menolak! Menolak, tahu?! Aku benar-benar menentangnya!”
Di halaman, Ranta dan Moguzo, serta Yume dan Shihoru, terbagi menjadi dua kelompok yang sedang adu mulut—atau lebih tepatnya, hanya Ranta yang berteriak-teriak.
“Apa kalian semua lupa?! Hari-hari yang kita lewati bersama di rumah penginapan untuk prajurit relawan ini?! Kalian kejam! Aku nggak nyangka kalian sekejam ini! Aku nggak percaya! Sungguh, sungguh, sungguh…!”
“H-Hey, ada apa? Apa yang terjadi?”
Saat Haruhiro berlari mendekat, Ranta menunjuk Yume dan Shihoru dengan marah.
“Mereka! Mereka mulai ngomong seenaknya soal pindah dari rumah penginapan ini!”
“Eh, maksudku…” Moguzo mencoba menyela.
“Diam kau!” Ranta membentaknya. “Ini salah! Meninggalkan rumah penginapan ini! Nggak masuk akal, kan?! Iya, kan?! Kau setuju, kan, Haruhiro?! Kan?! Tentu saja setuju! Aku tahu itu! Tuh, Haruhiro sependapat denganku, jadi lupakan saja ide gila ini! Sudahi saja! Selesai! Tamat!”
“…Eh, nggak, aku nggak bilang aku setuju.”
“Apa kaaaatamu?! Kau mau mengkhianatiku, Parupiro?!”
“Aku nggak mengkhianatimu… Maksudku, cepat atau lambat kita pasti akan keluar dari penginapan ini juga, jadi nggak aneh kalau itu terjadi sekarang.”
“Itu dia, ‘kan?” Yume menyilangkan tangan dan menggembungkan pipinya. Ia kesal. “Yume sih udah mulai terbiasa, tapi penginapannya tua, terus juga nggak bersih-bersih amat, tahu? Dari dulu Yume pengin pindah begitu punya cukup duit. Dan sekarang udah bisa.”
“…Makanya,” Shihoru mengangkat tangan. “Merry… Dia tinggal di penginapan khusus perempuan, jadi… kami cuma tanya-tanya soal itu. Itu aja, tapi…”
“Berarti kalian memang mau pindah!”
Ranta kenapa sih sampai sepanik itu? Haruhiro nggak ngerti.
“Memangnya kenapa kalau pindah? Tempatnya pasti lebih bagus dari sini. Iya, kan?”
“Gah…! Itu dia! Dengar, tuh! Lebih bagus, ya?! Hei, Haruhiro, kau pikir kau terlalu hebat buat tinggal di sini, ya?!”
“A-Aku nggak bilang begitu. Sama sekali nggak…”
“Kau ngerasa paling hebat, ya?!”
“Oh, sudahlah! Kau nyebelin!”
“Itu karena kau pikir kau hebat banget, ya?!”
“Sialan—”
Haruhiro mulai naik darah.
Wah, nggak beres nih. Ranta. Orang ini emang punya bakat bikin orang kesel. Tapi aku nggak bakal terpancing. Aku nggak akan marah beneran karena dia.
Haruhiro menghela napas, lalu mencoba rileks. Setelah itu, ia menatap Ranta.
Ya, bahkan cuma lihat mukanya aja bikin aku pengin ngebanting sesuatu. Wajahnya, rambutnya, semuanya. Nggak, nggak. Harus tetap tenang.
“Ada apa sih sama kamu, Ranta? Hentikan omong kosongnya, dan kalau kamu punya alasan kenapa Yume dan Shihoru nggak boleh pindah, jelaskan dengan benar.”
“A-Aku udah jelasin, kan, sialan!”
“Kalau gitu, jelasin dengan cara yang bisa kupahami.”
“U-Udah kubilang juga tadi!” Ranta memalingkan wajah dan menendang tanah. “…Ada alasannya! Banyak! Kayak… kenangan! Tempat ini penuh sama itu, dan kalian tahu itu. Di sini, di sana, di mana-mana.”
“Kenangan…”
“Iya, benar! Kalian mau buang semuanya?! Cuma karena sekarang keadaannya sedikit lebih baik. Emangnya kalian pikirin itu? Kalian beneran nggak masalah ninggalin semua itu?!”
Yume, Shihoru, dan Moguzo—ketiganya menunduk bersamaan.
Haruhiro menutupi bagian bawah wajahnya dengan tangan. Apa yang sebenarnya ingin Ranta sampaikan? Apa dia sedang mencoba menyampaikan sesuatu tanpa benar-benar mengatakannya secara langsung? Haruhiro tahu maksudnya. Mungkin, mereka semua tahu.
Nggak mungkin mereka nggak tahu.
Mereka pernah tinggal di sini bersamanya. Memang hanya sebentar. Tapi dia pernah ada di sini.
Dia adalah rekan mereka.
Orang yang paling bisa diandalkan. Pemimpin mereka.
“…Itu maksudku.”
Ranta mengendus pelan, lalu menghembuskan napas panjang.
“Tentu saja aku ingin meningkatkan taraf hidup. Tapi bukan itu masalahnya.”
“Yah, iya sih…” Haruhiro menggaruk kepalanya. “Tapi keinginan buat dapat penghasilan lebih, makan makanan yang lebih enak, tinggal di tempat yang lebih bagus… semua itu bisa jadi motivasi juga, kan.”
“Kau dangkal. Terlalu dangkal! Itulah masalahmu, Haruhiro. Kamu tuh… gak punya wawasan!”
“Dan kamu punya…?”
“Jarang ada orang yang pikirannya setinggi aku.”
“Oh, ya…?” ucap Shihoru dengan nada dingin.
“Hah!” Ranta mengangkat bahu. “Kalian ini emang gak bakal ngerti. Cara pikirku tuh di atas level kalian. Lagian, apa hebatnya penginapan khusus perempuan? Cuma perempuan yang boleh masuk, kan? Itu gak alami. Di dunia ini ada laki-laki, ada perempuan. Gak masuk akal kalau isinya cuma perempuan. Serius deh.”
“Ohhh…” Moguzo mengangguk, ekspresi pasrah sekaligus paham.
Jadi itu alasan sebenarnya, ya? Haruhiro menggeleng pelan.
“Jadi… ini soal itu, ya…?”
“A-Apa maksudmu soal itu?! Ngomong yang jelas, bodoh!”
“Intinya… kamu merasa kesepian kalau Yume sama Shihoru sampai beneran pindah dari penginapan, kan?”
“Huuuuuuuuuuuuuuuh?! A-Apa?! Kau gila, ya?! Emang kapan aku bilang kayak gitu?!”
“Kesepian…?” Yume mengernyitkan dahi dan memonyongkan bibir bawahnya. “Ranta, kamu bakal kesepian ya kalo Yume sama Shihoru ninggalin penginapan?”
“A-A-A-A-Aku gak kesepian! Mana mungkin aku kesepian! A-A-A-A-Aku?! Nggak bakal! J-J-Jangan ngelantur!”
Wajah Ranta memerah terang, ludah muncrat ke mana-mana. Dia bener-bener—bingung. Total bingung. Cowok ini beneran goyah. Ada apa sih sama dia?
Haruhiro sempat mengatakan bahwa dia akan merasa kesepian. Itu, uh, cara tidak langsung untuk menyentuh inti masalahnya.
Kalau Yume dan Shihoru tinggal di tempat yang sama, itu membuka banyak kemungkinan. Ini bukan medan perang di mana mereka harus selalu waspada, jadi pasti ada saat-saat ketika mereka lengah—meskipun mereka perempuan. Bukan tak mungkin ada kesempatan untuk melontarkan, “Waduh, maaf,” atau, “Sumpah, kebetulan, beneran,” sesekali.
Ranta terus mengawasi kesempatan seperti itu. Dengan kata lain, dia seperti binatang. Binatang buas sejati.
Kalau Yume dan Shihoru pindah, dia tidak akan punya peluang sedikit pun lagi.
Haruhiro mengutarakannya secara halus, tidak langsung, dengan bilang bahwa dia akan merasa kesepian. Dia tak bisa begitu saja mengatakan, “Jadi kamu nggak bisa ngintip mereka lagi, kan?”
Itu sama saja mengaduk sarang lebah.
Walaupun sebagian besar memang salah Ranta, Haruhiro dan Moguzo juga punya catatan melakukan hal yang sama. —Tapi.
Melihat sikap Ranta, bisa jadi dia benar-benar merasa kesepian.
“A-A-Aku nggak! Sama sekali nggak! A-Aku nggak kesepian! Aku nggak ngerti! Aku nggak ngerti cara mikir kalian yang tolol itu! Nggak masuk akal!”
Ranta berdeham, lalu mengusap bawah hidungnya dengan telapak tangan.
“Pokoknya! Bukan itu maksudku! Aku nggak kesepian, sumpah nggak!”
“Hmm…” Yume men-sandwich pipinya dengan kedua tangan. Wajahnya jadi gepeng dengan cara yang lucu.
“Yah, oke deh. Sekarang setelah dipikir-pikir, Yume juga jadi merasa sedikit kesepian.”
“A-Apa…?” Ranta langsung bereaksi panik. “B-Benarkah? K-Kau merasa… kesepian? K-Kenapa…?”
“Soalnya, ini tempat di mana petualangan kita berakhir setiap harinya.”
Petualangan, ya… Haruhiro tidak sepenuhnya tidak setuju dengan kata itu, jadi ia memutuskan untuk tidak mengejeknya.
Yume masih menekan pipinya, jadi bukan cuma wajahnya yang terdengar aneh, suaranya pun begitu.
“Semua orang balik ke sini, kan? Yah, kecuali Merry-chan. Waktu kita mandi, tidur, bangun… semuanya di sini.”
“Iya juga, ya…” gumam Moguzo sambil menatap ke arah halaman. Shihoru ikut menoleh, memandangi halaman dan bangunan di sekitarnya.
“Kita udah terbiasa, tahu?” kata Yume dengan helaan napas. “Bener-bener terbiasa. Kalau semua ini berubah… Yume mungkin bakal ngerasa kesepian juga…”
“A-Aku tahu, kan?! Itu maksudku sebenarnya!” Ranta mendadak jadi bersemangat. “Memang begitu, kan?! Itu yang dari tadi pengin aku bilang! Kebiasaan itu penting!”
“Ranta, kamu nggak ngomong apa-apa soal itu tadi…”
“Diam, Haruhiro! Aku ngomongnya di dalam hati! Hatiku teriak sekencang-kencangnya!”
“Aku nggak bisa dengar isi hatimu.”
“Itu karena kau kurang latihan! Latihan, dong! Latihan terus! Latihan gila-gilaan!”
“Latihan… apa, coba?”
“Pikir sendiri, tolol! Sekarang, lanjut!” Ranta meletakkan tangannya di pinggang dan membusungkan dada.
“Diskusi selesai! Kita bakal hidup bahagia selamanya di rumah penginapan ini, kan, guys?! Kan?! Sudah diputuskan!”
Shihoru menatap Yume, lalu menunduk memandangi tanah. Sepertinya Yume belum benar-benar yakin.
“…Aku masih mau mikir lagi. Bareng Yume juga.”
5. Ya Begitulah
Setelah itu, Haruhiro pergi ke kota para pengrajin bersama Moguzo. Tentu saja, tujuan mereka adalah mengambil senjata. Awalnya Moguzo sempat berpikir untuk pergi sendiri, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menunggu Haruhiro. Karena sejak awal mereka sudah pergi bersama ke bengkel itu, jadi dia ingin pengambilannya juga dilakukan bersama. Alasan itu agak masuk akal… dan agak tidak juga, tapi terasa sangat khas Moguzo, dan entah kenapa Haruhiro merasa senang karenanya. Rasanya mereka bukan cuma rekan seperjuangan, tapi juga teman.
Dan ternyata, ada kejutan yang menanti mereka.
Seseorang yang familiar berdiri di depan jalan sempit yang mengarah ke Workshop Masukaze.
“Merry?!”
“Merry-san?!”
“Oh…” Merry menoleh ke arah mereka, mulai melambaikan tangan, lalu ragu-ragu menghentikannya. Ia menundukkan kepala sebentar, kemudian kembali mendongak. Wajahnya tampak seperti ingin tersenyum, tapi senyumnya sangat canggung.
Dia terlihat malu-malu.
Saat Merry menunjukkan ekspresi seperti itu, Haruhiro jadi tidak tahu harus berbuat apa. Moguzo juga tampak gelisah.
Iya, aku ngerti, bung. Aku juga bingung harus ngapain. Maksudku, ini bukan masalah sih. Tapi… kenapa, ya?
Jantung Haruhiro berdegup kencang.
“E-Erm…”
Nggak, ini nggak benar.
Kalau Haruhiro terus gugup, situasinya malah bakal terasa canggung buat Merry.
Harus kumpulin keberanian. Keberanian? Nggak, kayaknya nggak butuh yang sampai segitunya. Ini bukan situasi yang menuntutnya buat nekat, kan? Kayaknya nggak. Mungkin.
“H-Huh? A-Ada apa, Merry? Ini… kebetulan? Eh, bukan ya…?”
“Iya…” Merry menyentuh dadanya dengan satu tangan, menarik napas. “Aku pikir kalian akan datang sebentar lagi. Untuk mengambil senjatanya. Karena kita datang bersama, jadi kupikir…”
Perkataan Merry terdengar agak masuk akal bagi Haruhiro, tapi juga agak tidak. Namun dia mengerti. Ya, dia paham maksudnya. Ini semacam perasaan seperti itu. Haruhiro dan Moguzo saling menatap. Benar, kan? Mungkin terdengar aneh untuk mengatakan apa yang sebenarnya “benar,” tapi saat ini, Haruhiro dan Moguzo jelas-jelas sedang berpikir, “Benar, kan?” Ini jenis hal yang mungkin Ranta tidak akan mengerti. Hanya dia dan Moguzo yang bisa saling paham dalam hal seperti ini.
Moguzo bukan tipe orang yang aktif mengambil inisiatif. Haruhiro juga bukan. Dia bukan orang yang supel seperti Kikkawa, dan dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan semua yang dia pikirkan. Dia tidak bisa langsung terbuka dan berteman dengan siapa saja. Memang bukan orang seperti itu.
Dan mungkin, Merry—atau paling tidak, Merry yang sekarang—juga seperti itu. Tapi tetap saja, dia datang.
Dia pasti bergumul dengan perasaannya. Walaupun dia berhasil mengatasi keraguannya dan sampai di sini, dia tetap harus menunggu lama. Mungkin dia bahkan sempat ingin berbalik dan pulang. Tapi Merry tetap tinggal. Dia menunggu sepanjang waktu ini. —Benar, kan?
Melihat hal seperti ini, rasanya… cukup membahagiakan, ya?
“Ohhh, gitu! Gitu. Kalau begitu… kau bisa saja datang ke rumah penginapan, kan? Benar, Moguzo?”
“Y-Ya. B-Benar. Ya.”
“…Aku sempat terpikir.” Suara Merry sangat kecil. Sekecil suara nyamuk. “—Maaf. Aku merasa… agak sungkan.”
“Enggak perlu minta maaf! Iya, kan, Moguzo?! Dia enggak perlu minta maaf, kan?!”
“T-Tepat! Justru karena itu, kita yang harus bilang gitu, kan?!”
“Iya! Maksudku, ada itu!”
“I-Itu, kan?!”
“Iya, itu! Kau tahu yang kumaksud, kan?!”
Haruhiro dan Moguzo saling menepuk bahu, terus membicarakan “hal itu”, tapi sebenarnya itu apa? Haruhiro sendiri tak tahu. Ia sama sekali tak punya gambaran. Moguzo sepertinya juga sama tidak tahunya.
Tapi tak masalah. Mereka memang tidak tahu, dan cukup sampai di situ. Lagipula, Merry sempat tertawa kecil, bahkan—meskipun hanya sebentar—tersenyum juga.
Aku bisa menatap senyuman Merry selamanya. Aku tak bisa menyangkal kalau aku memang merasa begitu. Moguzo mungkin merasakannya juga. Tapi kalau aku terus melakukannya, kurasa Merry bakal merasa canggung. Jadi, lebih baik jangan.
“Kalau begitu, ayo berangkat! Semuanya sudah kumpul!”
“Y-Yep! Ayo, Merry-san!”
“S-Siap.”
Kalau ada yang melihat mereka, mungkin akan menganggap mereka kelompok yang aneh—dan memang agak canggung. Tapi, ya sudah lah. Ini jauh lebih baik daripada saat mereka baru mulai dulu. Nanti juga mereka akan bisa bersikap lebih alami. Semua butuh waktu. Perlahan tapi pasti, tak masalah.
“Halooo~!”
Moguzo membuka pintu Workshop Masukaze dengan semangat ceria dan tenaga luar biasa. Haruhiro tak sengaja bergumam, “Wahh…”
Seperti sebelumnya, mereka disambut oleh si Trigon itu—tapi entah kenapa, sekarang ukurannya tampak lebih besar. Ia tak bisa bilang persisnya kenapa, tapi bentuknya juga sedikit berbeda. Ada aura mengancam dari wujudnya, seakan hendak menerkam. Meski terbuat dari besi, benda itu terasa liar, seperti hidup. Terlalu nyata, bahkan.
“Y-Yang ini… apa, ya?”
Moguzo tampak kebingungan. Merry hanya memiringkan kepalanya, menatapnya tanpa ekspresi.
“Halo, selama—” Riyosuke si pandai besi menyembulkan kepalanya dari balik bengkel, lalu langsung menariknya kembali ke dalam. Lebih tepatnya, dia buru-buru masuk lagi ke ruang tempa di belakang.
“Huh?” Haruhiro mengerutkan alis, melirik Moguzo dan Merry dengan bingung. “T-Tadi dia kabur… kan? Baru saja? Kenapa…?”
“Ah, tidak, tidak.” Riyosuke keluar lagi, kali ini sambil menggaruk kepalanya. “Hehe, bercanda, kok. Selamat datang. Ada keperluan apa kalian datang ke bengkel ini?”
“Keperluan, ya…” Moguzo cepat-cepat melihat sekeliling bengkel. “Umm, jelasnya sih, aku datang buat ngambil senjata yang kutitipkan kemarin-kemarin.”
“Oh, ho. Senjata seperti apa itu?”
“S-Senjata seperti apa…? A-Aku nitip di sini, kan? J-Jangan bilang… kau lupa, atau semacamnya…?”
“Hrm…” Riyosuke menyilangkan tangan. “Nngh…” Pandangannya mengarah ke langit-langit. “Hmmm… Yang mana, ya…?”
“Ya ampun.” Haruhiro tak bisa menahan tawa. “Enggak mungkin kamu lupa. Enggak mungkin. Kami kan titipkan pedangnya Death Spots ke sini. Kamu bahkan udah kasih estimasi biayanya. Harusnya sekarang udah jadi, kan?”
“Oh, ya?” tanya Riyosuke, dengan ekspresi serius.
“Ada apa sih sama orang ini…?” gumam Merry pelan.
Itu dia. Ada apa sebenarnya dengan orang ini? Ini buruk, ya? Dia memang terlihat agak aneh, tapi jangan-jangan lebih parah dari yang mereka kira. Apa dia sengaja memperdaya mereka, lalu mencuri pedangnya Death Spots?
Haruhiro tiba-tiba menyadari bahwa Moguzo sedang gemetar. Kedua tangannya mengepal, dan tubuhnya bergetar.
Dia marah…?
“Itu seharusnya sudah selesai, kan?”
Suara Moguzo terdengar sangat mengancam. Tapi tetap sopan. Dia masih berhasil menahan amarahnya—hanya sedikit lagi sebelum meledak. Riyosuke tampaknya menangkap sinyal bahwa dia mungkin sedang berhadapan dengan pelanggan yang berbahaya. Ia langsung tersenyum. “Aku cuma bercanda, cuma bercanda,” katanya. “Ya, selesai… seharusnya memang begitu.”
“Tapi?” tanya Haruhiro.
“Yah…” Riyosuke menggaruk belakang kepalanya dengan canggung. “Awalnya aku memang berniat menyelesaikannya. Tapi saat sedang mengerjakan desainnya, aku jadi sedikit… ambisius.”
“…Ambisius?” Merry memiringkan kepalanya.
“Ya, ini kebiasaan burukku. Aku ingin melakukan ini, ingin menambahkan itu, merasa harus begini. —Begitu terpikirkan, rasanya nggak bisa aku abaikan. Kurasa semua pengrajin itu begitu, setidaknya sampai taraf tertentu.”
“Jadi, intinya…” Haruhiro menatap Trigon itu, “Belum selesai, ya?”
“Persis sekali.”
“Cepat banget ngakuinnya…”
“Soalnya itu kenyataannya,” jawab Riyosuke sambil mengangguk bijak. Kenapa orang ini malah kelihatan senang?
Suara Moguzo bergetar saat ia mengajukan pertanyaan yang jelas, “Ka-Kapan…?” katanya. “Kapan akan selesai?”
“Soal itu…” Riyosuke memasang ekspresi serius, lalu menunjuk lurus ke atas. “‘Hanya Tuhan yang tahu,’” jawabnya.
“Kau tahu itu bukan jawaban yang bisa diterima, kan?”
Bagus, Merry. Nadamu barusan menyeramkan.
Riyosuke tampak agak gentar.
“I-Iya kalau diberi satu atau dua hari…” Langsung saja, “Terlalu samar,” desak Merry dengan dingin.
“Ah…” Riyosuke menyatukan kedua tangannya di depan dada. “Bagaimana kalau… besok?”
“Lebih spesifik,” kata Merry, tetap dengan ekspresi tajam.
“Akan selesai besok jam 8 pagi! Kalian datang ke tempat yang tepat.”
Haruhiro refleks melirik ke arah Trigon. “…Sepertinya aku pernah dengar kalimat itu sebelumnya. Persis begitu.”
“Akan langsung kukerjakan.” Riyosuke memberi mereka jempol, lalu berlari masuk ke bengkel di belakang.
Bahu Moguzo langsung merosot kecewa, dan Merry menatapnya dengan penuh rasa iba.
Dengan ragu, Haruhiro menyentuh Trigon itu. “…Tapi orang itu jelas-jelas udah ngubah banyak bagian dari benda ini. Apa bakal aman…?”
6. Teror Itu Kembali
Dentang lonceng terdengar, menandakan waktu. Pukul 08.00 pagi. Haruhiro dan yang lainnya sudah berdiri di depan Workshop Masukaze.
Hari ini bukan hanya Haruhiro, Moguzo, dan Merry saja. Ranta, Yume, dan Shihoru juga ikut. Begitu mereka mengambil senjatanya, mereka berencana langsung pergi berburu. Semuanya sudah siap berangkat. Yang mereka tunggu tinggal senjata Moguzo.
“U-Umm…” Moguzo membuka pintu Bengkel Masukaze.
“Wah…?!” Ranta langsung terhuyung ke belakang.
“Eek…!” Shihoru refleks memeluk Yume, dan, “Nyoh!” Yume mengeluarkan pekikan aneh sebagai balasan.
Haruhiro, Moguzo, dan Merry semua menelan ludah.
Trigon, naga-kuda beroda itu, seperti biasa, duduk di sisi lain pintu. Tapi—setidaknya menurut pengamatan Haruhiro—bentuk kepalanya tampak sedikit berbeda dari kemarin. Apa dia mengutak-atiknya lagi? Tapi yang lebih penting dari itu…
“Selamat datang.” Riyosuke si pandai besi sedang berlutut di depan Trigon.
Itu tak masalah. Tapi… kenapa?
Kenapa Riyosuke telanjang dari pinggang ke atas?
Dan, kenapa ada sebilah belati yang belum bersarung tergeletak di depan lututnya?
Ekspresinya tampak serius. Bahkan, ada sesuatu yang terasa menyedihkan dari dirinya.
“Untuk urusan apa kalian datang ke bengkel ini?” Tapi, dari cara dia mengatakannya lagi…
Orang ini jelas tidak waras.
“Urusan apa…?” Haruhiro hanya sempat mengucapkan itu, lalu terdiam.
Riyosuke mengangguk tanpa suara. “Hanya bercanda.” Ia memejamkan mata. “Aku sudah menunggu kalian.”
“…U-Um,” Moguzo bertanya ragu, “Di mana s-senjata yang kutitipkan padamu…?”
“Aku sudah menduga kau akan bertanya begitu.”
“Huh…? Ya, m-maksudku, itu satu-satunya urusanku di sini, kan…?”
“Itulah kenapa! Aku sudah bilang aku menunggu, kan?!”
Dia terlihat marah padahal dia yang salah…?
Ya. Pasti begitu.
Itu jelas-jelas yang dia lakukan. Tidak mungkin bukan itu.
Tak satu pun dari mereka—bahkan Ranta sekalipun—bisa berkata apa-apa sebagai balasan. Mereka terdiam, terpukau oleh intensitas aneh Riyosuke.
“Dengarkan baik-baik!” Mata Riyosuke terbuka lebar. “Benar, aku menerima senjata kalian! Itu memang benar! Kemarin, aku bilang akan selesai besok jam 8 pagi! Aku bilang begitu, iya! Tapi! Itu bukan jaminan bahwa benar-benar akan selesai! Tidak ada yang pasti! Tidak ada! Bukankah hidup memang begitu?! Bukankah begitu?! Aku salah ngomong? Tidak, kan?! Tidak! Kalau semua berjalan sesuai rencana, hidup akan membosankan, bukan?! Ketidakpastian! Itulah hidup! Ya, di sanalah letak kebahagiaan hidup! Dengan kata lain…! Inilah hidup…!”
“…Orang ini ngomongin apa sih?” tanya Yume pada Shihoru.
Shihoru tampak bingung mencari jawaban, lalu hanya berkata, “A-Aku juga nggak tahu…” sambil menggeleng pelan.
“Jadi maksudmu…” Merry maju ke depan. “Belum selesai?”
Riyosuke menutup mata, lalu menggeleng… tapi menyerong. Kenapa menyerong…?
“Aku tidak pernah bilang begitu.”
“Ka-Kalau begitu…” Moguzo menelan ludah. “Apakah… sudah selesai?”
“Cetek!”
“…Cetek?”
“Pertanyaan itu cetek! Iya atau tidak! Hitam atau putih! Apa hidup sesederhana itu? Tidak, kataku! Tidak…!”
“Tapi yang itu jawabannya ‘tidak’, ya…?” Haruhiro tak bisa menahan diri untuk menunjukkannya. Padahal Riyosuke baru saja bilang kalau kita tidak bisa membagi semuanya ke dalam hitam dan putih. Namun Riyosuke hanya tersenyum tenang.
“Kadang kita tetap harus menemukan sebuah jawaban. Itu juga bagian dari hidup.”
“Hei…” Ranta menunjuk Riyosuke. “Apa pun yang dia omongin aneh semua. Nggak ada satupun yang masuk akal…”
“Padahal kamu sendiri juga gitu…”
“Apa maksudmu, Haruhiro?! Apa yang aneh dari aku?! Aku ini orang paling logis sedunia!”
“Iya!”
“Tuh, pria itu juga setuju—Eh, bentar…?”
“Ya?”
Riyosuke tampak sama sekali tak terganggu saat Ranta menatapnya. Ranta menunjuk dirinya sendiri, lalu Riyosuke, lalu dirinya lagi.
“Kita belum pernah ketemu sebelumnya, kan…?”
“Bisa dibilang begitu.”
“…Huh? Maksudmu ‘bisa dibilang gitu’ itu apa…?”
“Itu pertanyaan yang bagus.”
“M-Menurutmu begitu?”
“Ya. Tapi itu pertanyaan yang dalam. Maukah kau mempertimbangkannya bersama-sama denganku, sampai kita menemukan jawabannya?”
“Enggak, aku nggak mau… Aku nggak mikir juga. Dan tunggu, ada apa sih sama orang ini?”
Apa jangan-jangan…
Dia sedang mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap mereka semua kebingungan lalu melupakan soal itu begitu saja…?
“…Aku mengerti sekarang.” Merry melangkah lebih maju, menghentakkan ujung tongkatnya ke tanah di antara Riyosuke dan belatinya. “Kalau kamu terpojok, rencanamu pasti membuat keributan seolah-olah kamu akan melakukan seppuku pakai belati ini, kan? Begitu caramu.”
Riyosuke menatap Merry… lalu menyeringai. Ekspresinya masih terlihat tenang, tapi keringat membasahi wajahnya.
“Sepertinya kau salah paham.”
“Oh, begitu?”
“Aku tidak akan pernah melakukan seppuku. Jangan salah sangka.”
“Aku juga tidak yakin kau benar-benar akan melakukannya. Paling cuma pura-pura.”
Riyosuke menatap Merry beberapa saat, lalu menundukkan pandangannya. “…Kau hebat,” gumamnya. “Sudah tiga tahun sejak terakhir kali ada yang berhasil menggagalkan trik ini. Haaah… kau benar-benar berhasil. Aku menyerah. Aku paham. Mari kita bicara terus terang, ya? Terus terang! Ya, terus terang…!”
“Kenapa mengulang kata yang sama tiga kali…?” Shihoru bertanya dengan bergidik, tapi Riyosuke justru meneriakkan kata yang terlarang itu untuk keempat kalinya.
“Aku akaaaaan! Terus terang—”
Swoosh… Tongkat Merry melesat dan nyaris menyentuh pipi Riyosuke. Tongkat priest itu bukan sekadar hiasan. Sebaris luka merah tertinggal di pipinya—Darah. Dia berdarah.
“Bicara terus terang. Kapan selesai?”
“…Sore ini?”
“Jam berapa?”
“Jam sembilan, atau sepuluh—”
“Jadi kau bilang akan selesai malam?”
“Huh? Tidak, jam enam sore… kira-kira.”
“Kira-kira?”
“Jam empat! Tidak, aku cuma sok keren! Jam empat mustahil! Jam enam…!”
“Jam enam tepat, mengerti?”
“Siap!”
“Kau tahu apa yang akan terjadi kalau kau terlambat?”
“…Kurang lebih.”
“Pastikan selesai kali ini.”
Merry menarik kembali tongkatnya dan membalikkan badan meninggalkan Riyosuke.
Saat itu juga, “Haaah…” Riyosuke mengembuskan napas panjang. Selamat. Aku selamat. Entah bagaimana aku berhasil melewatinya. Ekspresi wajahnya seakan menyuarakan semua itu.
Seolah berkata, “Betapa naifnya,” Merry berputar dan langsung menyorongkan tongkat priest-nya ke ujung hidung Riyosuke.
“Dengar. Jangan buat aku kecewa.”
“…Dimengerti.”
“Kami akan datang pukul enam sore.”
“…Aku akan menunggu.”
Bahkan wajah Riyosuke kini tampak sedikit pucat, dan dia memandangi ujung tongkat itu. Mata julingnya makin menjadi. Serius, juling sekali.
Merry menusuk hidung Riyosuke dengan ujung tongkatnya.
“Eek!”
Tanpa sedikit pun menoleh saat Riyosuke terjengkang ke belakang, Merry melangkah keluar dari bengkel.
“…Serem banget dia,” bisik Ranta. Mungkin tak sepatutnya dia berkata begitu soal rekan sendiri. Tapi, jujur saja, Haruhiro juga merasakan hal yang sama. Jelas dia tak bisa bilang begitu di depan Merry. Atau lebih tepatnya, kalau dia mengucapkan, “Jujur saja,” di depan Merry setelah apa yang barusan terjadi, dia yakin sesuatu yang sangat mengerikan akan menimpanya…
Bagaimanapun juga, sekarang Merry sudah keluar, jadi dia tak bisa membiarkannya pergi sendiri. Setelah memberi tahu Riyosuke, “Baiklah, kami akan kembali pukul enam sore nanti!” Haruhiro ikut keluar dari bengkel—tapi begitu sampai di luar, dia tak melihat Merry, dan sempat panik.
“M-Merry…?!”
Dia berlari cepat menyusuri jalan sempit itu. Menoleh ke kanan. Lalu ke kiri.
Ketemu.
Merry berdiri diam dengan kepala tertunduk. Ada apa dengannya? Punggungnya menghadap Haruhiro, jadi dia tak bisa melihat wajahnya. Tapi entah kenapa, dia terlihat… murung?
Haruhiro tak sanggup memanggilnya. Saat dia ragu, Yume melangkah santai ke arahnya, berputar ke depan, lalu menatap wajah Merry dari dekat.
“Merry-chan? Ada apa?” tanya Yume dengan bingung.
“Aku… maaf. Aku tadi…”
“Foo?”
“Yang barusan tadi, itu…”
Ranta datang menghampiri mereka dengan langkah lebar. “Heh!” Ia mengacungkan jempol ke arah Merry. “Lumayan juga. Tadi itu keren. Nggak heran kau dulu dipanggil ‘Merry Si Menyeramkan’!”
“…!” Merry menggeleng cepat.
Haruhiro sempat bertukar pandang dengan Shihoru dan Moguzo yang baru saja menyusul mereka. Tingkah Merry jelas aneh. Yang pasti, dia tidak terlihat seperti sedang tersenyum puas dan berpikir, ‘Tuh kan, kena juga dia.’ Malah sebaliknya. Seolah dia merasa gagal, seperti ‘Duh, aku kebablasan.’ atau semacamnya?
Yume mencoba bicara, mulutnya membuka dan menutup, tapi yang keluar hanya, “Uhh,” dan, “Nngh,” atau, “Mew.” Tak satu pun terdengar seperti kata-kata sungguhan.
Ranta menoleh ke Haruhiro dan memiringkan kepalanya. “…Apa?”
Jangan sok nggak tahu. Itu karena kau manggil dia Merry Si Menyeramkan.
Tapi… benarkah cuma itu? Apa hanya karena itu?
Tiba-tiba, Merry menarik napas dalam-dalam dan mengangkat wajahnya. Dia menatap satu per satu dari mereka. Itu senyuman, ya? Tapi dipaksakan. Tak ada niat sungguhan di baliknya.
“Kalau begitu, kita ketemu lagi di sini, jam enam.”
Setelah mengatakan itu, Merry langsung pergi. Bukan lari, sih—tapi jalannya cepat, sangat cepat. Bisa dibilang dia kabur.
“Ada apa sih sama dia…?” gumam Ranta, tapi saat itu Merry sudah menghilang jauh dari pandangan.
Aku harus nyusul dia. Tapi mau bilang apa?
Haruhiro tak tahu. Dan menyedihkannya, kakinya bahkan tak mau bergerak.
7. Hati, Terbuka
Meski begitu, membiarkannya seperti itu tetap mengganggunya. Siapa yang tidak akan terganggu? Dia pasti gila kalau tidak peduli.
Mereka sepakat untuk berpencar dan melakukan hal masing-masing sampai pukul enam, tapi Haruhiro sudah tahu bagaimana ia ingin menghabiskan waktunya.
Aku akan mencari Merry.
Ia punya sedikit gambaran ke mana harus mencari. Altana memang terlihat besar, tapi dalam banyak hal, sebenarnya cukup kecil juga. Kalau ia terus berjalan-jalan, ia yakin cepat atau lambat akan menemukan Merry.
Sambil melakukan ini dan itu, bel berbunyi menandakan waktu telah menunjukkan pukul dua belas siang—dan ia masih sendirian.
“Haah… Seriusan? Aku belum nemu juga…”
Haruhiro terduduk lemas di sudut sebuah alun-alun yang entah berada di mana, kira-kira dekat pusat kota Altana.
Di seberang alun-alun berdiri sebuah bangunan tinggi bernama Menara Tenboro. Menara itu adalah tempat tinggal markgraf. Garlan Vedoy. Penguasa Altana—katanya. Haruhiro tahu namanya, tapi belum pernah melihat orangnya. Jujur saja, yang ia tahu hanya, “ada orang penting bernama begitu.” Yah, seorang prajurit relawan seperti Haruhiro memang kecil kemungkinan bisa bertemu dengan orang sepenting itu.
“…Bodo amat.”
Apa aku makan siang saja, ya? Tapi itu pun terasa merepotkan. Tapi aku lapar. Perutku kosong, tapi suasana hatiku lagi nggak enak buat makan.
Saat ia sedang mondar-mandir tanpa tujuan, suara seseorang terdengar dari kejauhan.
“Huh?! Haruhiro-kun?!”
“…Moguzo.”
Moguzo berlari menghampirinya.
“Ada apa, Haruhiro-kun? Lagi ngapain di sini?”
“Hmm. Nggak, nggak ngapa-ngapain, sih. Aku nggak ngelakuin apa pun…”
“Umm…” Moguzo tampak canggung, tapi tetap bicara. “Kamu sempat bertemu dengan Merry-san?”
“Eh… K-Kenapa aku harus ketemu Merry?”
“Soalnya… Pagi ini, Merry-san terlihat agak aneh. Aku mikir, ‘Mungkin Haruhiro-kun jadi khawatir dan pergi nyari dia.’ Jujur aja, aku juga sempat nyari dia, sih, walaupun nggak terlalu niat.”
“O-Oohh… Iya. Merry memang kelihatan aneh. Iya, ya… Maksudku, aku juga jadi kepikiran. Ya jelas lah, kami ini kan rekan satu tim…”
“B-Benar, kan? Kita ini rekan. Dan kau pemimpin kami.”
“Secara teknis, iya sih? Tapi rasanya nggak cocok aja. Agak memalukan juga…”
“Tapi kau memang lagi nyari Merry-san, kan?”
“Uhhh… Iya, tapi nggak yang sampai serius banget, gitu. Aku cuma lihat-lihat aja, sambil jalan…”
Aku memang nyari. Aku keliling cukup banyak juga —tapi Haruhiro ragu untuk bilang terus terang pada Moguzo. Dia nggak mau Moguzo jadi menebak-nebak maksud sebenarnya. Haruhiro melakukannya dengan niat baik—sebagai rekan satu tim, dan sebagai pemimpin yang khawatir dengan kondisi Merry. Hanya itu.
“J-Jadi, Haruhiro-kun, um… kalau kamu memang nyari dia juga, gimana kalau kita cari bareng?”
“Bagus tuh idenya!” Haruhiro langsung berdiri. “A-Ayo, kita cari bareng! Mungkin lebih gampang nemuinnya kalau bareng-bareng. Oh, Moguzo, kau udah makan siang belum? Belum? Ya udah, ayo kita makan dulu. Di warung kaki lima sekitar sini, atau di pasar juga boleh. Yang ringan-ringan aja. Merry pasti lagi makan juga di suatu tempat, ‘kan? Aku yakin, deh.”
Dengan catatan itu, mereka pun menuju ke Sate Dory di pasar, dan ternyata Yume serta Shihoru sudah ada di sana.
“Huh…!”
Shihoru sedang menyumpal mulutnya dengan sebatang tusuk sate saat itu, dan tampak sangat malu karenanya.
Yume, di sisi lain, berseru, “Unyoh!” dengan mata membelalak, lalu segera menghabiskan daging yang sedang ia santap.
“Hei, itu Haru-kun sama Moguzo. Kalian ke sini buat makan daging, ya?”
“Iya.” Moguzo mengangguk, lalu langsung memesan tusuk sate. “Aku ambil dua. Eh, enggak, tiga deh.”
“…Langsung pesan tiga? Hebat juga, Moguzo. Aku satu aja, deh.”
“Enggak, satu tusuk tuh pasti kurang. Dua mungkin cukup, tapi tusuk sate Dory itu enak banget, dan aku udah sampai sini juga…”
“Ohhh. Iya juga, ya. Aneh, ya, daging di sini kok bisa seenak itu.”
“Iya. Tadi Yume nanya Shihoru enaknya kita ke mana siang nanti, terus Shihoru bilang kita ke tempat Dory aja.”
“…A-Aku nggak kepikiran tempat lain, itu aja, kok… Ah!”
Shihoru buru-buru menoleh ke arah kakek penjual tusuk sate itu dan menundukkan kepala.
“U-Umm, d-daging Anda enak banget. Sungguh. A-Aku juga suka…”
Si kakek membalasnya dengan senyum lapang dada. Kalau dipikir-pikir, Haruhiro pertama kali mampir ke warung ini saat masih jadi calon prajurit relawan. Sepertinya si kakek mengenali wajah mereka, jadi bisa dibilang mereka sudah jadi pelanggan tetap.
Jumlah tempat di Altana yang bisa disebut “langganan” untuk mereka memang makin lama makin bertambah, meskipun pelan.
Apakah Merry juga begitu? Ia pasti punya tempat-tempat yang biasa ia datangi juga.
Sambil memakan tusuk dagingnya, Haruhiro memutuskan untuk bertanya pada Yume dan Shihoru.
“Hey, kami sedang berpikir buat nyari Merry. Maksudku, ya, aku tahu kita bakal ketemu dia jam enam nanti, tapi… pagi ini, dia kelihatan agak aneh, kan? Itu bikin aku agak khawatir.”
“…Kami juga, sebenarnya.”
Shihoru sudah menghabiskan tusuk dagingnya dan kini meminum minuman yang dibelinya dari kios lain. Minuman itu berkarbonasi, dengan rasa herbal dan madu. Harganya dua koin tembaga, tapi kalau mengembalikan cangkir tanah liat tipisnya ke kios, kau akan mendapatkan satu koin tembaga kembali.
“Kami khawatir sama Merry… Aku juga memperhatikan sekeliling pasar tadi, siapa tahu dia lewat…”
Ngomong-ngomong, kenapa Shihoru sempat terhenti setelah menyebut “Merry…” tadi? Apa karena itu? Karena mereka rekan satu tim, jadi wajar menyebut namanya tanpa embel-embel kehormatan. Mungkin Shihoru sedang mencoba membiasakan diri. Tapi karena belum terbiasa, jadinya terdengar ragu—apa begitu?
Kalau dugaan Haruhiro benar, akan canggung kalau dia menyinggung hal itu.
Lambat laun Shihoru akan terbiasa. Meskipun butuh waktu.
Tapi waktu tidak tak terbatas. Bisa saja habis besok.
Shihoru mungkin sangat menyadari bahwa tak ada jaminan mereka akan hidup sampai hari esok. Bahkan mungkin lebih sadar dari siapa pun di antara mereka. Mungkin itu sebabnya Shihoru berusaha sekuat tenaga untuk mempersempit jarak emosional antara dirinya dan Merry.
Mereka mungkin masih punya waktu untuk bersantai. Tapi mungkin juga tidak.
“Menurutmu, Merry-chan pergi ke mana, ya?” tanya Yume sambil mengunyah. “Apa dia sudah balik ke penginapan?”
“…Ka-Kalau dia memang sudah balik, kita nggak bisa nyusul dia, ya?” Moguzo mengeluh, menggenggam tiga tusuk sate di kedua tangannya.
…Dia udah ngabisin ketiganya? Cepat banget!
“Penginapan, ya…” Haruhiro menepuk kening dengan telapak tangan kirinya. “…Ngomong-ngomong, Ranta ke mana, ya? Ada yang tahu?”
“Yume nggak lihat, dan Yume juga nggak tahu.”
“…Aku juga nggak lihat. Dan terus terang, aku juga nggak peduli.”
“Oh, Ranta-kun tadi sempat ngomong soal permainan.”
“Permainan?”
Pertandingan macam apa, sih, itu? Haruhiro benar-benar nggak punya gambaran. Tapi dia punya firasat buruk. Ini Ranta, lho. Mana pernah ada hal baik yang terjadi kalau dia dibiarkan sendirian. Tapi kalau harus ngawasin Ranta terus-menerus juga capek banget. Kalau dia harus jagain Ranta 24 jam sehari, dia bisa-bisa beneran jadi benci sama orang itu.
Untuk sekarang, mending lupakan soal Ranta dan cari Merry bareng yang lain. Rasanya nggak mungkin Merry ada di wilayah timur tempat markas guild mage, atau wilayah barat tempat guild thief dan dread knight. Apa dia ada di distrik selatan tempat penginapan mereka dan kota para pengrajin? Atau di distrik utara tempat pasar, Jalan Taman Bunga, dan Gang Celestial?
Saat mereka hendak keluar dari pasar untuk memeriksa Jalan Taman Bunga, mereka melihat kerumunan orang di sepanjang jalan.
“Ohhhh, yessss…!”
Suara itu, datang dari balik kerumunan…
“Itu suara Ranta, ‘kan?”
“Y-Ya.”
“…Kita abaikan saja.”
Haruhiro mengerti perasaan Shihoru, tapi dia tak bisa begitu saja mengabaikannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin mereka. Dan yah, Ranta itu secara teknis masih rekan mereka, kan?
Ia mendorong tubuhnya melewati kerumunan, lalu menemukan Ranta bersama beberapa pria lain yang duduk melingkar di sekitar meja kayu pendek.
“Ranta, serius…”
“Huh? Wah, kalau bukan Haruhiro. Ngapain kamu di sini, bung?”
“Harusnya aku yang tanya… Kamu lagi ngapain?”
“Enggak kelihatan, ya?”
Ranta menunjukkan kartu-kartu persegi panjang yang ada di tangannya. Ada empat atau lima lembar, dan di masing-masing terlukis gambar-gambar. Kalau diperhatikan lebih dekat, ada tumpukan kartu sejenis yang berserakan di atas meja, tidak tersusun rapi.
“Aku lagi main game, jelas banget lah. Aku ini gamer alami, dilahirkan untuk bermain, master game, ngerti, kan?”
“…Oke, deh. Tapi aku baru dengar sebutan itu sekarang.”
“Oke, giliranku! Gini caranya!”
Ranta membanting kartunya ke atas meja, sekaligus membalik dua kartu lainnya.
“Yessss…! Ganda! Aku dapet gan-daaaaaaa…!”
“Sialan!”
Seorang pria lain yang tampak kotor dengan wajah memerah membanting kartunya, membalik tiga kartu sekaligus.
“Tuh! Gimana?!”
Ranta dan para pria lainnya menjerit, “Triple…?!”, lalu memegangi kepala mereka.
“…Ranta, kamu pasti main pakai uang, ya? Aku yakin kamu taruhan.”
“Jelas aja lah! Apa serunya main kalau nggak dapat duit?! Aku nggak bisa serius kalau nggak ada taruhan!”
“Jadi… kau menang, gitu?”
“Hah!” Ranta memalingkan muka. “Ini baru pemanasan! Di sinilah titik baliknya! Aku bakal balikkan keadaan besar-besaran…!”
“…Aku nggak mau tanya kau udah kalah berapa. Jujur aja, aku takut tahu. Tapi tolong, kendalikan dirimu, ya?”
“Bodoh! Di setiap permainan, itu menang atau kalah! Nggak ada istilah ngendalin diri! Kau nggak tahu, ya, bego?! Goblok! Mati aja sana, menderita karena ambeien!”
Dia mau main sampai bangkrut? Haruhiro khawatir, tapi dia juga tahu dirinya nggak punya kekuatan buat menghentikan Ranta. Toh, dia nggak bakal mau denger. Malah, makin Haruhiro nyuruh dia berhenti, makin keras kepala dia jadi. Kalau begitu, membiarkannya sendiri mungkin pilihan terbaik.
“Ya udah, semoga beruntung.”
“Nggak usah disuruh juga aku bakal serius! Aku bakal terus main sampai balik lagi 1 emas yang—”
“1 emas…?! Serius, kau kalah 1 emas?!”
“Baru 1 emas doang! Aku masih punya banyak duit! Di akhir permainan, yang punya duit paling banyak pasti menang…!”
“Kau yakin kamu nggak malah jadi bahan ketipu dan kehilangan semuanya…?”
“Diam! Tutup mulutmu, dan pergi sana! Pergi jauh-jauh! Ngilang, Parupiro!”
“Ya, ya, aku pergi. —Oh, tapi sebelum itu. Cuma mau pastiin… Kau lihat Merry, nggak?”
“Huh? Iya, aku lihat.”
“Huh?”
“Di dekat jembatan, beberapa jam yang lalu, waktu aku balik ke rumah penginapan. Aku benar-benar cuekin dia, sih. Dia juga lagi nunduk dan sama sekali nggak nyapa aku. Emangnya kenapa?”
“Dia ada di sana?! Dekat rumah penginapan?! Merry?!”
“Iya, kan udah kubilang tadi. Tapi itu udah agak lama. Sekarang dia pasti udah pergi ke tempat lain. Maksudku, ngapain juga dia ada di sana?”
Haruhiro langsung bilang ke Ranta, “Tahu batas, ya!” lalu berlari menerobos kerumunan. Sepertinya Moguzo, Yume, dan Shihoru juga mendengar percakapan mereka. Mereka saling bertukar pandang, mengangguk, lalu buru-buru menuju rumah penginapan.
Kalau kata Ranta, dia melihat Merry beberapa jam lalu. Berarti itu sebelum tengah hari. Sulit dibayangkan kalau dia masih ada di jembatan dekat rumah penginapan sekarang. Sudah pasti dia pergi. Nggak mungkin dia masih di sana. Tapi tetap saja, mereka nggak punya petunjuk lain. Jadi walaupun kemungkinan dia masih di sana nyaris nol, tapi bukan berarti mustahil sepenuhnya.
“Nyaa! Itu Merry-chan, kan? Yang di sana!”
Yume, sebagai seorang hunter, punya penglihatan yang tajam—dan dialah yang pertama melihat Merry.
Jembatan itu. Dia ada di sana. Itu Merry. Nggak salah lagi. Dia sedang berdiri di atas jembatan.
“Merry…!”
“Merry-san…!”
“M-Merry…!”
“Merry-chan…!”
Keempatnya memanggil nama Merry bersamaan, dan Merry pun menoleh ke arah mereka. Matanya membelalak kaget. Ya, tentu saja. Siapa pun pasti bakal kaget kalau namanya diteriakkan sekencang itu. Lagi pula, pasti memalukan juga buat dia. Kalau Haruhiro ada di posisi Merry, mungkin dia malah bakal lari tanpa sadar.
Merry tidak lari. Ia menggenggam stafnya erat-erat dan tetap berdiri di tempat, menunggu mereka.
Mereka semua berlari menuju jembatan hingga terengah-engah. Haruhiro sendiri, selain napasnya yang memburu, bahkan tidak tahu harus berkata apa. Pasti ada hal-hal yang ingin ia sampaikan, tapi pikirannya terlalu kacau sekarang.
Merry mengerutkan alis sedikit, bibirnya mengatup rapat saat memandangi Haruhiro dan yang lainnya. Ia juga tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa menemukan kata-katanya.
Akhirnya, Shihoru hanya berkata, “Ke…” lalu menutup mulutnya kembali. Butuh waktu sebelum ia membuka mulut lagi dan menyelesaikan kalimatnya, “Kenapa…?”
“Aku…” Merry menundukkan pandangannya. “Aku sungguh—” Sepertinya ia hendak meminta maaf. Maaf, pasti itu yang akan ia katakan. Dan itulah satu hal yang tidak ingin Haruhiro biarkan ia lakukan. Merry tidak punya alasan untuk minta maaf.
“Syukurlah!” seru Haruhiro dengan suara paling ceria yang bisa ia keluarkan. Nada itu terasa janggal, dan keheningan canggung langsung menyelimuti mereka.
Duh. Itu tadi… gagal total. Kenapa aku nggak bisa bilang sesuatu yang lebih peka sih? Rasanya pengen nangis. Tapi kalau aku nangis, ini pasti bakal makin runyam, jadi nggak boleh.
“…Sy-Syukurlah. Umm, untuk, uh, apa tadi ya…? Syukurlah kami menemukanmu. Oh! Tapi ini bukan karena aku, kayak, terlalu lebay atau gimana karena bisa ketemu kamu, ya—”
Aaaarghhh! Ini benar-benar kacau. Haruhiro nyaris menjatuhkan diri ke tanah dan menggeliat-geliat karena frustrasi. Semakin banyak ia bicara, suasananya malah makin canggung.
Merry mendengarkan dengan serius, tapi pada akhirnya, ia memiringkan kepala, nampak bertanya-tanya dalam hati, Orang ini sebenarnya mau ngomong apa sih…?
Wajar. Wajar banget.
Haruhiro sendiri merasa… mungkin ia tahu maksudnya, atau mungkin juga tidak. Tidak, ia tidak tahu. Apa tadi? Sebenarnya ia sedang mencoba membicarakan apa?
“P-Pokoknya… Intinya… Gimana ya bilangnya…? Rasanya kayak…”
Mungkin karena tidak tahan melihatnya lagi, Yume pun menyela, “Ngomong-ngomong, Merry-chan udah berapa lama di sini?”
“Kurasa aku udah di sini dari…” Merry menggantungkan kalimatnya, lalu melanjutkan dengan suara yang sangat pelan, “…jam sembilan, mungkin…?”
“…Jam sembilan,” ulang Shihoru sambil menoleh ke Haruhiro.
“…Jam sembilan?” Haruhiro pun menoleh ke Moguzo.
“Jam… jam sembilan…” Moguzo menoleh ke Yume.
“Jam sembilan… Tunggu. Nnngh…” Yume berpikir keras sambil berkedip-kedip. “Itu lama banget, ya? Kamu bilangnya jam sembilan, tapi sekarang udah lewat tengah hari… Whaaaaa! Itu beneran lama banget…!”
“…Aku ingin menjelaskan.” Merry menyusut sedikit, tubuhnya bergetar halus. “…Kupikir kalau aku tunggu di sini, mungkin seseorang akan datang.”
“Um…” Moguzo ikut menunduk, menyusut tak kalah dari Merry, dan membungkukkan punggungnya. “Menjelaskan apa?”
“…Tentang apa yang terjadi di Workshop Masukaze. Sikapku di sana, bisa dibilang…”
“Mwah. Cara kamu bersikap di bengkel itu, kelihatan tegas dan keren banget.”
“…B-Berhenti. Itu salah. Aku nggak seharusnya seperti itu.”
“Benarkah…?” Sepertinya Shihoru agak kesal saat mengingat bagaimana perlakuan Riyosuke si pandai besi terhadap mereka. “Kurasa kamu memang harus tegas terhadap orang-orang seperti itu… Bukan berarti aku sendiri bisa melakukannya. Aku terlalu penakut… Kurang percaya diri, kurasa…”
“Aku juga… gak percaya diri.”
“A-Aku juga enggak!”
“Yume juga, dia nggak percaya diri juga, lho?”
“…Aku juga, sih.”
Ini apa, sih? Ada apa ini? Estafet pengakuan kekurangan rasa percaya diri, atau bagaimana?
Tapi—sebagai pemimpin mereka, bukankah Haruhiro seharusnya tidak ikut-ikutan menyatakan kalau dia tidak percaya diri? Memang sih, dia gak punya. Tapi siapa juga yang mau dipimpin orang kayak gitu? Kalau memang dia pemimpin, sejujurnya, meski sebenarnya dia tidak punya rasa percaya diri, mungkin setidaknya dia harus pura-pura punya.
“U-Umm, enggak!”
Haruhiro menepuk kedua tangannya. Yang lain langsung menatap ke arahnya. Mereka terlihat sedikit terkejut. Dia jadi merasa bersalah karenanya.
“Merry… K-Kamu waktu itu cuma sedang melakukan apa yang perlu dilakukan. Itu sebabnya kamu bersikap seperti itu. Kamu melakukannya demi kami. Kamu tahu bagaimana kondisinya. Jadi kamu lakukan ury. Ya. Gitu, kan…?”
“Iya, tapi…”
“Hah? Tapi?”
“Kalau aku nggak punya sisi seperti itu dalam diriku… kurasa aku gak akan bisa bersikap seperti itu. Mungkin, memang seperti itulah diriku yang sebenarnya.”
“Masa, sih? Yume, dia ngerasa kamu anaknya baik, lho, Merry-chan. Karena kamu baik. Hmm. Yume emang cuma bilang ‘baik,’ tapi ya, kalau kamu nggak baik—Yume nggak yakin kamu bakal ngelakuin hal itu kalau kamu bukan orang yang baik.”
Iya. Aku paham. Aku mengerti maksudmu, Yume, tapi… tolong, hentikan!
Kalau kau bicara seperti itu langsung ke orangnya, kebanyakan bakal malu, tahu! Lihat saja Merry—dia jelas-jelas malu sekarang!
“U-Um…” Moguzo mungkin ingin meredakan suasana, tapi dia tak menemukan cara yang pas, jadi dia hanya memegangi kepalanya dan mengeluh pelan.
Baiklah! Saatnya aku bertindak sebagai pemimpin!
Haruhiro menyemangati dirinya sendiri, tapi tak bisa memikirkan ide yang bagus.
“Y-Yang penting adalah…!”
Shihoru. Shihoru turun tangan. Terima kasih, Shihoru.
“Y-Yang penting… kamu mau bicara sama kami… kurasa. Kamu pengin bicara… Dan, um, itu… itu bikin aku senang.”
“Aku tahu, kan?!” Haruhiro langsung tersenyum lebar dan berseru. Lalu langsung menyesal telah melakukannya.
Aku ingin jadi orang yang lebih tenang dan dewasa suatu hari nanti. Tapi kayaknya susah.
“…Iya. Benar juga. Sebagai teman seperjuangan, aku juga senang, tahu? Maksudku, gimana ya. Apa yang kita bicarakan itu penting, sih. Tapi bukan cuma itu. Yang penting juga… lingkungan atau suasananya? Kita butuh tempat atau kondisi yang bikin kita bisa saling bicara. Entah kita punya itu atau enggak, itu dulu yang harus dipikirin, mungkin? Err… Aku kayaknya ngomong ngawur, ya? Gak banget deh…”
“Enggak ‘gak banget’.” Merry menggeleng pelan. Lalu, dengan suara tegas, dia berkata, “Kamu itu bukan ‘gak banget,’ Haru.”
“…Serius?”
Waduh. Aku merasa bakal senyum-senyum sendiri nih.
Haruhiro memaksa dirinya tetap menjaga ekspresi datar. Dia yakin kelopak matanya sedang berkerut sekarang.
“Y-Yah… Ya. Ya, kurasa memang begitu, ya? Meremehkan diri sendiri seperti itu, jelas nggak baik. Tapi, kalau aku punya rasa percaya diri tanpa dasar seperti Ranta, itu juga bakal jadi masalah. P-Pokoknya soal kejadian di bengkel tadi, nggak ada yang menganggap itu aneh. Jadi nggak usah khawatir. Lagi pula, lihat saja situasinya. Aku juga nggak begitu paham si Riyosuke itu gimana orangnya, tapi kupikir… kita memang perlu ngancem dia sampai segitunya.”
“Soal itu,” Merry mendesah pelan. Tatapannya tiba-tiba jadi… lebih tajam? “Aku sudah memikirkannya. —Mungkin aku belum cukup tegas. Orang-orang seperti dia nggak akan belajar kalau nggak dipaksa. Aku rasa kita harus tetap mengawasinya. Dia perlu dikendalikan.”
Haruhiro bergidik. Mungkin memang beginilah diri Merry yang sebenarnya, pikirnya.
Tapi ternyata, Merry benar-benar tepat. Saat mereka sudah mengumpulkan Ranta dan kembali ke Workshop Masukaze, mereka mendapati Riyosuke si pandai besi sedang bermain-main dengan kepala Trigon.
“A-Ah! B-Bukan! Ini cuma… aku cuma ngilangin stres aja! Aku bentar lagi juga mulai kok—!”
“Cepat selesaikan,” perintah Merry dingin, tanpa perlu meninggikan suara. Jujur saja, Merry itu benar-benar menyeramkan kalau sudah begini. Rasanya Haruhiro sendiri pun tak akan bisa meniru sikap itu, meskipun dia mencoba. Mungkin itu memang sesuatu yang sudah ada sejak dia lahir?
Diri aslinya, ya…?
Tapi meskipun begitu, Merry bukan cuma itu saja.
Bukan hanya Merry. Setiap orang memiliki banyak sisi. Mereka berubah tergantung situasi, dan orang pun bisa berubah seiring waktu. Di masa depan, mungkin Ranta akan berhenti jadi menyebalkan—Oke, tidak, yang itu rasanya mustahil.
Bagaimanapun juga, mereka memutuskan untuk bergantian berjaga di bengkel pandai besi, mengawasi Riyosuke bekerja. Kalau tidak, dia mungkin takkan pernah menyelesaikannya. Mereka tidak bisa turun ke lapangan sebelum senjata Moguzo selesai.
“Baik! Aku ngerti! Aku ngerti, oke?! Aku tinggal kerjain, kan?! Ya udah, aku kerjain! Nggak usah disuruh-suruh! Aku juga udah niat dari awal…!”
Riyosuke akhirnya mulai bekerja. Haruhiro tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, Kenapa juga marah-marah ke kami…? Tapi begitu dia mulai, dia tidak teralihkan sedikit pun. Ia dibantu tiga orang murid. Menyaksikan keempatnya bekerja di bengkel itu memunculkan rasa puas tersendiri. Si master mengayunkan palunya seolah kerasukan.
“Itu bukan karena master kami lambat,” bisik salah satu murid yang lebih muda, “Cuma butuh waktu buat mulai. Bisa dibilang, dia itu seniman. Tangannya nggak akan bergerak sampai dia nemu inspirasi. Tapi—dan aku tahu aneh rasanya bilang begini sebagai muridnya—hasil kerjanya benar-benar solid.”
Haruhiro tak tahu banyak soal dunia para pengrajin, tapi dunia sukarelawan tempur pun penuh dengan berbagai tipe orang. Mungkin dunia pengrajin juga sama.
Akhirnya, mereka tidak perlu menunggu sampai lonceng pukul enam sore berdentang. Senjata Moguzo selesai hampir satu jam lebih awal. Anehnya, senjata itu tidak terlihat terlalu berbeda dari saat digunakan oleh Death Spots. Namun, ukurannya sudah diperkecil dengan tepat.
“Nah!” kata Riyosuke dengan ekspresi paling pongah saat menyerahkan pedang itu kepada Moguzo. “Pekerjaan kelas atas! Coba pegang!”
“…Oke.” Moguzo meraih gagang senjata barunya. Saat itu juga, “Huh?!” ekspresinya berubah drastis. “A-Apa ini…?! Berat, tapi ringan?! Apa ini masuk akal…?!”

“Kamu bilang apa?! Moguzo, sini, kasih ke aku!” Ranta merebut pedang besar itu dari tangan Moguzo—namun, “Gwuh?!” ia langsung menjatuhkannya.
“B-Berat banget ini! Nggak mungkin kamu bisa bawa-bawa barang beginian, kan…?!”
Ranta memang tidak sebesar atau sekuat Moguzo. Sepertinya itu alasannya—tapi saat Riyosuke menjelaskan dengan senyum bangga, ternyata ada hal lain juga.
“Seberapa mudah sebuah senjata digunakan hampir sepenuhnya tergantung pada letak titik gravitasinya. Titik gravitasi itu memang sifat bawaan senjata, tapi tiap orang merasakannya berbeda! Intinya, untuk pedang besar ini, aku sudah mengatur titik gravitasinya supaya pas banget kalau dipakai dia! Kalau orang lain yang coba, ya bakalan repot! Tapi buat dia, meski berat, rasanya akan tetap ringan! Gimana, keren kan?!”
Haruhiro benar-benar terkesan, dan Moguzo pun tampak sangat senang. Shihoru mengangguk mendengar penjelasannya, sedangkan, “Fweh…” Yume tampaknya tidak benar-benar mengerti, tapi Ranta langsung minta Riyosuke membuatkan senjata juga untuknya.
“Ahaha! Sabar dulu. Sebelum itu, aku tagih bayaranku dulu dong. Ini kan usaha juga.”
Saat Riyosuke mengedip nakal, Moguzo refleks berkata, “Oh, iya!” dan hampir menyerahkan uangnya—tapi Merry menghentikannya.
“Tunggu. Soal itu.”
“…Y-Ya?” Riyosuke langsung tampak lemas. Ia kelihatan cukup takut pada Merry.
“Setelah kamu jelas-jelas melanggar tenggat waktu, kamu masih berani menagih 40 perak seperti yang kamu sebut di awal?”
“…T-Tidak boleh, ya?”
“Pikir sendiri.”
“…Aku nggak bisa… ya? Ya, tentu saja nggak. Masuk akal sih… Nggak, aku juga udah sempat kepikiran bakal gitu. Hahaha… Oke, tiga puluh delapan…”
“Haaaah?”
“Tiga puluh tujuh—”
“Pikirin baik-baik.”
“Tiga puluh… silver.”
“Mungkin nggak apa-apa? Kalau emang kamu ngerasa itu harga yang pas.”
“…Tolong jadi dua puluh lima silver, ya.”
Dan begitulah, Moguzo mendapatkan pedang milik Death Spots, dengan diskon berkat Merry. Sudah jelas kalau percakapan yang sedikit mengancam tadi cuma akting dari Merry demi membantu Moguzo. Haruhiro tahu itu. Memang agak menakutkan juga, tapi kalau Merry nggak sampai segitunya, efeknya pasti nggak akan terasa. Dia pasti sudah berusaha keras terdengar benar-benar mengintimidasi.
Moguzo bilang dia akan mentraktir mereka makan malam yang mahal, jadi mereka semua berkumpul di desa kios yang tak jauh dari kota para pengrajin.
“Whew! Gila sih, Merry! Nggak pernah liat orang seketakutan itu. Lucu banget!”
“Ranta, woy…”
Haruhiro awalnya mau menegur Ranta, tapi Merry malah tertawa kecil.
“Itu negosiasi yang lebih cerdas daripada yang bisa kamu lakuin, kan?”
“Heh. Aku tuh tipe yang main tekan terus. Bukan tipe-tipe cerdas gitu dari awal. Yang penting hasil akhirnya.”
Merry kelihatannya juga nggak terlalu terganggu lagi. Apa itu artinya dia sudah bisa move on? Mungkin karena dia udah terbuka soal perasaannya ke mereka, jadi bebannya sedikit terangkat. Kalau memang begitu, Haruhiro ikut senang. Sebagai teman seperjuangan, itu sudah cukup buatnya.
“Yume, aku kepikiran…” bisik Shihoru ke Yume, “Soal rumah penginapan. Kayaknya… nggak masalah, deh. Untuk sekarang…”
“Hmm. Iya. Yah, nggak perlu buru-buru juga, kan.”
Dia bukannya bilang begitu karena Merry menyeramkan… kan?
Mereka berbisik cukup pelan, tapi sepertinya Ranta sempat mendengarnya. Dia menyeringai, lalu bergumam pelan, entah apa. Seperti, Aku belum sempat lihat dengan jelas, atau semacamnya.
“…Belum sempat lihat dengan jelas?”
“Huh?”
Tatapan Haruhiro bertemu dengan mata Ranta.
Belum sempat lihat… dengan jelas? Maksudnya apaan…?
“…Oh…” Saat Haruhiro menyadarinya, Ranta buru-buru memalingkan wajah. “…Jadi bukan soal kenangan, atau soal kesepian… tapi itu…?”
Tiba-tiba, Ranta merangkul bahu Haruhiro dan Moguzo, lalu tertawa dengan gaya mesum yang keterlaluan.
“Artinya keseruannya masih akan terus berlanjut! Jangan paksa aku ngucapin, malu tahu!”
“…Kau yang memalukan.”
“Y-Ya…”
Dukung Terjemahan Ini:
Jika kamu suka hasilnya dan ingin mendukung agar bab-bab terbaru keluar lebih cepat, kamu bisa mendukung via Dana (Klik “Dana”)